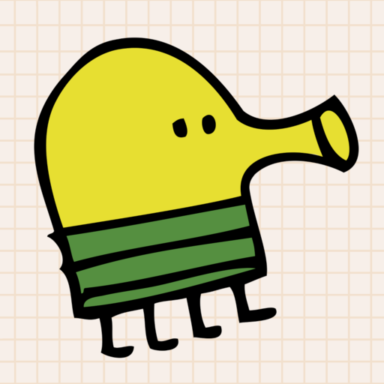MENUJU NASIONALISME KAPITALIS ?
Esai-Esai Sosial-Politik (1)
Oleh Aprinus Salam
Daftar Isi
(1) Menuju Nasionalisme Kapitalis
(2) Di Balik Tahun Politik
(3) Makar Sosial
(4) Warga Negara Indonesia
(5) Mengonsumsi Mitos dan Hoax
(6)Yang Tua, Yang Tamak
(7) Wajah Senyum Tak Bersalah
(8) Lelah Menjadi Bangsa
(1)MENUJU NASIONALISME KAPITALIS
Kekuatan besar dalam suatu negara terletak pada masyarakatnya yang diam.Dalam proses sejarah budaya yang panjang, dalam berbagai prosesi kekuasaan dankonflik, banyak orang memilih diam. Mereka memilih diam karena tidak ingin adakegaduhan yang tidak penting. Lebih dari itu, mereka memilih diam karena merekamemiliki pendapat sendiri, sesuai dengan proses negosiasi yang ada dalam ruangkesadaran diri dan pikiran mereka masing-masing.Persoalannya, hal apa saja yang bernegosiasi dalam ruang kesadaran masyarakatdiam tersebut? Bagaimana proses negosiasi itu terjadi? Dalam hal ini, ada empathal yang bernegosiasi, yakni nilai-nilai lokal (tradisi), nilai-nilai agama, nilai-nilainasional, dan nilai-nilai kapitalisme. Setiap nilai memiliki karakter dan tujuantersendiri di dalam dirinya. Modernisme dan globalisme tentu perludiperhitungkan, tetapi untuk keperluan di sini diwakili oleh kapitalisme.
Karakter Nilai
Nilai-nilai lokal atau tradisi, dalam sejarahnya, terbukti adaptif. Lokalitas terbiasa menerima banyak hal. Hal pertama yang “diterima” lokalitas adalah agama. Itulah sebabnya, karakter agama di setiap lokal berbeda-beda. Ada lokal yang mengadopsiagama secara dominan, tetapi ada lokal yang mempertahankan nilai lokalitasnyasecara kental. Di beberapa lokal di Jawa, misalnya, nilai-nilai lokal yang memegangteguh pada harmoni, pada kepantasan dan ketidakpantasan, masih menjadi kendaliyang penting.
Agama memiliki rukun-rukun tersendiri yang khas. Rukun-rukun tersebut memberikeyakinan dan identitas, sehingga agama bisa memasukkan dan mengeluarkan seseorang dalam identitas dan keyakinannya. Ada janji “keabadian” di dalamnya yang tidak dimiliki nilai lain. Sekali lagi contoh, orang Jawa, selamanya tetap Jawa,karena tidak ada aturan yang bisa mengeluarkan atau memasukannya. Akan tetapi,suatu ketika bisa saja orang Jawa tersebut beridentitas dengan agama yangberbeda.Dalam sejarah Indonesia, nasionalitas mencoba mengakomodasi nilai-nilai lokal,agama, dan kapitalisme/modernisme. Hal itu dapat dengan mudah dilihat dalam
Pembukaan UUD ’45. Di luar nilai lokal, agama, dan kemodernan, sesuatu yang khas dari nilai nasional terletak pada persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuanNKRI menjadi sangat penting. Dalam logika yang sama, tentu seseorang bisa sajaberpindah warga negara dan itu mengeluarkannya dari nilai persatuan dannasionalitas.Sementara itu, kapitalisme memiliki kemampuan menyerap semua hal sejauhdalam kalkulasinya menguntungkan dan meningkatkan kinerja dirinya. Artinya,kapitalisme mendorong masyarakat untuk selalu melakukan kalkulasi rasionalekonomis apakah tindakan, prilaku, atau keputusan mereka akan menguntungkanatau tidak.
Kita tahu, aspek sekuler memegang kendali penting. Dalam skala yanglebih besar, wajah kapitalisme bisa beragam karena kemampuannya memodifikasinilai-nilai yang diserapnya untuk dijadikan komoditas.
Negosiasi Karakter
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lokalitas dapat beradaptasidengan apa saja. Dalam posisi itu, lokalitas menjadi bagian-bagian khusus, baikdalam nasional, agama, ataupun kapitalisme/modernisme. Kedirian dan kecirian(lokalitas seseorang) bisa muncul dalam wajah nasional, agama, ataupun sebagaimasyarakat modern. Lokalitas bermetamorfosis terus menerus sebagai sesuatuyang menjadi ciri-ciri masyarakat tertentu.Agama bisa beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan nasional, tetapi sulitberadaptasi dengan kapitalisme yang rasional dan sekuler. Ada keyakinan terhadaphal-hal mistis, keberadaan dan peranan Tuhan/Allah, yang dalam setiap agamabersifat universial, tetapi tetap saja rukun-rukun dalam setiap agama adaperbedaan. Itulah sebabnya, banyak negara atau masyarakat di muka bumi ini tidakmemposisikan rukun-rukun keagamaan sebagai praktik berbangsa atau bernegaraKalau melihat perjalanan politik Indonesia, maka diketahui bahwa masyarakatIndonesia memilih pegangan pada nilai nasional yang didukung oleh nilai-nilai lokal.Hal itu dapat dilihat dari berbagai hasil pemilu di tingkat nasional. Kalau dalam perjalanan ekonominya, Indonesia memilih modernisasi, dalam kendali kapitalisme,atau biasa kita sebut sebagai pembangunanisme.Memang, di tingkat daerah terjadi berbagai variasi. Hal tersebut bergantungproses-proses negosiasi di antara berbagai kekuatan nilai tersebut di lokal masing-masing. Ada daerah yang tetap mengedepankan nilai-nilai nasional (nasionalitas),ada daerah yang masih berpegang teguh pada kekuatan nilai dan tradisi lokal,tetapi ada daerah yang kandungan agamanya cukup kuat.
Nasionalisme Kapitalis.
Kembali mencermati situasi Indonesia, baik dalam rentang sejarah politik, ekonomi,sosial, dan budaya, maka proses negosiasi di antara empat nilai tersebut secara relatif dimenangkan oleh “gabungan” nasionalisme dan kapitalisme.
Persoalannya, apa kaitan “nasionalisme kapitalis” tersebut dengan masyarakat diam? Kaitannya,masyarakat kelas menengah cukup menikmati situasi tersebut, dan merekamemilih diam. Kondisi-kondisi yang stabil jauh lebih mengundungkan daripada adagejolak.Tentu ini kesimpulan terbatas, karena bagaimanapun proses-proses negosiasi ituterus berlangsung, bergantung pada kondisi yang berkembang, dan berbagaiperistiwa dengan komposisi nilai yang berbeda. Berbagai hal tersebut terus dicernadan diikuti dengan diam dan secara diam-diam. Merekalah yang diam-diam justrumenentukan ke mana arah keputusan-keputusan yang akan diambil. Merekaadalah mayoritas yang rasional, cinta tanah air, selalu melakukan perhitungandengan cermat, dan memilih diam sambil terus bekerja.
(2)DI BALIK TAHUN POLITIK
Kita cemas menghadapi berjalannya waktu, terutama dua tahun ke depan yangsebagian orang mengatakan tahun politik. Penamaan tahun politik dikarenakansebagian besar menduga akan terjadi kontestasi yang keras karena tahun-tahuntersebut dianggap bagian dari tahapan penting proses-proses transisi dan ujianpolitik reformasi dan demokrasi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalahmempertanyakan ruang budaya apa di balik kontestasi politik tersebut.Pada masa Orde Baru, kita tidak cukup mengenal apa yang disebut sebagai tahunpolitik. Pada waktu itu, proses-proses politik telah diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya sudah dapat diduga. Orde Baru telah berhasil membangun ruang “budayapolitik” sehingga persai
ngan berjalan seperti sinetron populer yang tidak menarik,kontestasi bersifat permukaan untuk memberi kesan demokrasi, dengan ending cerita yang sudah diketahui.
Pada masa-masa itu, masyarakat Indonesia belum cukup punya budaya demokrasi.Hal itu juga didukung rata-rata pendidikan yang belum baik, informasi danindoktrinisasi masih bersifat linier dari atas ke bawah, aparatus negara masih sangat digdaya dan ditakuti, wacana-wacana tandingan/ alternatif dibungkam,budaya teknologi belum massif. Kondisi tersebut mengkonstruksi cara berpikirparsial. Dengan berberapa kejadian kekerasan negara, berupa penangkapan ataupenghilangan warga, telah cukup menimbulkan efek panoptik. Ruang budaya yangterkondisi adalah budaya ketakutan.Dalam budaya ketakutan, segala hal lebih mudah dikendalikan dan diatur. Di balikitu, banyak orang mencari selamat untuk dirinya masing-masing, berusaha keluardari ketakutan. Efek dari budaya ketakutan tersebut adalah banyak pihakmengambil muka untuk menjadi agen-agen negara sebagai strategi membebaskandiri dari ketakutan. Budaya ketakutan menimbulkan sikap-sikap oportunis. Politikberjalan hambar dan serba formalitas.Kini, kondisi tersebut telah berubah, tentu tidak semua. Dalam cengkraman masalalu, proses demokrasi berjalan walau compang-camping.
Rata-rata pendidikantentu sedikit meningkat. Kedigdayaan aparatus negara sebagian besar telah “dibarakkan”. Walaupun terdapat aturan main politik yang cukup ketat, tetapi dengan canggihnya teknologi android yang massif, wacana-wacana tandingan tidaklagi bisa dibungkam. Negara tidak bisa seenaknya melakukan kekerasan. Budayaketakutan telah sangat berkurang.
Kemungkinan Benturan.
Dalam kondisi tersebut, kejadian apa yang bisa kita perkirakan dengan tahun politikdi depan. Telah disinggung bahwa walau telah terjadi banyak perubahan, tetapitidak semua. Bagian yang masih akan bertahan adalah sikap-sikap bahkan karakteroportunis yang telah terbangun akibat sejarah politik masa lalu yang tidak hilangbegitu saja. Masalahnya adalah bahwa karakter itu berjalan dalam ruang budayapolitik yang berbeda.Oportunistik dalam ruang budaya ketakutan memunculkan efek mencari selamat.Akan tetapi, dalam ruang budaya yang serba terbuka, akibat teknologi digital/ internet, oportunisme akan sangat memalukan dan tidak memberi efek keselamatan.
Namun, sebagai karakter, resiko itu akan tetap dipilih oleh sebagianmasyarakat lebih sebagai satu strategi aji mumpung. Hal itu disebabkan tahunpolitik masih masuk dalam satu periode transisi.Di dalam masa transisi, orang mengambil resiko untuk sukses atau gagal. Padasesama yang mengambil keputusan aji mumpung, sangat mungkin akan terjadibenturan. Benturan akan berbahaya jika aji mumpung
tersebut berhasil mengelolaidentitas, karena yang terjadi adalah benturan antar-identitas. Identitas yang paling berbahaya adalah jika mengadopsi wacana atau simbol-simbol keagamaan. Orangberani mati dalam keyakinannya.
Hal lain, Indonesia, sebagai bagian dari tatanan global, terikat dengan berbagaipemainan kekuatan internasional, khususnya negara adikuasa. Berbagai perubahanyang terjadi pada konstelasi internasional, sangat berpengaruh terhadap bukansaja peta politik, tetapi bahkan ruang budaya di Indonesia. Salah satu yangsifnifikan adalah konstruksi kapitalisme global yang menghidupkan spirit kompetisi.Spirit kompetisi yang dimaksud adalah berbagai upaya untuk mendapatkankemenangan. Secara kultural ruang ini sangat berbeda dengan budaya Indonesiayang lebih mengedepankan kerukunan dan harmoni. Akan tetapi, ruang kompetisitelah terbentuk sedemikian rupa, dan mengondisikan masyarakat Indonesia untukmenjadi kompetitor-kompetitor. Hal yang sangat berbahaya adalah bahwa sebagaikompetitor kita dikonstruksi untuk siap menang, dan tidak siap kalah.Itulah sebabnya, wacana tandingan berbasis budaya perlu diperkuat jika kita tidakingin negara kita tambah compang-camping.
(3) MAKAR SOSIAL
Beberapa kali saya diminta menjadi saksi ahli bahasa untuk beberapa kasus,terutama apakah seseorang telah melakukan makar dari segi bahasa. Ada yangsaya penuhi ada yang tidak saya sanggupi. Hal awal yang menjadi pertimbangansaya untuk menyanggupi atau tidak, apakah saya bisa menjelaskan bahwa kasustindak berbahasa atau bertutur tersebut sebagai makar atau tidak. Kalau sayamerasa tidak mampu menjelaskan, saya tidak menyanggupi.Pertimbangan kedua adalah apakah ada kejahatan berbahasa/bertutur didalamnya. Kejahatan bisa berupa ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan sebagainya,dan merugikan atau menzalimi pihak lain. Pihak lain yang dirugikan tersebutterutama pihak yang lemah dan dilemahkan.
Jika kedua hal tersebut terpenuhi,biasanya saya menyanggupi. Terkait dengan hal kedua, siapa yang saya bela, dan bagaimana bentuk dan sifatkasus tersebut. Misalnya, ada dua kasus yang berbeda. Seorang penyayang hewanmembawa piaraannya ke dokter. Dokter memberikan obat. Akan tetapi, sebulankemudian hewan tersebut mati. Si penyayang hewan yakin sekali jika dokter telahsalah memberi obat. Si penyayang marah dan memaki dokter hewan tersebut.Ujaran si penyayang hewan dituntut oleh dokter hewan bersangkutan. Pada kasustersebut saya tidak sanggup membela si penyayang hewan.
Kasus kedua, ada sorang buruh wanita yang dianggap melecehkan pemilikperusahaan dengan kata-kata yang dianggap kasar. Setelah kasusnya saya pelajari,saya bersedia membela. Bukan saja si buruh wanita rendahan tersebut memanglayak dibela, tetapi, di balik itu, ungkapan kasar seorang buruh bisa dianggapungkapan orang kecewa dan berusaha melakukan semacam kritik, tetapi dia tidakpunya alat bahasa yang cukup. Dalam konteks itu, kritik orang kecil terhadap orangkuat tidak sama dengan makar atau pelecehan sosial.
Makar
Hal di atas adalah ilustrasi bagaimana memahami tindak berbahasa, baik dalamkonteks pelecehan, penghinaan, penzaliman, atau sesuatu yang mengarah makar.Ihwal awal penggunakan kata makar lebih dalam konteks politik dan kekuasaan,yakni tindakan bertutur, berbahasa, atau melakukan berbagai kegiatan, dandimaksudkan untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah yang syah. Kemungkinankedua tindakan berbahasa dan melakukan berbagai kegiatan dalam rangkamerongrong kekuasaan yang sah. Pemerintah yang sah memiliki landasan hukumuntuk menghukum mereka yang berbuat makar tersebut.Namun, bisa saja sebetulnya seseorang dengan sengaja atau tidak melakukantindakan berbahasa atau melakukan kegiatan yang disebut sebagai makar sosial.Apa itu makar sosial?
Makar sosial adalah suatu tindakan berbahasa/bertutur ataumelakukan berbagai kegiatan yang mengganggu, merusak, atau merugikan keberlangsungan tatanan sosial. Tatanan sosial yang dimaksud adalah sesuatu nilai,norma, sistem, dan berbagai konvensi yang dipraktikkan bersama dalam suatumasyarakat tertentu. Artinya, tatanan sosial untuk setiap masyarakat berbeda-beda.Secara umum, katakanlah tatanan tersebut tatanan sosial Indonesia.
Hal itu dimaksudkan sebagai satu nilai, norma, sistem, dan berbagai konvensi lainnya yangdiakui dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Siapa saja yang mengganggu,merusak, atau merugikan praktik pelaksanaan tatanan sosial maka orang tersebuttelah melakukan tindakan makar sosial, dan layak diperkarakan.Dalam hal ini, hal yang bisa dianggap tindakan makar sosial adalah tindakan yangmerugikan atau menzalimi masyarakat. Memang, batas masyarakat di sini menjadiproblematik.
Di sini pula kelemahan untuk menilai apakah seseorang telahmelakukan makar sosial atau tidak karena adanya kesulitan untuk mengklaim siapamasyarakat itu. Akhirnya, orang yang telah melakukan makar sosial menjadi sulitdituntut karena tidak jelas siapa yang bisa dituntut dan menuntut.Padahal, saat ini, cukup banyak yang telah melakukan makar sosial. Mereka adalahpara penghasut, penyebar hoaks dan berita palsu, mereka yang memfitnah,mereka yang berwacana tentang kebencian, mereka yang suka menuduh danberprasangka. Apalagi jika itu berkaitan dengan tatanan sosial beragama, bersuku-bangsa, hubungan dan nilai kemanusiaan, maka para makar sosial itu sungguhberbahaya.Maka perlu ada sangsi moral dan sosial, perlu ada wadah hukum yang jelas,bagaimana menyikapi orang yang terbukti telah melakukan makar sosial. Kita haruspunya kekuatan untuk melawan para pemakar sosial.
(4)WARGA NEGARA INDONESIA
Munculnya polemik atau wacana pribumi non-pribumi memperlihatkan lemahnyakonsep negara sebagai ikatan yang menyatukan warga Indonesia. Hal ini perludimaklumi mengingat jika dalam beberapa hal pemerintah nasional merupakanrepresentasi negara, maka dalam proses dan sejarah yang cukup panjang, wargamerasa tidak bangga dan tidak terikat dengan apa yang disebut negara.Kita perlu paham bahwa secara empirik hal yang dialami sehari-hari oleh warga adalah,
pertama, ikatan keluarga, kekerabatan, itu artinya kedekatan garis keturunan /darah.
Kedua, ikatan perkampungan/desa atau ikatan perkawanan/ikatan kesukuan.
Ketiga, ikatan kehidupan sosial dan terutama keagamaan.
Keempat, ikatan sejarah kebersamaan dalam aras ketiga ikatan tersebut yang biasanya bersifat lokal.Artinya, ikatan pengalaman bernegara sungguh sesuatu yang secara empirik tidakbegitu dialami, kecuali mungkin hanya dikenalkan lewat pelajaran-pelajaran disekolah.
Pada satu satuan waktu dan ruang yang sama, tidak semua wargamengalami secara empirik dahsyatnya peristiwa kemerdekaan. Pada satu satuanwaktu dan ruang yang sama, tidak semua warga mengalami makna dan peristiwa1965, 1998, dan berbagai peristiwa nasional lainnya.Berdasarkan itu, kita bisa membayangkan banyak warga merasa tidakberkepentingan dengan apa yang disebut sebagai negara nasional Indonesia. Halitu diperburuk dengan buruknya pemerintah dalam membangun kinerja dirinya,dan buruknya pemerintah dalam membangun rasa kebanggaan untuk menjadiwarga negara Indonesia. Pendek kata, buruknya pemerintah dalam membangunkinerja dirinya, menyebabkan warga tidak percaya dengan pemerintah sebagairepresentasi negara.
Soal Pribumi
Jika hal pribumi dimaksudkan sebagai penduduk asli, tidak ada warga asli diNusantara ini. Maksudnya, tidak ada warga atau orang yang tiba-tiba hadir di bumiNusantara. Sebagai manusia keturunan Adam, nenek moyang kita entah datangdari mana, dan kemudian berdomisili di Nusantara dan/atau Indonesia.
Dengan demikian, yang ada adalah pendatang yang lebih dulu, dan pendatangkemudian. Mereka beranak pinak, menyebar ke seluruh Nusantara. Percampurandan pengalaman keempat hal empirik sebelumnya, ditambah faktor geografi,geososial, geoekonomi, geopolitik, menyebabkan munculnya perbedaan bahasa,perbedaan kebiasaan sehari-hari, termasuk soal kuliner/pangan, pakaian,perumahan, dan sebagainya.Oleh karenanya, isu pribumi atau yang merasa asli, sangat tidak relevan. Saat ini,tidak ada lagi yang asli di muka bumi ini. Yang ada adalah keturunan danpercampuran yang bermukim dan membentuk satu satuan masyarakat tertentu didaerah tertentu. Masalahnya adalah ikatan satuan apa yang paling berpengaruhdalam satuan masyarakat tertentu dalam daerah tertentu itu. Di sinilah persoalanperbedaan menjadi muncul.
Soal Identitas
Isu pribumi yang berimplikasi pada referensi identitas merupakan persaingan padatataran empat aras empirik di atas. Ada daerah-daerah tertentu, dalam kontestasiyang panjang, akhirnya memilih basis bangunan masyarakat dan budayanyaberdasarkan etnisitas, tetapi ada pula yang berbasis agama, atau bebasiskekerabatan dominan.Berdasarkan itu pula, kita bisa memahami apa yang terjadi di Aceh, Minang,Melayu, Jawa, Ambon, Papua, Bali, Bugis, Makasar, dan sebagainya. Pengalamanhidup berbeda berdasarkan empirik lokalitasnya, menyebabkan referensi identitasberbasis negara sungguh lemah.
Kalau kita ditanya atau bertanya, maka konteksdasar yang berkaitan dengan identitas tersebut adalah, misalnya, bahwa kita orangJawa, beragama Islam, atau Katholik, bukan orang Indonesia.Referensi identitas berbasis agama, suku, atau bahkan ras, sekali lagi,memperlihatkan bahwa negara (Indonesia) tidak berhasil mengatasi ikatan-ikatanempirik emosional dan lokal untuk bersama-sama menjadi warga bangsa negaraIndonesia. Memang, tentu ada ikatan nasionalisme atau ikatan berbasis ideologiPancasila. Kadang nasionalisme hanya berarti jika itu dihadapkan dan berhadapandengan negara lain.
Sementara itu, ikatan keberadaan Pancasila tidak jarang berhadapan dengan basis ideologis lain, dan terutama besumber agama.Bagaimana supaya negara menjadi ikatan yang kuat bagi basis kewargaan danidentitas? Tidak ada jalan lain bahwa negara harus kuat dalam menegakkan hukum.Dengan itu negara akan mendatangkan kepercayaan warga. Negara berbasishukum harus sangat kuat menegakkan multikulturalisme, menegakkan pemerintahanti-korupsi, negara yang mampu membebaskan kemiskinan, dan pemerintah yangbersih dan jujur. Tanpa itu, sekarang kita mengalaminya.
(5)MENGONSUMSI MITOS DAN HOAX
Bila disederhanakan, mitos itu ada dua, yakni mitos tradisional dan mitos modern.Mitos tradisional berkaitan dengan kepercayaan populer tentang keberadaan dan “kekuatan” sesuatu yang bersifat supranatural, mungkin magis, mungkin pula dalam bentuk kearifan dan/atau keyakinan lokal, yang dianggap bisa berperansecara positif atau negatif dalam kehidupan manusia.
Hal tradisi(onal) dimaksudkan bahwa kita atau masyarakat merupakan bagian darisejarah kebudayaan yang telah berlangsung hingga hari ini, dan kita hidup di dalammitos itu. Ada mitos tradisional yang relatif kondusif dan fungsional terhadapkehidupan. Akan tetapi, ada mitos tradisional yang secara relatif mengungkung,walaupun kita sering tidak mempersoalkannya.
Karena kadang kita menjadi tidaksadar bahwa hal itu berjalan dan dirasakan sebagai sesuatu yang natural.Mitos modern adalah narasi-narasi pasca tradisi(onal) yang diciptakan oleh orang-orang/masyarakat (modern) untuk kepentingan tertentu. Tentu ada banyak mitosmodern yang relevan dalam kehidupan yang juga modern, seperti hubungan antarakerja keras dan rezeki, ketekunan dan keberhasilan, dan sebagainya.
Kita tidakmempersoalkan benar salahnya mitos.Dalam kehidupan kita, kedua mitos itu, baik mitos tradisional maupun modernhidup berdampingan, dan bahkan bersaing. Seseorang bisa saja mengeluarkanuang ratusan juta rupiah untuk mengonsumsi benda-benda antik karena narasimitos yang berkaitan dengan benda tersebut. Sebaliknya, bisa saja seseorangmengonsumsi benda-benda modern, karena mitos prestise dan simbolik dari bendamodern tersebut, dan bersedia mengeluarkan uang yang sangat banyak.
Kita memang tidak bisa keluar dari mitos. Mitos tentang keunggulan ras, tentangkecantikan, tentang orang suci, dsb., mungkin kita berusaha menolak. Akan tetapi,ketika kita menolak mitos tersebut, biasanya kita memakai mitos lain/tandingan,dan masuk ke dalam mitos baru yang kita percaya untuk menolak mitos dominan tersebut.
Mitos atau Hoax ?
Baik mitos tradisional maupun modern biasanya muncul dalam berbagai bentuk.Hal yang menarik saat ini adalah bagaimana kedua mitos tersebut muncul dalamberbagai bentuk meme ataupun dalam berbagai ungkapan verbal yang beredarsecara viral. Kedua bentuk mitos yang dikemas dan diviralkan tersebut, bisa saja (1)mengukuhkan mitos, dan (2) mendekonstruksi, atau paling tidak menggangguingatan dan kesadaran kita.Terlepas dari soal salah benar, viral dalam kategori mengukuhkan mitos agak sulitdimasukan ke dalam kategori hoax . Hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, kearifan lokal, petuah-petuah, pribahasa, dalam berbagai penampilandan ekspresinya tidak bisa dimasukan ke dalam kategori
hoax.
Terdapat keyakinan dan kepercayaan bersama tentang mitos itu sendiri, walaupun sangat mungkinsecara individual, karena keyakinan dan posisi sosial yang berbeda, seseorangmengkategorikannya sebagai hoax.
Yang menarik adalah kategori viral yang diandaikan semacam “dekonstruksi”, ataudengan “niatan” mengganggu atau melawan. Terdapat dua kemungkinan. Pertama, mungkin karena perbedaan perspektif dan posisi sosial, maka dekonstruksi berbasisrasionalitas dan etika tertentu, ini juga sulit untuk disebut hoax.
Kedua, viralitasdengan niatan mengganggu, melawan, mitos baru yang ada, dan sangat mungkinberbasis ideologi dan posisi sosial tertentu, maka viral ini bisa terjerumus menjadin hoax.
Persoalannya, viral yang terjerumus ke dalam hoax bisa menjadi sangat berbahaya.Hal ini berkaitan dengan institusi pengetahuan dan memori kita. Seperti diketahui,institusi pengetahuan dan memori kita selama ini (sebelum era gejet dan viralitas)berdasarkan referensi yang terbaca dan dapat dipertanggungjawabkan, atauberdasarkan informasi/tulisan kepakaran tertentu.Hal itu tentu tetap ada masalah di dalamnya, yakni kaitannya dengan kuasa rezimdominan dan hegemonik tertentu. Akan tetapi, paling tidak, institusi pengetahuandan memori kita masih bisa dilacak sumber-sumbernya.
Masih bisa dipersoalkan,masih bisa direvisi jika kuasa rezim melakukan proses-proses demokratisasiterhadap pengetahuan dan memori itu sendiri.
Akan tetapi, jika institusi pengetahuan dan memori kita berdasarkan dan bersandar pada hoax, yakni ketika referensinya tidak bisa dilacak, ahistoris, irrasional, maka bisa dibayangkan tingkat kerusakan pengetahuan dan memori kita. Yang lebih berbahaya lagi, kita tidak tahu bahwa sandaran institusi pengetahuan dan memori kita itu hoax. Saya merasa kita sedang dalam situasi tersebut. Aduh dik!.
(6)YANG TUA, YANG TAMAK
Konstelasi kekuasaan di Indonesia, memang tidak separah seperti yang digambarkan film Curse of the Golden Flower, sebuah film yang disutradarai ZhangYimou. Diceritakan dalam film yang bersetting
tahun 900-an itu, bagaimana dilingkaran kekuasaan kerajaan (China), raja yang telah lama berkuasa, permaisuri,anak, paman, dan beberapa petinggi melakukan berbagai intrik dan tipu muslihat busuk. Mereka, secara diam-diam dan dalam berbagai cara, saling menjahati dan membunuh, berebut kekuasaan untuk menjadi penguasa.
Di puncak konflik, akhirnya sang raja (lama) dengan indah dan sukses membunuhpesaingnya, yakni permaisuri, sebagian jenderalnya, bahkan anak-anaknya yang berpotensi merebut kekuasaan sang raja kelak. Sang raja tetap bersinggasana,dengan memegang kekuasaan tanpa tanding, tanpa mengetahui bahwa sebetulnyarakyatnya sudah sangat muak dengan raja zalim itu.Tentu dalam sebuah cerita selalu ada tokoh baik. Tokoh baik itu adalah sangpangeran, anak putra raja dan permaisuri. Pangeran itu berilmu sangat tinggi, cerdas, dan amat tangguh.
Berbagai peperangan dalam membela raja (Ayahnya)selalu ia menangkan. Tak pelak, salah satu kekuatan dan kebesaran kerajaan harusdiatribusikan kepada jasa-jasanya.Kelemahan pangeran muda itu, pertama, ia amat mencintai dan menghormatiorang tuanya. Kedua, ia lebih sebagai seorang satria daripada seorang politisi atauintelektual.
Kelemahan pertama membuat ia tidak tahu jika ia “dikerjain” oleh orang tuanya. Kelemahan kedua, membuat ia juga tidak tahu ke mana arahperkembangan politik kekuasaan.
Bahkan di akhir cerita ia terpaksa memakan buah simalakama, membela Raja iahidup, ibunya yang mati. Membela Ibu, ayahnya yang mati. Karena dia satria, diamemilih berkorban dirinya yang mati, dengan harapan ibu dan ayahnya tidak mati.Sang pangeran itu tidak tahu bahwa pada akhrinya ibunya juga dibunuh secaraperlahan-lahan, dengan sistem racun, oleh sang ayah.
Hal yang menarik bagi refleksi transisi dan prosesi kekuasaan di Indonesia adalahbagaimana film itu menggambarkan para orang tua, baik raja dan para jenderal, juga permaisuri, memanfaatkan anak-anak muda, bahkan anaknya sendiri, sebagai “alat” untuk melanggengkan ketamakan atas kekuasaan yang masih dan sedang dipegang para orang tua.
Belakangan ini di Indonesia salah satu isu yang cukup santer adalah kehendak adanya semacam prosesi dan transformasi kekuasaan dari para orang tua (usia diatas 60 tahun) kepada generasi yang lebih muda (dengan kisaran usia antara 35 hingga maksimal 50 tahun). Ada keengganan dari para orang tua memberikan roda kekuasaan kepada generasi muda dengan alasan anak muda belum siap.
Alasan itu tentu sangat meragukan, tidak siap dalam pengertian apa. Argumen itu, disamping lemah, juga mengada-ada. Paling tidak Rusia dan Amerika telah membuktikan bahwa kekuasaan di tangan anak muda, yang masih berusia sekitar 42 atau 43 tahun, tidak memperlihatkan sebagai satu kepemimpinan yang prematur. Bahkan di tangan anak muda, Amerika dan Rusia memberikan banyak perubahan yang lebih kondusif untuk masa depan dunia.
Memang, di lain pihak, anak muda (Indonesia) terkesan kurang “sakti”, baik dari segi modal dan terutama pengalaman (berperang atau berpolitik). Ada beberapa sebab mengapa hal itu terjadi. Pertama, dalam sejarah politik yang panjang, hanya baru beberapa tahun ini saja anak muda mendapat kesempatan untukberpartisipasi dalam politik kekuasaan.
Kita tahu, pada waktu rezim Orde Baru berkuasa, pendidikan dan pengalaman berpolitik anak muda dimandulkan.
Kedua, kekuasaan politik di Indonesia nyaris secara langsung berhubungan dengan kemewahan, kenikmatan, dan kekayaan. Di tengah krisis dan multi-dimensi kemiskinan massif, maka pilihan untuk menjadi penguasa (dalam segala levelnya) adalah pilihan yang masuk akal. Pilihan untuk tetap berkuasa sekaligus adalah pilihan dalam rangka menyelamatkan diri sendiri di tengah masa depan yang tidakpasti. Artinya, terdapat faktor aji mumpung dalam konstelasi kekuasaan seperti itu.
Orang yang duluan berkuasa, akan mempertahankan kekuasaannya sekuat mungkin.Hal yang perlu disadari bersama adalah bahwa sejarah keberadaan sebuah bangsa dan negara berjalan ke depan. Mati hidupnya sebuah negara dan bangsa ada di tangan anak muda, dan anak muda pada generasi-generasi berikutnya.
Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat diterima jika anak muda“dihalang-halangi” atau tidak segera diberi kesempatan untuk berlatih menjadi penguasa atau mendapat kesempatan memimpin dan mengendalikan negara sesuai dengan kehendak dan aspirasi zamannya. Sejarah tidak pernah berhenti,walaupun mungkin kadang-kadang bisa saja melompat-lompat.
Sebaliknya, anak muda yang bakal berkuasa, jauh hari sebelumnya haris pula memiliki kesadaran bahwa pelajaran tamak kekuasaan seperti diajarkan oleh generasi tua terdahulu harus segera dihentikan/dipotong. Kalau tidak, maka generasi kini tidak ada bedanya dengan generasi tua yang tamak kekuasaan.
Generasi muda kini, jika kelak berkuasa, haruslah tahu diri jika telah memimpin negara ini, sambil mengatur negara ini agar lebih baik, salah satu agenda yang juga perlu dipersiapkan adalah melakukan kaderisasi kepemimpinan.
Begitu kelak telah muncul generasi baru, maka generasi baru itu harus segera diberi kesempatan untuk memimpin dan mengatur negara sesuatu dengan kehendak dan aspirasi zamannya.
Kembali ke film Curse of the Golden Flower, film itu mengajarkan dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa bagaimanapun kekuasaan itu adalah sesuatu yang fana. Sesakti-saktinya seseorang, maka dalam sejarah kekuasaan diIndonesia, seseorang hanya bisa berkuasa sekitar 30 hingga 35 tahun.
Ketika kekuasaan dipertahankan dalam segala cara, seperti pengalaman Soeharto,maka cara-cara itu hanya menimbulkan dendam dan pelajaran buruk bagi sistemdan konstelasi kekuasan di Indonesia. Jejak-jejak pelajaran yang diajarkan Soeharto itu hingga hari masih menjadi trauma masyarakat Indonesia. Kekuasaan (politik)menjadi sesuatu yang dilematis dan problematis di Indonesia.
Curse of the Golden Flower dan kekuasan Soeharto memberi pelajaran kepada kitabahwa kekuasaan harus dibersihkan dari ambisi-ambisi pribadi. Jika tidak, cepatatau lambat, kekuasaan akan punah dan rakyat akan mengenangkan sebagai rajaatau presiden yang zalim dan otoriter. Dan itu tidak akan pernah bisa dihilangkansejarah, sampai kapan pun.
(7)WAJAH SENYUM TAK BERSALAH
Ada hal menarik yang coba dipertontonkan oleh para tersangka dan terdakwapelaku kejahatan (khususnya koruptor) di televisi. Wajah itu adalah wajah penuhsenyum. Dan bahkan dengan percaya diri tidak terlihat kesan malu di wajah itu.Tidak ada kesan merasa bersalah dan prihatin di wajah itu.Tentu, sejauh pengadilan belum membuktikan bahwa para pelaku kejahatan itubersalah, kita tidak boleh berprasangka bahwa para pelaku itu pasti telahmelakukan kesalahan.
Apa pun yang terjadi, para tersangka dan terdakwa pelakukejahatan berhak membela dirinya, hingga hukum positif membuktikan bahwamereka terbukti bersalah dan layak dihukum.Herannya, ketika kejahatan para pelaku itu telah ditayangkan dan diberitakan,berupa bukti-bukti rekaman video, rekaman telepon, dan gambar-gambar peristiwakejahatan lainnya, wajah senyum itu tak pernah meluntur. Apa yang terjadi?
Pertama, mereka tahu bahwa melakukan kejahatan di Indonesia itu biasa. Mereka paham, siapa yang tidak pernah melakukan kejahatan di Indonesia. Hidup dalam negara miskin dan semrawut ini, siapa pun dia tidak akan terhindar dari perbuatan jahat. Mereka hanya sial dan tertangkap basah. Mereka segelintir orang yang tidak beruntung karena secara tidak sengaja kejahatannya diketahui.
Kedua, mereka tahu melakukan kejahatan tidak harus malu. Ya, kenapa mereka harus malu. Jangankan mereka yang “orang awam”, lha mereka para alim ulama,mereka para intelektual, peneliti, mahasiswa, guru, dan para pemimpin lainnya juga korupsi, atau melakukan kejahatan lainnya.
Ketiga, mereka tahu bahwa memasang wajah senyum itu adalah “kepribadian”
masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah. Senyum itu sebagai tanda bahwa hatinya sedang riang karena dapat memberikan sedekah senyum. Jadi, senyum itu sebagai tanda kebaikan mereka, atau mereka baik-baik saja dan perlu memberi senyum.
Keempat , mereka tahu bahwa mereka hanya dikambinghitamkan. Dalam sistem birokrasi yang kita bangun itu, kemudian kita mengenal istilah bahwa korupsi itu dilakukan secara berjamaah. Dalam jamaah koruptor itu semua orang sebetulnya terlibat. Mereka “sengaja” ditangkap untuk dikambinghitamkan agar jamaah yang lain selamat, Jadi, ada juga perasaan di hati mereka justru yang tertangkap itu telahbertindak sebagai pahlawan.
Kelima, mereka tahu bahwa toh nanti hukum bisa dibeli. Artinya, tidak ada yangperlu ditakutkan jika melakukan kejahatan korupsi. Uang akan menyelesaikansegalanya. Siapa kita yang bukan orang munafik tidak mau uang? Bahkan penegakhukum seperti jaksa, hakim, pengacara, polisi, pun ternyata tak kebal suap. Senyumadalah tanda kedermawanan.
Keenam, mereka tahu bahwa kelak setelah dihukum mereka bisa bersenang-senang. Mungkin mereka akan dihukum 1 atau bahkan hingga 7 tahun. Tapi dengan uang korupsi milyaran yang telah “disimpan” itu, mereka menganggap hukuman 1 hingga 7 tahun itu seperti bertapa sebentar, seperti mejalani hidup prihatin.Mereka percaya, setelah masa prihatin di penjara, maka masa untuk bersenang-senang akan datang sebagai imbalannya.
Ketujuh, terlepas dari itu, mereka tahu bahwa bagaimanapun mereka harus tampil layak lihat dan memenuhi kepantasan. Prasangka buruknya adalah bahwa sebetulnya mereka tidak percaya diri terhadap wajah mereka yang tidak ganteng atau tidak cantik. Untuk menutupi itu, mereka harus tampil senyum sehingga terlihat tetap ganteng atau cantik.Tentu kita tidak tahu persis, kira-kira senyum yang mana yang diumbar para koruptor jahat tersebut. Mungkin salah satunya, mungkin salah dua, mungkin semuanya.
Akan tetapi, mengingat kejahatan korupsi di Indonesia adalah keterlibatanberjamaah, sangat mungkin senyum mereka adalah senyum pahlawan. Jadi, jikaAnda ingin menjadi pahlawan, maka salah satu cara adalah dengan melakukankorupsi. Syukur jika korupsi itu tidak ketahuan, karena Anda tetap menjadipahlawan di lingkungan jamaah Anda. Wajah senyum Anda tentu tetap dapatditebarkan, terutama di lingkungan jamaah sesama koruptor.
Terlepas dari itu, ada hal menarik lain, bahwa biasanya para pelaku kejahatan itutiba-tiba tampil memakai kopiah, atau kopiah haji berwarna putih, dan memakai sarung. Seperti memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya sangat relijius, tapi terjebak dalam kejahatan yang dia sendiri tidak mau melakukan.
Kemudian setelah tertangkap, dengan wajah tetap mengumbar senyum, setiap pembicaraan mereka mengucap Astagfirullah, Alhamdulillah, Allah sedang memberi cobaan, dan ungkapan lain yang seolah dengan tertangkapnya para koruptor itu, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Tahu, bahwa sebetulnya Tuhan tahu bahwa dia tidak bersalah.Yang pasti, mereka para koruptor itu adalah para aktor yang mampu
menyembunyikan kegelisahan mereka.
Mereka mampu “menjadi orang lain”, mampu memerankan peran yang bukan dirinya sendiri selama menjadi pesakitan.Saya yakin, ketika mereka sendiri, tidak ada orang yang melihat, maka wajahaslinya akan muncul dalam kesepian yang sangat. Wajah asli itu adalah wajah yangmurung, wajah yang menyesal, wajah yang pedih. Dalam kondisi itu, merekasedang tidak menjadi aktor dunia panggung sandiwara. * * *
(8)LELAH MENJADI BANGSA
Belakangan menguat kembali idiom atau frasa bela bangsa bela negara.
Bangsa dan negara merupakan dua hal yang berbeda. Di Indonesia, walaupun beberapaoranisasi politik telah menyebut ide kebangsaan pada tahun 1908, tetapi ide danimajinasi ke-bangsa-an dikukuhkan pada tahun 1928. Setelah itu, baru kemudianNegara KRI pada tahun 1945.
Sadar karena masyarakat Indonesia itu majemuk darisegi etnis, bahasa, ras, agama, dan sejarah kebudayaannya, maka denganmeminjam gagasan Ernest Renan tentang bangsa, berbagai perbedaan tersebutdimasukan ke dalam dan untuk menjadi bangsa, bangsa Indonesia.Bangsa adalah kesepatan sosial dan kultural, sedang negara adalah kesepakatanpolitik dan struktural.
Kasus Indonesia, bangsa adalah adanya berbagai perbedaan untuk dan agar perbedaan tersebut masuk dalam satu wajah bangsa. Artinya,bangsa Indonesia adalah sesuatu yang terdiri dari perbedaan atau keragaman menuju wajah yang satu, wajah bangsa Indonesia.
Untuk mempertahankan wajah bangsa, dibutuhan kesepakatan politik dan struktural, yakni negara. Di Indonesia,keberadaan negara justru melegitimasi keberadaan bangsa.
Untuk kasus Indonesia, kesepakatan tentang bangsa mendorong hadirnya negara.Kasus hubungan bangsa dan negara di tempat lain akan berbeda. Di Amerika, misalnya, negara lebih dulu muncul sebagai kesepatan politik, baru kemudiannegara itu mencoba mengelola apa yang disebut sebagai bangsa Amerika.
Di beberapa negara “yang homogen” dari segi ras, seperti Jepang, tidak menghadapi kasus kebangsaan yang serius.Secara faktual negara Indonesia tersebut menjadi ada, terdiri dari wilayah, rakyat,menejemen pemerintahan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan berbagaikelengkapan lain untuk disebut negara.
Kemudian, negara berkewajiban mempertahankan bangsa yang melahirkannya. Negara menghegemoni dan berdialektika dengan rakyat dan mendapat legitimasi untuk membela bangsa. Munculah jargon bela bangsa bela negara. Bila negara tidak kuat dan bubar, apakah bangsa bisa bubar?
Lelah
Saya menduga bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sedang dalam keadaan lelah menjadi bangsa karena dipaksa terus menerus untuk mempertahankannya. Lelah karena begitu banyak cobaan yang dihadapi untuk menjadi bangsa yang bernegara.
Cobaan tersebut dapat dibedakan dalam dua hal, yakni serangan dan ancaman terhadap negara dan serangan terhadap bangsa. Ancanam terhadap negara adalah berbagai upaya politik, baik dengan kekerasanatau tidak, untuk mengganti, atau paling tidak merongrong, struktur kekuasaan dan legitimasi negara yang diakui berdasarkan kesepakatan bangsa.
Kita tahu bahwa hal bangsa tersebut adalah dengan berpegang teguh pada keragaman suku, agama, ras, yang dipayungi oleh UUD dan pancasila. Dalam konteks tersebut, jika mengancam atau menyerang negara, berarti keberadaan bangsa juga terancam. Peristiwa politik pada tahun 1965, apapun perspektifnya, adalah salah satu kasus yang mengancam keberadaan negara.
Jika negara berganti, kita tidak tahu karakter “negara baru” akan tetap
mempertahankan bangsa dalam pengertian 1928 atau tidak. Karena bisa saja
“negara baru” akan mengeluarkan unsur kegaraman,unsur pembentuk keragaman, baik unsur agama, ras, atau suku. Mungkin juga tidak, kita sungguh tidak tahu.
Akan tetapi, pesan pentingnya adalah keberadaan negara baru menjadi ancamanterhadap substansi kebangsaan.
Serangan terhadap bangsa burapa berbagai gerakan sosial, terutama berbasis kesukuan, kedaerahaan, keagamaan, atau bahkan berdasarkan ras tertentu yang mencoba berdiri sendiri dan keluar dari bangsa. Kasus-kasus pendirian negara baikberbasis daerah atau berbasis agama (di daerah tertentu), merupakan contoh terbaik yang bisa dikenal sebagai bagian dari gangguan terhadap kesepakatan berbangsa.
Munculnya, baik serangan dan ancanam terhadap bangsa dan negara, hal tersebut sebetulnya memperlihatkan lemahnya negara menjaga ibu kandung dirinya, yakni bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa dalam rentang waktu yang panjang, negara tidak terlalu sukses meyakinkan ibu kandungnya, untuk bangga menjadi bangsa Indonesia.
Pertama, negara Indonesia, dalam sejarahnya, bukan negara yang sukses membangun dirinya sebagai satu kuasa struktural yang berwibawa. Hal-hal yang bersipat korup, manipulatif, dan personalisasi kuasa yang terjadi dalam tubuh negara, telah melemahkan wibawa negara sehingga bangsa harus menanggungbeban kelemahan tersebut. Dalam budaya Jawa dikenal
anak pola bapak kepradah.
Kedua, negara juga tidak mampu meminimalkan jarak/jurang antara yang kaya dan miskin, antara yang elite dan rakyat kebanyakan. Jarak yang jauh ini sangat berbahaya, karena, dalam sejarahnya, tidak ada alasan bagi rakyat kebanyakan untuk mempertahankan negara jika rakyat kebanyakan hidupnya relatif susah dan menderita. Jurang struktur ekonomi yang tajam dengan mudah mendapat gangguan atau intervensi yang menjanjikan perbaikan ekonomi. Itulah sebabnya, nalarbela bangsa dan bela negara merupakan satu kesatuan yang saling bergantung. Negara perlu memperbaiki kinerja dirinya untuk berwibawa dan kuat agar bangsa yang merangkum keragaman terjamin keberadaan dankeberlasungannya. Negara harus mengurangi beban yang ditanggung bangsa agarterhindar dari kelelahan yang berbahaya. * * *