Menuju Paradigma Sains Islam Nusantara
By:
Ahmad Yanuana Samantho, MA
“AND ALLAH HAS BROUGHT YOU FORT FROM THE WOMBS OF YOUR MOTHER – YOU DID NOT KNOW ANYTHING – AND HE GAVE YOU HEARING AND SIGHT AND HEARTS THAT YOU MAY GIVE THANKS.”
( QS AN-NAHL, 16: 78 )
Latar: Krisis Multidimensional Akibat Modernisme-Materialisme
Secara hipotetis-filosofis dapat dikatakan bahwa krisis multidimensional mutakhir yang dihadapi umat manusia saat ini adalah efek negatif dari Modernisme dan Postmodernisme yang telah semakin meningkat dan terbukti secara bersamaan dari hari ke hari di era kontemporer ini. Sayangnya tidak cukup jumlah orang yang menyadari bahwa krisis multidimensional global dalam seluruh kehidupan asasi manusia hari ini benar-benar berakar lebih dalam pada paradigma filosofis Modernisme mereka. ….
Masalah utama modernisme (dan juga postmodernisme) pada kehidupan manusia modern disebabkan oleh dominasi pandangan dunia sekuler-materialistik (materialisme, humanisme sekuler dan sekularisme) yang bercampur dengan agnostisisme, antropho-sentrisme dan ateisme, sebagai alat dan “filosofi dasar” ideologi materialisme liberalisme-kapitalisme.[1]
Pada gilirannya dominasi ini modernisme sekuler-materialistik ini telah menyebabkan banyak masalah krusial dan gawat bagi kehidupan manusia di bumi. Krisis multidimensi yang terjadi dari hari ke hari, telah menakutkan sebagian besar orang di dunia saat ini, tanpa manusia modern dapat memecahkan masalah mendasar mereka secara tuntas dan komprehensif. Masalah ini akan penulis elaborasi dalam deskripsi analitis berikutnya tentang masalah modernisme, kritik modernisme dan postmodernisme juga dan solusi alternatif untuk masalah tersebut menurut sudut pandang Seyyed Hossein Nasr.
Dalam mengambarkan kondisi kehidupannya, menurut Nasr, manusia modern telah terusir ke tepian lingkaran roda realitas eksistensialnya (keberadaan nyatanya), yang jauh dari porosnya. Ini adalah krisis eksistensial yang diderita oleh manusia modern, karena mereka melupakan realitas diri mereka sendiri. Nasr menulis:
“Dunia masih terlihat oleh diatur kekuatan dan elemen yang kosong dari suatu horizon spiritual, bukan karena tidak hadirnya cakrawala spiritual seperti itu, tapi karena mereka seringkali memandang lanskap kontemporernya seperti manusia yang tinggal di tepian lingkaran roda eksistensi dan karena itu memandang segala sesuatu dari pinggiran lingklaran roda. Dia tetap acuh tak acuh terhadap jari-jari roda dan benar-benar tidak menyadari Sumbu dan Pusatnya, yang bagaimanapun tetap tak pernah diakses ke tengahnya dari pinggirannya.”
“Masalah kehancuran yang dibawa teknologi kepada lingkungan, yang menyebabkan krisis ekologi dan sejenisnya, semua itu adalah masalah akibat penyakit amnesia atau lupa diri yang diderita manusia modern serta post-modern. Manusia modern telah lupa siapa hakikat jati dirinya. Hidupnya berada di pinggiran lingkaran eksistensinya sendiri, walau ia telah mampu untuk mendapatkan kuantitas pengetahuan yang banyak tapi dangkal kualitas ilmu pengetahuan dunianya. Dia telah memproyeksikan citra kulit luaran dan dangkal pengetahuan tentang dirinya mengenai dunia.”[2]
Menurut Nasr, di Barat manusia pertama-tama memberontak terhadap pengaruh Langitan akibat pengaruh falsafah-ideologi humanisme zaman Renaissance di Eropa Abab 16; pada saat awal ilmu modern hadir mewujud. Antropologi humanistik renaissance adalah latar belakang yang mendorong Revolusi Ilmiah pada abad ketujuh belas dan penciptaan Ilmu pengetahuan (science) yang meskipun di satu sisi bersifat non-manusiawi, dalam arti lain, akal rasional manusia dianggap yang paling anthropomorphic dan bentuk ilmu pengetahuan yang paling mungkin, itu yang menjadikan nalar humanis dan data empiris yang hanya didasarkan pada indera manusia sebagai satu-satunya kriteria untuk keabsahan (validitas) semua pengetahuan.[3]
Nasr juga menyatakan bahwa dekadensi kemanusiaan di zaman modern ini disebabkan oleh hilangnya kemanusiaan dari humaniora di zaman modern ini, yang disebabkan oleh karena manusia telah kehilangan pengetahuan langsung tentang dirinya sendiri dan juga tentang Diri yang sejatinya, yang sebenarnya ia selalu memilikinya, dan karena ketergantungannya pada sebuah sudut pandang luar, sebuah pengetahuan tentang dirinya sendiri yang supevisial (dibuat-buat), yang ia berusaha untuk mendapatkan dari luar lingkaran. Secara harfiah adalah pengetahuan “dangkal” yang diambil dari pingir lingkaran dan tanpa sebuah kesadaran diri akan poros roda dan jari-jari yang dapat menghubungkan dia seperti sinar cahaya matahari ilahiah.[4]
Modernisme, sebagai sebuah pandangan dunia materialistik-sekuler dan paradigma filosofis yang masih dominan pada sebagian besar kebanyakan orang di dunia sejak zaman modern sampai sekarang, secara hipotetis atau sangat diasumsikan oleh Nasr, telah menyebabkan banyak masalah dan mendorong krisis multidimensional bagi kehidupan manusia. Masalah-masalah ini akan dipelajari dan dielaborasi lebih jelas dan dikaji secara kritis bukti-buktinya dalam pandangan cahaya Filsafat Islam dan metodologinya (secara ontologis & epistemologis) oleh penulis.
Masalah kedua yang muncul sebagai reaksi ekstrim terhadap modernisme – adalah munculnya “fundamentalisme” ekstrim paham keagamaaan di mana mereka melakukan penafsiran harfiah (literal) yang salah dan aplikasi religius yang salah (terutama dalam aspek eksoterisme/kulit luaran Islam) yang diajarkan hari ini. Pada satu sisi hal ini juga akhinya telah menyebabkan berbagai bencana terorisme dan kekerasan yang mengatasnamakan ajaran Agama Islam dan Tuhan.
Apa yang benar-benar terjadi pada modernisme, berapa banyak aspek kehidupan modern telah menjadi krisis kemanusiaan dan kehancuran? Bagaimana hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan mendorong krisis multidimensional manusia modern sampai beberapa waktu terakhir? Apa masalah utama dan karakteristik prinsip dalam paradigma modernisme yang menyebabkan krisis multidimensional global manusia modern saat ini, termasuk gerakan kekerasan fundamentalisme literal keagamaan ?
Setelah kita mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan & krisis modernisme, seberapa jauh kita bisa menawarkan paradigma alternatif baru untuk memecahkan masalah tersebut? Apa itu paradigma alternatif baru yang dapat memecahkan masalah tersebut menurut Seyyed Hossein Nasr? Berapa jauh terkait dengan beberapa kesadaran baru, Sophia Perrenialism (kebijaksanaan abadi) dan mistisisme (ilmu suci tradisional) yang telah meningkat dan terlahir kembali di waktu kontemporer baru-baru ini? Bagaimana dan mengapa relevan dengan Teori Fisika Quantum dalam melihat kosmologi baru? Dapatkah filsafat, tradisi dan agama bersatu dan akan menyelaraskan dalam satu paradigma baru holistik-integral (terpadu dan menyeluruh) di masa depan?
Apa yang disarankan oleh Seyyed Hossein Nasr ini tentang pentingnya Traditional Sacred Science (Ilmu Pengetahuan Sakral/Suci Tradisional) serta Sophia Perennialisme (Kearifan Kuno-Abadi) ini, ternyata menurut hipothesis penulis menemukan relevansi dan signifikasinya dengan warisan kearifan lokal asli Nusantara atau dengan nilai-nilai dan ajaran tradisional sakral/suci Nusantara yang telah menjadi semacam Sophia Perennialism, yang mungkin tak hanya akan bermanfaat bagi masa depan bangsa kita, tetapi juga akan bermanfaat bagi masa depan kemanusiaan sedunia.
Tujuan
Hasil penelitian penulis yang ditulis dalam buku ini mencoba untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bencana dan krisis multidimensi global manusia modern dan apa penyebab utamanya secara prinsipil?
Setelah kita mengidentifikasi dan mengelaborasi problema dan krisis modernisme, penulis akan berusaha mencari alternative paradigma baru untuk memecahkan berbagai masalah ini dari akarnya berdasarkan resep yang disarankan oleh Seyyed Hossein Nasr di abad modern ini dan juga oleh para bijak berstari serta para orang suci serta Nabi Allah sepanjang sejarah kemanusiaan di dunia ini.
Penelitian yang mendahului proses penulisan buku ini yang didahului oleh penelitian thesis magister filsafat Islam penulis, juga akan menganalisa, sejauh mana hal ini terhubung dengan beberapa kesadaran baru, Sophia perennialism dan mysticism (traditional sacred science) yang telah bermunculan dan lahir kembali di zaman kontemporer mutakhir ini? Bagaimanakah hal in terkait dan relevan dengan kemunculan teori fisika baru Quantum Physics dan pandangan kosmologis baru? Dapatkah filsafat (termasuk science) dan agama bersatu dan menjadi harmonis dalam sebuah paradigma baru yang integral holistic di masa depan.
Jawaban nyata atas pertanyaan dan masalah ini, mudah-mudahan akan menawarkan layanan bagi basis intelektual, filosofis dan spiritual untuk memecahkan masalah secara radikal dan fundamental. Dengan kata lain, penelitian ini akan menyajikan saran untuk mengaktualisasikan atau meng-aktivasi “pergeseran paradigma” menuju paradigma yang holistik dan integral yang mendekati untuk memahami Realitas: integrasi dan harmonisasi antara Tuhan Allah, manusia dan alam semesta, dalam sudut pandang Filsafat Islam atau pandangan dunia Islam.
Penelitian ini juga mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan beberapa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan penemuan terbaru seperti terkait dengan teori Fisika Quantum dan beberapa fakta yang mengarah untuk membuka realitas alam semesta dan spiritual makhluk yang tidak terpisahkan. Sejalan dengan kemajuan ilmu baru pada Quantum Physic, penelitian ini juga mencoba untuk menyajikan kesinambungan dan hubungan antara fakta & teori dengan beberapa pendekatan pengajaran mistis yang dilayani oleh tasawuf dan Irfan (Mistisisme Islam) dan mistisisme agama-agama lainnya. Penelitian ini juga akan menyajikan dan menguraikan dan wacana penting tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama sebagai konsekuensi dari penelitian inti keseluruhan dalam penulisan thesis ini.
Signifikansi
Buku yang dikembangkan dari hasil penelitian Program Magister Filsafat Islam (2010) ini tentu sangat penting dan akan memberikan banyak manfaat dan signifikansi untuk kehidupan sehari-hari saat ini dan masa depan kita. Setidaknya hasil penelitian ini sangat signifikan untuk meningkatkan dan membuat dekonstruksi yang berlanjut pada reformulasi (dan rekonstruksi) dari paradigma kita secara filosofis. Pada gilirannya, pada tingkat epistemologi dan aksiologi, pendekatan paradigma holistik dan integral ini dan nilai-nilai dalam pencerahan Filsafat Islam dan Tasawuf Islam (Irfan & Tasawuf) dapat memecahkan banyak masalah manusia modern secara bertahap, baik untuk tujuan individu dan juga dalam sistem sosial-ekonomi-politik-budaya dan di dalam supremasi percerahan terbaru, dan peradaban yang lebih baik.
Lebih spesifik, manfaat yang saya harap dapat tercapai setelah thesis dan buku ini diselesaikan adalah penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun ulang filsafat ilmu kita (atau minimal epistemologinya) dan kemudian dapat menjabarkan pandangan dunia baru dan sebuah ideologi yang dapat memainkan peran penting sebagai pedoman untuk proyek rekonstruksi kurikulum ilmu baru dan untuk melakukan penulisan ulang semua isi buku teks dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan pendidikan dan akademik menuju rekonstruksi peradaban manusia baru dalam cahaya misi Islam Rahmatan lil ‘Alamin.
Tentu saja ada telah ada beberapa studi yang berkaitan dengan kritik pada modernisme menurut pandangan Seyyed Hossein Nasr, seperti apa yang teman penulis di ICAS Jakarta, Humaedi telah tulis dalam thesisnya berjudul: “Konsep Nasr dalam Knowledge: Pengetahuan Sakral, kontribusi kepada Epistemologi Modern “
Tentu saja bahwa beberapa studi yang juga berkaitan dengan pandangan Seyyed Hossein Nasr dan kritiknya kepada modernisme dan post modernisme sangat berguna untuk penelitian penulis sebagai referensi, terutama untuk pemahaman dan deskripsi latar belakang thesis penulis & rumusan masalah yang akan penulis pelajari.
Penelitian thesis penulis lebih fokus pada relevansi resep Nasr atau saran untuk mempromosikan ilmu pengetahuan suci atau pandangan tradisional agamis dan mistisisme atau esoterisme sebagai kebijaksanaan abadi (Sophia Perennis) untuk memecahkan masalah modernisme dan postmodernisme. Paradigma alternatif tentang Sacred Science dan Perennial Wisdom ini akan diikuti oleh elaborasi penulis terkait dengan kecenderungan terbaru dan wacana dalam pengembangan atau penemuan ilmu fisika baru terutama dalam teori fisika kuantum yang memiliki hubungan yang kuat dengan kesadaran (consciousness) yang baru dalam ilmu: filsafat ilmu pengetahuan integral dan holistik dan pandangan agama (Paradigma holistik-Integral). Pendekatan ini dan pilihan untuk topik ini, saya pikir masih unik dan memiliki studi asli di bidang penelitian Filsafat Islam.
Sumber utama saya untuk penelitian thesis ini adalah beberapa buku penting dan mendasar di antara keduanya dari Seyyed Hossein Nasr seperti “The Plight of Modern Man” and “The Need for A Sacred Science”, “The Knowledge and The Sacred”, “Ideal and Reality” and “Islamic Philosophy from Its Origin to the Present, Philosophy in The Land of Prophecy”, dll.
Sumber-sumber primer akan dibandingkan, dielaborasi dan dikompilasi dengan sumber-sumber sekunder yang terkait dengan wacana tentang wacana Perennialisme, ilmu pengetahuan dan agama, teori fisika baru Quantum Physic, seperti: “The Greatest Achievement in Life: Five Traditions of Mysticism, Mystical Approaches to Life”, oleh R.D Krumpos; “Tawheed and Science: Essays on The History and Philosophy of Islamic Science” oleh Osman Bakar; “Nature, Human Nature and God, …”, (terjemahan Indonesianyta berjudul: “Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama”) oleh Ian G Barbour; “The Web of Live, A New Synthesis of Mind and Matter”, oleh Fritjof Capra; and “The Holy Qur’an and The Sciences” by Mehdi Golshani; “Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami”, oleh Armahedi Mahzar, sebagaimana dapat kita lihat dalam daftar pustaka saya (referensi) di halaman terakhir dari thesis ini, serta beberapa artikel yang memuat kearifan lokal Nusantara sebagai warisan budaya dan Peradaban Adiluhung Nusantara yang masih tersisa, yang bisa menjadi contoh betapa Leluhur Nusantara sudah mewariskan Kearifan Perennial dan Traditional Sacdred Science tersebut.
MASALAH KRISIS MODERNISME:
Krisis Multidimensional yang Disebabkan oleh Paradigma Ontologis–Epistemologis Materialialisme-Sekulerisme Barat dalam Ilmu Dan Kebudayaan
Modernisme yang masih memainkan peran hegemonik dan berpengaruh besar di dunia saat ini, telah mendapatkan dasar gerakannya sejak Renaissance di Perancis (abad ke-14-17 M) dan beberapa revolusi sosial-politik pada setengah pertama abad kesembilan belas di Eropa.
Modernisme yang kita kaji di sini adalah kompilasi dari beberapa filsafat modern barat. Dalam pemahaman umum:
“Modernisme, dalam definisi yang paling luas, adalah pemikiran modern, dan karakter yang mudah menjadi usang atau baru dalam praktek ekonomi, sosial dan politik. Lebih khusus lagi, istilah modernism ini menggambarkan seperangkat kecenderungan budaya dan berbagai gerakan budaya yang terkait, yang awalnya timbul dari perubahan masyarakat Barat dalam skala luas dan jauh jangkauannya di akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Istilah ini mencakup kegiatan dan hasil dari mereka yang meninggalkan hal-hal yang ‘tradisional’ dalam bentuk seni, arsitektur, sastra, keyakinan agama, organisasi sosial dan kehidupan sehari-hari yang merupakan kondisi dari sepenuhnya muncul dunia industri.”[5]
Modernisme menolak kepastian yang tersisa dari pemikiran Pencerahan (Enlightenment), dan juga menolak keberadaan (eksistensi) Tuhan Yang Maha Pengasih, Tuhan Pencipta Yang Maha Kuat[6]. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua modernis atau gerakan modernis menolak semua agama atau semua aspek pemikiran Pencerahan, melainkan modernisme yang dapat dilihat sebagai selalu mempertanyakan aksioma zaman sebelumnya.
Karakteristik penting dari modernisme adalah kesadaran diri. Hal ini sering kali menyebabkan eksperimen dengan berbagai bentuk, dan pekerjaan yang menarik perhatian pada proses dan bahan yang digunakan (dan kecenderungan lanjut abstraksi)[7]. Saran paradigmatik penyair Ezra Pound adalah untuk “Make it New!” Apakah motto “membuat yang baru” dari kaum modernisme merupakan era sejarah baru yang bisa diperdebatkan. Filsuf dan komposer Theodor Adorno memperingatkan kita:
“Modernitas adalah sebuah kategori kualitatif, bukan kronologis, karena hal seperti itu tidak dapat direduksi menjadi bentuk abstrak, dengan kebutuhan yang sama itu harus kembali pada koherensi permukaan konvensional, penampilan harmoni, urutan yang dikuatkan hanya dengan replikasi.” [8]
Adorno ingin kita memahami modernitas sebagai penolakan terhadap rasionalitas palsu, harmoni, dan koherensi pemikiran, seni, dan musik era Pencerahan dari Jerman. Tapi masa lalu membuktikannya lengket. Perintah umum Pound yang penting untuk membuat baru, dan nasihat Adorno untuk menantang koherensi palsu dan harmoni, menghadapi penentangan TS Eliot tentang hubungan antara seniman ke tradisi. Eliot menulis:
“Kita sering akan menemukan bahwa tidak hanya yang terbaik, tapi bagian yang paling individu dari karya seorang penyair, mungkin orang-orang di mana penyairnya mati, nenek moyangnya menegaskan keabadian mereka yang paling penuh semangat.” [9]
Sarjana sastra Peter Childs menyimpulkan kompleksitasnya:
“Ada paradoks jika tidak ada kecenderungan menentang ke arah posisi revolusioner dan reaksioner, takut terhadap hal yang baru dan menyenangkan pada hilangnya yang tua, nihilisme dan antusiasme fanatik, kreativitas dan keputusasaan.” [10]
Oposisi ini melekat pada modernisme: itu adalah yang dalam arti luas penilaian budaya masa lalu yang berbeda dengan zaman modern, pengakuan bahwa dunia menjadi lebih kompleks, dan bahwa “otoritas final” lama (seperti: Tuhan, pemerintah, ilmu pengetahuan, dan penalaran) yang akan menjadi tunduk pada pengawasan kritis intens.
Interpretasi mutahir tentang modernisme sangatlah bervariasi. Beberapa reaksi membagi abad ke-20 ke dalam modernisme dan postmodernisme, sedangkan yang lainnya melihat mereka sebagai dua aspek dari gerakan yang sama.
Untuk memahami resume singkat tentang modernisme, saya mengutip dari penjelasan tentang Filsafat Barat Modern dari Sang Dosen di The Islamic College for Advanced Study (ICAS) Jakarta, 2004, Dr. Fransisco Budi Hardiman, di bawah ini: [11]
- Arus Utama dan Karakteristik Filsafat Modern:
Menurut Fransico Budi Hardiman, Ph.D dalam kuliah-kuliahnya di ICAS Universitas Paramadina tahun 2004 yang penulis ikuti, ada beberapa arus utama dalam Filsafat Barat Modern (Modernisme), yaitu:
- Rasionalisme (Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Pascal)
- Empirisme (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume)
- Kritisisme (Kant)
- Idealisme (Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer)
- Materialisme (Feuerbach, Marx)
- Positivisme (Comte, Mach)
- Eksistensialisme (Kierkegaard)
- Vitalisme (Nietzsche)
“Modern” berarti yang “baru” dan “sekarang”. Modern adalah orientasi temporal ‘di sini dan sekarang’ [tidak ada ‘di sana dan di masa lalu’ dari mentalitas abad pertengahan]. Istilah ini berhubungan dengan konsep waktu: kemajuan linear [bertentangan dengan konsep siklus waktu]. Konsep kunci dari modernitas: “kemajuan teknologi”, “revolusi”, “pertumbuhan ekonomi”.
Tiga Karakteristik Filsafat moderen:
- Berpusat pada masalah kesadaran atau subjektivitas manusiawi [bertentangan dengan theo-sentrisme]
- Radikalisasi konsep epistemologis kritik [bertentangan dengan dogmatisme]
- Teleologis dan Konsep kemajuan sejarah umat manusia [bertentangan dengan status quo]
- 1) Filsafat Modern Adalah Filsafat Subjek:
Secara keseluruhan kita dapat melihat filsafat modern Barat sebagai program penelitian tentang masalah epistemologis dan metafisik kesadaran seperti itu [subjek atau subjectum]. Jadi Habermas menyebutkan itu filosofi Subjek [die Subjekt philosophie] [12]
- Asal usul kesadaran (misalnya Descartes dan Locke)
- Perkembangan kesadaran (misalnya Hegel, Kierkegaard, Comte)
- Runtuhnya kesadaran (misalnya Schopenhauer, Nietzsche)
- Kritik Sebagai Konsep Sentral Dalam Filsafat Modernisme:
Kritik adalah dianggap rata-rata dari proses emansipasi; yang berfungsi sebagai:
- Refleksi pengetahuan diri (kritik pengetahuan atau epistemologi)
- Pemecah benteng manipulasi ideologis (kritik ideologi atau pencerahan)
- Perjuangan melawan ketidakadilan politik (kritik terhadap rezim atau revolusi)
Catatan: Kritik bukanlah penolakan belaka terhadap sesuatu, tapi negasi wajar dengan kondisi epistemologis yang kompleks. Ini berasal selama munculnya ilmu pengetahuan alam modern yang mereka sangat skeptis terhadap pemikiran metafisik abad pertengahan. Kritik adalah seorang pembela faktual.
- 3) Sejarah Memiliki Struktur Teleologis (Kebermanfaatan):
Sejarah tidak sewenang-wenang, namun memiliki akhir yang dapat diantisipasi. Para idealis Jerman mencoba menemukan skema rasional di balik peristiwa empiris sejarah. Mereka percaya bahwa ‘telos’ sejarah adalah kebebasan manusia dan masyarakatnya. Proses peradabannya cara untuk kebebasan manusia.
Marx percaya bahwa manusia (khususnya kaum proletar) adalah aktor sejarah yang mendorong ke ujungnya melalui transformasi sosial (revolusi). Baginya akhir dari sejarah adalah masyarakat tanpa kelas.
Comte menyatakan bahwa ujungnya masyarakat positivis, peradaban ilmiah dari umat manusia.
Hegel melukiskan akhir sejarah sebagai rekonsiliasi akhir gagasan dengan diri, yaitu sejarah yang tahu diri.
Catatan: pemikiran teleologis (Kebermanfaatan) adalah sumber dari utopianisme dalam teori sosial modern.
- C. Renaissance dan Filsafat Humanisme [13]
Semangat filsafat modern mulai dibangun di zaman Renaissance. Kelahiran kembali peradaban Yunani dan Romawi di Italia selama abad ke-16 tercermin dalam banyak aspek budaya seperti sastra, arsitektur, filsafat, seni dll. Agen utama gerakan renaissance itu adalah kaum humanis seperti Dante, Petrarkha, Rabelais, Thomas Morus, dll. Para humanis mengajarkan kefasihan bicara, sejarah, puisi, moral (sebanding dengan sofis di Yunani kuno).
Manusia sebagai Makhluk Alami (Natural Being): budaya Renaissance memandang manusia sebagai makhluk alami. Dia tidak datang dari langit, tetapi tumbuh dari bumi dan dilengkapi dengan bakat alam dan vitalitas. Jadi figur-figur patung telanjang di galeri renaissance yang mengagungkan keindahan alami manusia ini adalah ciri khas kebangkitan kembali peradaban Yunani di Eropa.
Manusia sebagai Individu: Individu (bukan kolektif) adalah tema sentral dari seni dan sastra dalam budaya renaissance. Dalam filsafat barat paradigma-pergeseran terjadi selama renaissance, yaitu dari pemikiran theo-sentrisme abad pertengahan menjadi pemikiran antroposentrisme (individualism) modern.
Machiavelli dan “Virtu”: teori kekuasaan Machiavelli adalah contoh dari pergeseran paradigma ini: menurut dia kekuatan politik bukanlah karunia Tuhan Allah yang diterima melalui keberuntungan (Italia: Fortuna), tetapi sesuatu yang bisa dirampas melalui usaha manusia dan keahliannya (Italia: virtu). Manusia (dalam hal ini sang pangeran) – bukan Tuhan – adalah pusat kekuasaan, dan dari tangannya-lah daya kekuasaan tumbuh, dan stabil dengan tangannya itu, yaitu melalui strategi rasional.
Reformasi Protestan, Renaissance memahami subjektivitas manusia sebagai kemampuan rasional. Tapi reformasi menekankan iman itu sebagai subyektif. Keduanya adalah sama dalam pemberontakan mereka melawan mentalitas abad pertengahan yang berpusat pada ‘alasan obyektif’ atau ‘iman obyektif’. [14]:
- Hubungan Antara Agama Dan Sains
Menurut Nancey Murphy, diskusi filosofis tentang hubungan antara ilmu pengetahuan modern dan agama secara historis telah cenderung berfokus pada ke-Kristenan, karena dominasinya di Barat. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama Kristen telah terlalu kompleks untuk dijelaskan oleh model ‘perang’ yang dipopulerkan oleh AD White (1896) dan JW Draper (1874). Perhitungan yang memadai dari dua abad terakhir membutuhkan perbedaan antara posisi konservatif dan liberal. Kristen konservatif cenderung melihat teologi dan ilmu pengetahuan sebagai sebagian yang saling beririsan dalam tubuh pengetahuan. Firman Allah dinyatakan (diwahyukan) di tengah ‘dua buku’: Alkitab dan alam Semesta. Idealnya, sains dan teologi harus menyajikan perhitungan yang konsisten tentang realitas yang tunggal; tetapi sebenarnya ada kasus di mana hasil capaian yang ilmu pengetahuan miliki rupanya bertentangan Kitab Suci, khususnya berkaitan dengan usia alam semesta dan asal-usul spesies manusia.[15]
![]()
Kaum Liberal cenderung untuk melihat ilmu pengetahuan dan agama sebagai pelengkap tetapi tidak berinteraksi satu sama lain, karena memiliki kekhawatiran yang begitu berbeda untuk membuat konflik tidak mungkin. Pendekatan ini dapat ditelusuri ke Immanuel Kant, yang telah membedakan dengan tajam antara akal murni (sains) dan alasan praktis (moralitas). Versi kontras ilmu pengetahuan yang lebih baru, yang berkaitan dengan apa dan bagaimana dunia alam, dan agama, yang berkaitan dengan makna, atau kontras ilmu dan agama karena mempekerjakan bahasa yang berbeda.
Namun, sejak 1960-an semakin banyak sarjana dengan kecenderungan teologis liberal yang telah mengambil minat dalam ilmu pengetahuan dan telah membantah bahwa dua disiplin tersebut dapat diisolasi satu sama lain. Topik dalam ilmu pengetahuan yang menawarkan poin bermanfaat untuk dialog kosmologi dengan teologi termasuk teori Big Bang dan implikasi yang mungkin untuk doktrin penciptaan, konstanta ‘fine-tuning’‘ kosmologi dan kemungkinan implikasi dari hal ini untuk argumen desain, dan evolusi dan genetika, dengan implikasinya terhadap pemahaman baru dari individu manusia.
Mungkin impor yang lebih besar adalah hubungan langsung antara ilmu pengetahuan dan teologi. Fisika Newton memupuk pemahaman tentang alam dunia sebagai ditentukan secara ketat oleh hukum-hukum alam; ini pada gilirannya memiliki konsekuensi serius untuk memahami tindakan ilahi dan kebebasan manusia. Perkembangan abad kedua-puluh seperti fisika kuantum dan teori kekacauan telah memanggil fisikawan untuk merevisi pandangan tentang sebab-akibat. Kemajuan dalam filsafat ilmu pada paruh kedua abad kedua puluh memberikan keterangan yang jauh lebih canggih pengetahuan daripada yang tersedia sebelumnya, dan ini memiliki implikasi penting untuk metode argumen dalam teologi.
- Agama dan Pendahulu Ilmu Pengetahuan Barat
Kepentingan Barat dalam perhitungan sistematis alam adalah warisan dari tradisi Yunani kuno dan bukan dari tradisi Ibrani, yang cenderung berfokus pada dunia manusia. Konsep alam Yunani tidak ditetapkan lebih terhadap konsep alam super, seperti yang telah berabad-abad yang lebih baru, sehingga sangat mungkin untuk mengatakan bahwa filsafat alam Yunani adalah inheren teologis. Sarjana Kristen awal terbagi dalam pendekatan mereka tentang filsafat alam Yunani, beberapa membuat penggunaan besar untuk tujuan apologetik[16], yang lain menolaknya[17]
Setelah jatuhnya Roma, pusat keilmuan bergeser ke arah timur. Para ilmuwan Islam di Abad Pertengahan sebagian besar bertanggung jawab untuk melestarikan pelajaran dari orang Yunani, serta untuk perkembangan ilmiah yang signifikan dari mereka sendiri dalam bidang optik, kedokteran, astronomi dan matematika. Melalui Muslim di Spanyol karya ilmiah yang penting Aristoteles diperkenalkan ke Eropa Barat pada abad kedua belas. Pengaruh karya ini pada pemikiran Kristen memuncak di “Two Summas“-nya Thomas Aquinas (Aquinas, T., Aristotelianisme).
- Ilmu Pengetahuan Modern Awal dan Pandangan Dunia
Pada akhir abad kesembilan belas, White (1896) dan Draper (1874) telah mempromosikan pandangan sains dan agama sebagai musuh tradisionalisme. Namun, sejarah revisionis pada akhir abad kedua puluh menyajikan gambaran yang jauh lebih kompleks. Memang benar bahwa Gereja Katolik telah membungkam Galileo pada tahun 1633, sehingga konsepsi mekanisme materi René Descartes dikutuk, dan sensor yang menakutkan, memiliki efek umumnya mengerikan bagi teori ilmiah sepanjang abad ketujuh belas. Namun, harus dicatat bahwa tidak semua pendeta Katolik menentang Galileo. Selain itu, sejumlah ilmuwan terbesar abad ini adalah Katolik: Pierre Gassendi, Marin Mersenne, Blaise Pascal dan Nicolas Steno, serta Galileo dan Descartes. Orde Jesuit adalah rumah bagi sejumlah ilmuwan yang bukan saja ahli teori yang luar biasa tapi memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan eksperimental.
Pada periode modern awal, sulit untuk membedakan konflik antara sains dan agama di satu sisi dari konflik intra teologis dan konflik antara ilmu baru dan sintesis skolastik Aristotelian di sisi lain. Perkara Galileo perlu ditafsirkan ulang dalam penerangan dari kedua komplikasi ini, karena tidak mungkin untuk memahami resistensi terhadap astronomi Galileo tanpa menyadari fakta bahwa itu mempertanyakan seluruh tatanan sosio-politik yang telah mapan tentang gambaran kosmos dan tempat manusia di dalamnya. Urusan itu juga tentang perjuangan internal gereja mengenai interpretasi yang tepat dari Kitab Suci. Perkara Galileo yang mengikuti Agustinus bahwa Kitab Suci harus ditafsiran ulang dan harus direvisi ketika ditemukan konflik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini menempatkan dia dalam konflik dengan para pendeta gereja konservatif lainnya yang mengadopsi strategi interpretatif lebih literalis. Sebuah komplikasi lebih lanjut adalah kenyataan bahwa ilmu baru sering bebas dicampur dengan sihir dan astrologi, yang Gereja Katolik mengutuknya baik karena mereka bereksperimen dengan iblis dan karena kecurigaan bahwa mereka membenarkan pandangan determinisme Calvinis terhadap pandangan kehendak bebas Katolik.
Robert Merton (1938) berpendapat bahwa puritanisme telah mempromosikan revolusi ilmiah, tesis ini masih diperdebatkan lebih dari setengah abad kemudian. Sementara tesis Merton itu dilebih-lebihkan, ada kemungkinan bahwa doktrin Reformed tertentu dari kedaulatan Allah – bahwa kedaulatan Allah mengecualikan semua kontribusi aktif dari makhluk yang lebih rendah untuk karya ciptaaNya – membuat konsepsi ilmiah dan materi filosofis modern sebagai kelembaman atau pasif lebih diterima oleh Isaac Newton, Robert Boyle dan Protestan selain itu.
Di sini sekali lagi adalah penting untuk mengenali interaksi Aristoteles dan sengketa intra-teologis. Konsepsi Mekanis materi adalah penolakan langsung baik dari konsepsi magis Neo-Platonisme dan dari teleologis Aristotelian dan pandangan organik, bahwa ‘bentuk’ yang melekat pada zat yang menyediakan kekuatan dan tujuan built-in. Pada saat yang sama, itu ditindaklanjuti dengan keyakinan teologis pertama diungkapkan oleh teolog nominalis di akhir abad pertengahan. Ini adalah salah satu ironi besar dalam sejarah, kemudian, bahwa konsepsi mekanika Newton tentang materi alam semesta telah begitu cepat berkembang menjadi murni materialis dan pandangan determinis Pierre Simon de Laplace, yang terakhir ini benar-benar tidak sesuai dengan agama.
G. Geologi, Evolusi dan Usia Planet Bumi
Fisika dan astronomi adalah fokus ilmiah utama bagi para teolog di abad XVII dan XVIII; geologi dan biologi mengadakan tempat analog di abad kesembilan belas dan kedua puluh. Selama berabad-abad, narasi Alkitab tentang Penciptaan sampai tentang Kristus dan Pengadilan Terakhir yang diproyeksikan telah memberikan garis besar kerangka piutang dari alam serta sejarah manusia. Misalnya, kisah Nabi Nuh dan banjirnya menyediakan penjelasan yang berguna tentang fosil laut yang ditemukan di atas permukaan laut. Namun, pada abad ketujuh belas, sejarah rentang pendek yang dihitung dari Alkitab ditantang dari sejumlah arah. (James Ussher, seorang Uskup Agung Irlandia abad ketujuh belas, telah dikreditkan dengan perhitungan bahwa penciptaan terjadi hanya 4004 tahun sebelum Kristus). Meskipun upaya sporadis untuk mendamaikan sejarah geologi dengan kitab Kejadian (Gennesis) berlanjut hingga saat ini, pada abad kedelapan belas besar sejumlah ahli geologi sudah mengakui bahwa hipotesis Banjir tidak bisa menjelaskan pengembangan ilmu pengetahuan tentang stratifikasi batu dan penempatan fosil. Sejarah lebih lama dari Bumi, sebelum sejarah manusia, harus dianggap. Pada saat yang sama catatan Mesir dan Cina memanggil untuk mempertanyakan sejarah jangka pendek manusia jika dihitung dari Alkitab.
Sementara beberapa oposisi kontemporer untuk teori evolusi yang melibatkan “kronologi bumi yang lebih muda”, reaksi negatif kepada buku Charles Darwin, pada abad kesembilan belas, The Origin of Species (1859) yang lebih sering berisi keberatan terhadap Darwinisme sosial dan klaim bahwa manusia berkerabat dengan ‘hewan yang lebih rendah”; reaksi negatif lain berfokus pada kenyataan bahwa seleksi alam telah memberikan sebuah alternatif rancangan ilahi untuk menjelaskan kesiapan organisme dengan lingkungan mereka, sehingga merusak argumen aplogetik yang penting. Meskipun demikian, banyak teolog dan orang beriman lainnya siap menerima teori dan menilai perubahan yang diperlukan dalam teologi untuk menjadi yang bermanfaat daripada sekadar akomodasi, (lihat Darwin, teori Evolution).
Teori evolusi adalah masalah panas yang mengejutkan lagi pada akhir abad kedua puluh. Sebuah jajak pendapat Gallup yang diterbitkan dalam majalah AS News and World Report (23 Desember 1991) melaporkan bahwa mayoritas orang Kristen Amerika Utara skeptis mengenai paradigma evolusi makro. Penjelasan terbaik untuk perlawanan ini mungkin adalah kenyataan bahwa masalah ini telah menjadi dibingkai dalam hal penciptaan, dibandingkan kesempatan sebagai pertimbangan asal-usul spesies manusia. Bahwa masalah dapat dirumuskan dalam hal ini adalah karena sebagian untuk teori tindakan ilahi (yang cacat) yang mengkontraskan tindakan kreatif Tuhan dengan proses alami, daripada membiarkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui proses alam, termasuk yang melibatkan peristiwa acak. Kontroversi ini diperparah oleh penggunaan biologi evolusioner untuk propaganda ateisme.
Ilmu Genetika menyediakan area baru bagi dialog antara agama dan ilmu biologi. Studi menunjukkan dasar genetika tentang karakteristik dan perilaku manusia yang menimbulkan pertanyaan tentang status pribadi manusia – misalnya, pertanyaan tentang kehendak bebas dan determinisme – yang telah menjadi bagian provinsi filsafat dan agama. Kepentingan tertentu adalah studi kembar yang menunjukkan faktor genetik dalam perilaku keagamaan (misalnya, Eaves et al. 1990).
Penelitian genetik secara umum dan rekayasa genetik pada khususnya telah mengangkat sejumlah pertanyaan etis yang berhubungan dengan etika teologis. Sebagai contoh, sementara sebagian orang menikmati pengobatan genetik untuk penyakit, banyak yang menentang intervensi rekayasa genetik, yang akan mempengaruhi semua generasi berikutnya. Beberapa keberatan didasarkan pada posisi kuasi-religius: ilmuwan seharusnya tidak ‘berperan sebagai Tuhan’. Garis batas pemikiran panggilan untuk pemeriksaan teologis: tidakkah manusia itu sendiri diciptakan untuk berpartisipasi dalam proses kreatif Allah yang sedang berlangsung? Perlu dicatat bahwa pada tahun 1991, US National Institutes of Health telah memberikan hibah pertama pernah ke lembaga Pusat Teologi dan Ilmu Pengetahuan Alam (Berkeley, California) untuk mempelajari implikasi teologis dan etis dari Human Genome Initiative, proyek untuk memetakan DNA manusia .
Kosmologi fisik adalah cabang ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Dimulai pada tahun 1920-an, perkembangan di bidang ini telah memicu perdebatan yang hidup yang berhadapan antara teologi dan sains. Teori The Big Bang, yang berdasarkan perluasan alam semesta dan berbagai data lain, mendalilkan bahwa alam semesta berasal dari sebuah ‘singularitas’ yang sangat padat, sangat panas sekitar 15 sampai 20 milyar tahun lalu. Banyak orang Kristen, termasuk Paus Pius XII, telah menyambut teori ini sebagai konfirmasi dari ajaran Alkitab tentang penciptaan. Tidak hanya orang-orang beragama yang melihatnya seperti itu; Frederick Hoyle membela model steady-state (keadaan mapan) alam semesta, di mana atom hidrogen terwujud di seluruh rentang waktu yang tak terbatas, sebagian karena ia melihatnya sebagai lebih kompatibel dengan ateisme-nya .
Diskusi antara para teolog tentang relevansi-kosmologi Big Bang dengan doktrin penciptaan melibatkan kontroversi atas sifat teologi. Sebagaimana disebutkan di atas, telah umum di kalangan teolog liberal sejak Schleiermacher untuk mengklaim bahwa makna religius yang sepenuhnya independen dari fakta ilmiah. Para teolog yang memegang posisi ini mengklaim bahwa doktrin penciptaan, harus melakukan dengan hubungan dari semua yang ada hanya kepada Tuhan, dengan mengatakan apa-apa tentang asal-usul temporal alam semesta, dan karena itu sama-sama kompatibel dengan model kosmologi.
Sebuah wilayah penelitian yang lebih baru yang telah disebabkan spekulasi teologis dapat disebut sebagai masalah prinsip anthropoid. Sejumlah faktor di alam semesta awal harus disesuaikan dengan cara yang sangat tepat untuk menghasilkan alam semesta yang kita miliki. Faktor-faktor ini meliputi massa alam semesta, kekuatan empat gaya dasar (elektromagnetisme, gravitasi, dan kekuatan nuklir kuat dan lemah), dan lain-lain. Perhitungan menunjukkan bahwa jika salah satu dari angka-angka ini telah menyimpang bahkan sedikit dari nilai sebenarnya, alam semesta akan berkembang dengan cara yang sangat berbeda, membuat kehidupan seperti yang kita tahu itu – dan mungkin kehidupan apapun – tidak mungkin. Sebuah contoh dari penyerasan gelombang (‘fine-tuning‘) diperlukan adalah bahwa jika rasio kekuatan elektromagnetisme dengan gravitasi telah bervariasi sebanyak satu bagian dalam 1040, tidak akan ada bintang seperti matahari kita.
Banyak yang mengklaim bahwa penyelarasan gelombang dari alam semesta untuk kehidupan membutuhkan penjelasan. Untuk beberapa orang, tampaknya memberikan dasar untuk argumen desain baru (argumen keberadaan Tuhan). Yang lain percaya bahwa hal itu dapat dijelaskan dalam istilah ilmiah -misalnya, dengan menyarankan bahwa ada jauh lebih banyak alam semesta, baik sejaman dengan kita sendiri atau secara berurutan, yang masing-masing melembagakan konstanta fundamental yang berbeda. Yang satu atau lebih dari alam semesta ini akan diharapkan untuk dapat mendukung kehidupan, dan itu hanya di rupa alam semesta sehingga pengamat akan hadir untuk meningkatkan pertanyaan tentang penyelarasan gelombang. Apakah penyelarasan gelombang diambil sebagai bukti keberadaan Tuhan atau tidak, ia memiliki konsekuensi penting bagi teologi yang beberapa filsuf percaya bahwa itu berpendapat terhadap perhitungan intervensionis melanjutkan penciptaan dan tindakan ilahi, karena prasyarat untuk keberadaan manusia dibangun ke alam semesta dari awal.
Berbagai perkembangan dalam fisika sejak akhir abad kesembilan belas telah mempertanyakan pandangan dunia determinis. Fisika kuantum telah memperkenalkan ketidakpastian ke dalam pandangan dunia fisika. Teori Quantum umumnya memungkinkan hanya untuk prediksi probabilistik mengenai kelas peristiwa, bukan untuk prediksi peristiwa individu. Tidak jelas apakah pembatasan ini hanya mewakili batas pengetahuan manusia, atau apakah itu menandakan ketidakpastian asli di alam. [18]
Namun, pendapat ilmiah cenderung ke arah pandangan yang kedua. Dengan demikian, kebanyakan fisikawan menolak determinisme dari pandangan dunia Newtonian, setidaknya pada tingkat ini. ‘non-lokalitas Quantum’ mengacu pada fakta aneh bahwa elektron dan entitas sub-atom lainnya yang pernah berinteraksi terus berperilaku dengan cara yang terkoordinasi, bahkan ketika mereka terlalu jauh untuk setiap interaksi kausal dikenal dalam waktu yang tersedia. Fenomena ini secara radikal disebut mempertanyakan gambaran alam semesta Newtonian sebagai partikel diskrit yang bergerak, berinteraksi dengan cara kekuatan fisik yang dikenal. Jika determinisme Newtonian memiliki implikasi yang kuat untuk teori tindakan ilahi, itu pasti terjadi bahwa perkembangan dalam fisika kuantum ini harus memiliki implikasi teologis juga. Apa implikasi ini masih sangat banyak pertanyaan terbuka.
Sebuah perkembangan yang lebih baru, yang melintasi fisika dan ilmu-ilmu alam lainnya, adalah teori chaos.[19] Ini adalah studi tentang sistem yang perilakunya sangat sensitif terhadap perubahan kondisi awal. Apa artinya ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari dinamika klasik: gerakan bola biliard diatur dalam cara langsung oleh hukum Newton, tapi sangat sedikit perbedaan dalam sudut dampak tongkat biliard telah sangat memperbesar efek setelah beberapa tabrakan; Selain itu, perbedaan awal yang membuat perbedaan besar dalam perilaku kemudian terlalu kecil untuk diukur, sehingga sistem secara intrinsik tak terduga. Sistem chaos ditemukan di seluruh alam – dalam sistem termodinamika yang jauh dari keseimbangan, dalam pola cuaca dan bahkan pada populasi hewan. Teori chaos relevan dengan diskusi tentang tindakan ilahi bukan karena sistem chaos yang tak tentu (yaitu, tidak ditentukan secara kausal/sebab-akibat) dan dengan demikian terbuka untuk tindakan ilahi tanpa melanggar hukum alam. Sebaliknya pengakuan mana-mana sistem chaos menunjukkan keterbatasan intrinsik dari pengetahuan manusia, dan mengarah pada kesimpulan negatif tetapi penting yang satu ini jarang (atau tidak pernah) dalam posisi untuk tahu bahwa Allah tidak bertindak dalam proses alami.
Perkembangan lain seluruh ilmu pengetahuan dengan implikasi penting bagi masalah determinisme dan tindakan ilahi adalah pengakuan dari ‘penyebab atas-bawah’. Ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai sebuah hirarki di mana ilmu yang lebih tinggi mempelajari sistem yang lebih kompleks: fisika mempelajari hal yang terkecil, komponen yang paling sederhana dari alam semesta; kimia mempelajari organisasi partikel fisik yang kompleks (atom dan molekul); biokimia mempelajari senyawa kimia yang sangat kompleks yang membentuk organisme kehidupan, dan sebagainya. Impian para positivis logis adalah untuk memberikan penjelasan tentang ilmu-ilmu di mana hukum ilmu tingkat tinggi semua bisa dikurangi dengan hukum fisika. Konsep reduksionisme jelas diikuti secara alami dari reduksionisme ontologis yang telah menjadi prinsip penting dari pandangan dunia ilmiah modern: jika semua entitas dan sistem yang pada akhirnya terdiri dari entitas dipelajari oleh fisika, perilaku mereka seharusnya dapat dipahami dalam kerangka hukum fisika. Jadi ontologis dan reduksionisme jelas memerlukan reduksionisme kausal, atau “penyebab atas-bawah’. Jika hukum fisika yang deterministik, kami memiliki perhitungan deterministik seluruh alam. Namun, hal itu telah menjadi jelas bahwa perilaku entitas pada berbagai tingkat hirarki kompleksitas tidak selalu bisa dipahami sepenuhnya dari segi perilaku bagian mereka; memperhatikan interaksi mereka dengan fitur non-tereduksi dari lingkungan mereka juga diperlukan. Dengan demikian, negara atau perilaku dari sistem-tingkat yang lebih tinggi penerapan pengaruh kausal atas-bawah pada komponen-komponennya.
Arthur Peacocke (1990) telah menggunakan perkembangan ini dalam pemikiran ilmiah untuk mengusulkan arah baru untuk memahami tindakan ilahi. Dalam padangan bukunya ‘panentheist’, alam semesta adalah ‘ada di dalam’ Tuhan Allah, dan pengaruh Tuhan di alam semesta kemudian dapat dipahami oleh analogi dengan penyebab atas-bawah seluruh hirarki tingkat alami. Sementara usulan ini tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana Allah mempengaruhi peristiwa tertentu dalam kosmos, itu membubarkan masalah lama determinisme kausal.
- Kritik terhadap Modernisme
Hal ini sangat penting bagi kami sebagai pemikir muslim untuk memahami paradigma modernisme dalam cara yang lebih kritis dan lebih komprehensif, dalam pandangan integral dan holistik, baik dalam dasar analisis filosofis-agama dan juga dalam pengaruh dan efek negatif yang disebabkan oleh paradigma modern yang memimpin dan mengarahkan banyak aspek dan dimensi budaya, ilmu, peradaban manusia dan ekologi di bidang hegemonik Filsafat Modern Barat di sebagian besar bagian dari dunia baru-baru ini secara global.
Dalam menggambarkan penderitaan manusia modern Seyyed Hossein Nasr dengan tegas menulis:
“Manusia modern telah membakar tangannya dalam api yang ia sendiri telah nyalakan ketika ia membiarkan dirinya lupa siapa diri dia. Setelah menjual jiwanya dalam cara Faust untuk mendapatkan kekuasaan atas lingkungan alam, ia telah menciptakan situasi di mana kontrol lingkungan sangat berubah menjadi pencekikan, yang membawa di belakangnya tidak hanya pemusnahan lingkungan, tetapi juga, pada akhirnya, tindakan bunuh diri”.[20]
Krisis multidimensional kita baru-baru ini hari ini harus diidentifikasi, dianalisis, dan dikaji untuk memecahkan banyak masalah yang disebabkan oleh pelaksanaan paradigma modernisme dan post-modernisme (barat).
Merujuk kepada Seyyed Hossein Nasr, penyebab krisis multi-dimensional manusia modern adalah krisis eksistensial. Nasr mengatakan:
“Dunia masih terlihat oleh Kekuatan dan elemen yang mengatur sebagai cakrawala tanpa kehadiran spiritualitas, tetapi juga karena mereka yang memandang lanskap kontemporer adalah manusia yang paling sering tinggal di tepian lingkaran roda eksistensinya dan karena itu memandang segala sesuatu dari pinggiran. Dia tetap acuh tak acuh terhadap jari-jari dan benar-benar tidak menyadari sumbu dan Pusat, yang bagaimanapun tetap tak pernah diakses kepadanya melalui mereka. ” [21]
Menurut pendapat saya, apa yang Nasr bicarakan tentang krisis eksistensial manusia modern adalah sangat benar. Karena mereka telah melupakan realitas keberadaan eksistensial mereka sebagai makhluk spiritual di luar casing jasmani mereka, dan mereka telah lupa sumber utama dari mana mereka datang, dan ke mana hidup mereka akan berakhir dan jiwa mereka akan kembali, maka kehidupan duniawi untuk manusia modern itu tak berarti dan tanpa-guna. Dari tradisi Islam kita tahu beberapa hadits itu; “Siapa pun yang telah lupa diri mereka, mereka akan lupa Tuhan Allah mereka”, “Siapa yang tahu diri mereka, sehingga mereka akan mengetahui siapa Tuhan Allah mereka”.
Lebih jelas, kelupaan manusia modern ini pada Realitas eksistensial mereka digambarkan oleh Nars sebagai berikut:
“Masalah kehancuran lingkungan akibat kemajuan teknologi, krisis ekologi dan sejenisnya, semua masalah derita manusia modern serta post–modern berasal dari penyakit amnesia atau lupa diri dari mana manusia berasal. Manusia modern telah lupa siapa diri dia yang sebenarnya. Mereka hidup di pinggiran lingkaran eksistensinya sendiri, ia telah mampu untuk mendapatkan pengetahuan secara kuantitatif mengejutkan tentang dunia tetapi secara kualitatif dangkal. Dia telah memproyeksikan citra externalized dan dangkal dirinya atas dunia.”[22]
Menurut Armahedi Mahzar dalam teks Pendahuluannya untuk buku karya Hussain Heriyanto tentang “Paradigma Holistik”, bahwa dalam pertengahan abad yang lalu, telah disadari perlunya adanya perubahan paradigma atau kecenderungan merubah paradigma yang lebih baru dalam ilmu pengetahuan. Paradigma adalah asumsi filosofis yang menjadi dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar untuk setiap bidang peradaban seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma yang dominan di awal abad terakhir adalah paradigma materialistik-mekanistik yang dikenal sebagai Paradigma Cartesian-Newtonian.[23]
Keberhasilan teori gravitasi dan mekanika Newton, yang telah diperkuat dengan teori lain seperti metode hipotetik deduktif yang rasional-spekulatif yang dikembangkan oleh Rene Descartes, dengan metode eksperimen-induktif dan obyektif-empirik berlebihan, yang dikembangkan oleh Roger Bacon.
Descartes telah mencoba untuk menemukan sebuah filosofi yang tak tergoyahkan dalam rangka memerangi sikap skeptis, ia menggunakan indubtability (tidak meragukan) keraguan dirinya sebagai landasan filsafatnya (“Aku Berfikir maka Aku Ada” / “Co gito ergo sum”). Selain itu, adanya ego dari peragu dan pemikir adalah wajar didasarkan pada fondasi itu. Dia memperkenalkan kejelasan dan keunikan sebagai kriteria indubitability, yang ia membuat standar untuk membedakan ide-ide yang benar dari ide-ide yang salah. Dia juga berusaha untuk menggunakan pendekatan matematis untuk filsafat, dan bahkan berusaha untuk memperkenalkan logika baru.
Oleh karena itu, untuk mulai dengan keraguan sebagai titik awal untuk berdebat dengan kaum skeptis adalah wajar. Namun, jika seseorang membayangkan bahwa tidak ada yang begitu jelas dan pasti, dan bahkan keberadaan peragu harus disimpulkan dari keraguan, ini tidaklah akan valid. Sebaliknya keberadaan ego sadar dan berpikir setidaknya sama jelasnya dan tentu sebagai adanya keraguan itu sendiri yang merupakan salah satu dari negara-negara tersebut.
Pemikiran Descartes sangat layak untuk dihargai dalam memerangi skeptisisme di jamannya, tetapi kita tidak dapat menerima ide utamanya tentang ‘cogito ergo sum’ (“Aku Berfikir maka aku Ada”),[24] karena, ide utama Descartes (dengan ide Newtonian tentang prinsip-prinsip mekanik) adalah dasar-dasar yang telah mengembangkan dan mendirikan paradigma materialistik dan mekanistik pada filsafat Barat dan ilmu Pengetahuan. Paradigma materialistik–mekanistik ini, dan sekularisme, bertentangan dengan filsafat Islam tentang Eksistensi Spiritual dan Realitas Tunggal.
Paradigma materialistik-mekanistik dalam sains, yang berdasarkan pada metode Cartesian dan Newtonian tentang “hipotesa (deduktif)-eksperimental (induktif)”, telah membawa kecenderungan reduksionisme-materialistik. Oleh karena itu, kehidupan, bahkan kesadaran telah dikurangi menjadi dipandang hanyalah sekedar merupakan gerakan mekanistik-material belaka. Arus utama ide sekuler ini menyebar dan mempengaruhi berbagai bidang filsafat-ideologi, budaya dan ilmu pengetahuan kehidupan manusia modern. Misalnya Adam Smith berbicara tentang “mekanisme pasar” mengenai ekonomi, Charles Darwin dalam biologi berbicara tentang “mekanisme evolusi” dan psikolog Sigmund Freud, bicara tentang “mekanisme pertahanan psikologis”. Semuanya serba mekanis.
Mekanisme-Reduksionisme ini, yang berakhir pada ontologi atomistik dan mekanistik ini, secara otomatis menolak dan mengabaikan peran ilahi di alam semesta (sekularisme) dan bahkan meniadakan keberadaan Tuhan. Hal ini bertentangan dengan realitas dan keyakinan pokok tradisi suci dan agama-agama dunia dan terutama Islam.
Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Armahedi Mahzar, M.Sc dalam ceramahnya tentang Filsafat Ilmu Islami di ICAS Paramadina University: “Dominasi Paradigma Cartesian-Newtonian pada ilmu pengetahuan modern, telah membawa dan menjebak peradaban manusia kepada kegelapan krisis multidimensi bagi kehidupan manusia. Krisis ini, baik berupa krisis internal maupun eksternal. Krisis internal paradigma ini ditunjukkan oleh Prinsip Relativitas Einstein, prinsip Heisenberg tentang “ketidakpastian, dan Teorema Gödel tentang “ketidaklengkapan”.
Krisis eksternal ilmu modern (yang ber-Paradigma Cartesian-Newtonian/ materialistik-mekanistik) ini yang menyebabkan beberapa masalah kritis seperti: pemusnahan massal manusia oleh militer dengan senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis pemusnah massal; degradasi lingkungan yang disebabkan oleh depletions, polusi, degradasi, dan kehancuran lingkungan; fragmentasi sosial yang disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi & fragmentasi sosial; keterasingan psikologis manusia dari lingkungan alam, sosial, dan teknologis. [25]
Kritik eksternal terhadap ilmu pengetahuan modern terjadi pada setidaknya tiga kritik :
- Teologi (ilmu pengetahuan bersifat parsial dengan menolak Realitas Supernatural),
- Filsafat :
- Kritik filosofis fenomenolog (ilmu hanyalah men-skema-kan pengalaman manusia);
- Kritik filosofis Post-strukturalisme (ilmu hanya cerita lain);
- Kritik ideologis yang dilakukan oleh kaum:
- Neo-Marxisme (bahwa ilmu pengetahuan hanyalah untuk kepentingan pemodal),
- Neo-Feminisme (bahwa ilmu pengetahuan hanyalah untuk kepentingan laki-laki),
- Ekologi Radikal (bahwa ilmu pengetahuan adalah hanya untuk kepentingan manusia, bukan lingkungan) &
- Etnisis Agama (bahwa ilmu pengetahuan adalah hanya untuk kepentingan orang ras kulit putih).[26]
Sebagai kesimpulan hipotetik, ternyata kita dapat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern tidaklah benar-benar lengkap, tidaklah rasional, tidaklah objektif, dan tidaklah netral. Mengapa hal itu dapat terjadi dalam ilmu modern atau paradigma Cartesian-Newtonian? Pertama, menurut teori penulis, hal itu mungkin disebabkan oleh epistemologi ilmu pengetahuan modern terlalu ‘over-rasionalisme’, ‘over-empirisme’, ‘over-reduksionisme’, alias lebay (berlebihan pada aspek rasionalisme-empirisme dan reduksionisme semua fakta alam semesta). Epistemologi semacam ini lebih mempengaruhi paradigma ontologis, berupa: materialisme, mekanisme, atomisme; dan membawa paradigma aksiologis tentang netralisme, humanisme dan individualisme.
Jadi kalau kita ingin selamat dunia-akhirat, kita harus mau meninjau ulang dan merekonstruksi paradigma sains dan kemanusiaan kita menjadi paradigma holistik dan integral sesuai dengan arah prinsip Tauhid Islam tentang Ketuhanan, alam dan manusia. Yang pertama-tama, kita harus memulainya dari rekonstruksi epistemologisnya. Oleh karena itu, di sini dalam buku ini saya ingin mengkaji dan melakukan rekonstruksi dalam pikiran kita untuk mencari jalan keluar dan solusi filosofis untuk memecahkan masalah utama dan krisis kehidupan manusia dan peradaban modern yang sedang sakit dan sekarat ini.
Dalam pemikiran Seyyed Hossein Nasr, untuk tujuan melakukan rekonstruksi terhadap paradigma baru ini, seperti untuk memecahkan masalah krisis modernisme, solusi multidimensi yang penting, yang paling signifikan dan relevan adalah bahwa kita harus kembali kepada Worldview (pandangan dunia) Tradisional kita yang merupakan Ilmu Pengetahuan Suci/Sakral/Divine/Ilahiyah, yang merupakan Sophia Perrenialsme dan Metafisika Transenden yang masih memainkan peran sebagai fundamen filosofis mendasar dan pondasi kecerdasan spiritual-intelektual yang holistik dan integral dari umat manusia sepanjang zaman lintas peradaban.
Dalam buku What Is Traditions, S.H. Nasr menjelaskan hubungan antara tradisi dan agama-agama dari perspektif filsafat perennial yang dapat diringkas sebagai berikut: sifat tradisi adalah merangkul semua agama, dan pada agama itulah terletak asal-usul tradisi tersebut. Dipahami dalam pengertian agama ini adalah apa yang mengikat manusia dengan Tuhan dan pada saat yang sama mengikat orang-orang satu sama lain. Agama Hindu dan Buddha Dharma, al-Din al-Islam, agama Tao, dan yang sejenisnya, adalah erat terkait dengan makna dari tradisi panjang tersebut, tapi tidak identik dengan itu, walaupun tentu saja dunia atau peradaban yang diciptakan oleh Hindu, Buddha, Taoisme, Yahudi, Kristen, Islam, atau dalam hal ini agama otentik lainnya, adalah dunia tradisional (SH Nasr, 1989, hal.67).
Dari perspektif itu, tradisi, karena itu bertentangan prinsip modernisme. Tradisionalisme ini seolah ingin menumbangkan kejahatan dunia modernisme dalam rangka menciptakan sesuatu kehidupan yang normal (Needleman [end] 1974). Tujuannya bukan untuk menghancurkan apa yang positif dari dunia modern, tetapi untuk menghapus selubung ketidaktahuan dan kebodohan yang memungkinkan ilusi muncul sebagai kenyataan, yang negatif sebagai positif dan yang palsu sebagai benar (SH Nasr 1989).
Sebagaimana Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara telah tulis dalam makalahnya bahwa: “Jika kita membandingkan antara perlakuan filosofis atau tantangan dalam 1.000 tahun yang lalu, tantangan filosofis yang dihadapi oleh umat Islam saat ini lebih serius dan lebih radikal, karena tantangan yang dihadapi oleh al-Ghazali pada zaman itu berasal dari filsuf yang masih sangat percaya dengan realitas metafisik, tetapi tantangan yang dihadapi oleh Muslim Intelektual hari ini berasal dari filsuf dan ilmuwan yang telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan YME dan pada pondasi metafisik lainnya.”[27]
Tidak cukup dengan itu, mereka juga telah menyebarkan pandangan anti-metafisik mereka dengan menyerang landasan metafisik seperti dikatakan sebagai ilusi (khayalan) dan tak berarti. Jadi tantangan yang lebih dan lebih serius dan radikal, karena mereka tidak hanya memberikan penafsiran non-ortodoks dengan realitas metafisik, tetapi juga mereka melakukan negasi/penolakan itu dengan menyerang status ontologis dari realitas metafisik itu sendiri .
Tantangan filosofis yang paling berbahaya untuk dunia metafisik yang berasal dari “Positivisme“. Menurut pandangan Positivisme, satu-satunya realitas yang ada adalah bahwa kenyataan “positif”, hanyalah yang dapat teramati oleh indera. Semua yang di luar dunia fisik (metafisika) hanyalah dianggap spekulasi pikiran manusia yang belum tentu kebenaran realitas ontologisnya dari kesadaran manusia. Konsep-konsep keagamaan pada Tuhan, akhirat, malaikat, dan makhluk ghaib lainnya, diasumsikan sebagai ciptaan pikiran manusia pada awal dari perkembangan mereka. (sebagaimana pandangan Freud). Pada perkembangan selanjutnya, manusia merevisi konsep agama mereka dengan mengembangkan sistem filosofis yang lebih rasional. Tapi pandangan terakhir itu, menurut mereka, masih berbasis ilusi karena mereka masih percaya pada dunia metafisik. Yang terbaru dan paling sempurna dalam perkembangan pemikiran manusia adalah di tingkat positivisme, di mana manusia menemukan bahwa satu-satunya yang dianggap benar dari realitas hanyalah dunia fisik yang dapat diverifikasi secara obyektif dan positif. Apa yang mereka dapat hasilkan bukanlah sistem kepercayaan religius atau sistem filsafat rasional tetapi ilmu berdasarkan pengamatan akal semata.
Pengaruh positivisme yang lebih besar – dan tentu saja lebih berbahaya sebagai tantangan filosofis dan teologis agamawan – bagi kita – karena mereka memiliki banyak pendukung dari para ilmuwan dari berbagai disiplin, seperti astronomi, biologi, psikologi dan bahkan sosiologi. Pengaruh itu bisa dilihat misalnya, dari tidak sukanya banyak ilmuwan untuk melihat entitas metafisik, seperti Tuhan atau malaikat, sebagai penyebab utama dan sumber untuk alam semesta. Dalam pandangan mereka, Tuhan telah berhenti menjadi apa pun. Dia telah berhenti sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dan manajer dari alam semesta. Mereka lebih memilih untuk melihat alam semesta sebagai mekanika raksasa yang dijalankan oleh hukum alam, dan fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh hukum alam semesta daripada menganggap sebagai ciptaan Tuhan.
Pandangan naturalis positivis ini mudah diketemukan dalam karya-karya atau pernyataan dari ilmuwan Barat yang terkenal dan berpengaruh, seperti Pierre de Laplace, Darwin, Freud, dan Emile Durkheim. Meskipun tidak semua ilmuwan setuju dengan pandangan mereka, tetapi pengaruh mereka dalam ilmu alam masih besar dan dominan. Mereka masih dianggap sebagai “nabi ilmu pengetahuan”. Jadi pemikiran mereka masih memiliki tantangan substantif dan mengancam sistem keimanan Islami. Pierre de Laplace (w. 1827), seorang astronom dan matematikawan Perancis yang dikenal sebagai penemu teori “Big Bang” (bersama-sama dengan Emanuel Kant), merasa tidak perlu bicara tentang Tuhan, ketika dia menjelaskan teori penciptaan alam semesta dalam bukunya The Celestial Mechanism. Alasannya adalah, baginya, Tuhan Allah adalah hipotesis yang tidak diperlukan dalam penjelasan astronomi, atau dalam pernyataannya sendiri nya: “Je nai pas besoin de cet hypothesie. “
Charles Darwin (w. 1882) seorang naturalis Inggris yang terkenal dengan teori evolusinya, menyatakan bahwa semua makhluk biologis di alam semesta ini bukan Ciptaan Tuhan Allah Yang Maha Bijaksana, tetapi hanya hasil dari hukum mekanisme seleksi alam. Dalam otobiografinya, Darwin mengatakan: “Ada waktu sebelumnya, dapat dikatakan bahwa bukti keberadaan Allah adalah harmoni dan ketertiban alam. Tapi setelah teori seleksi alam ditemukan, kita tidak bisa mengatakan bahwa kapak bersama kerang laut yang indah, harus menjadi makhluk agent luar dirinya (Tuhan), sama seperti kita mengatakan bahwa engsel sambungan pintu bersama kapak bukan ciptaan Tuhan.”
Pengaruh pandangan positivisme juga muncul dalam Sigmund Freud (w. 1939), seorang dokter dan penemu psiko-analisis. Dalam bukunya The Future of an Illusion, Freud melihat agama sebagai ilusi ini yang berasal dari ketidak-berdayaan manusia dalam menghadapi kekuatan alam eksternal dan daya imajinatif internal dalam dirinya sendiri. Kebangkitan agama dalam waktu yang pertama dari perkembangan umat manusia, ketika mereka belum menggunakan akal mereka (rasio) untuk menghadapi dunia eksternal dan dunia internal, sehingga mereka harus mengontrol dan menekan daya eksternal tersebut dengan bantuan eksternal yang efektif. Karena mereka tidak dapat mengontrol dengan akal mereka, sehingga kebutuhan “kontra efek emosional” untuk mengontrol dan menekan apa yang dia tidak bisa menanggungnya secara rasional. Jika agama dipandang sebagai ilusi, maka secara otomatis agama yang percaya dengan realitas metafisik seperti Allah, malaikat, roh dan akhirat juga dianggap khyalan/ilusi. Itu masalah sama yang telah menjadi pemikiran filsuf Perancis dan sosiolog Emile Durkheim (w. 1917). Dalam karya-karyanya, ia melihat agama hanya sebagai proyeksi dari nilai-nilai sosial, dan Tuhan hanyalah ciptaan masyarakat itu sendiri, dan bukan entitas pribadi metafisikal, seperti yang kita percayai.
Serangan untuk metafisika juga dilakukan terhadap sistem Epistemologi Islam, terutama yang berkaitan dengan sumber-sumber pengetahuan. Karena negasi/penolakan ke dunia metafisik, sehingga satu-satunya sumber pengetahuan, untuk kaum positivis hanyalah pengalaman, atau dalam kata lain, sesuatu yang masuk akal. Mereka tidak percaya kepada sumber-sumber lain, yang sangat penting dalam Epistemologi Islam, seperti: akal, intuisi dan wahyu dari Allah. Laplace mengatakan: “Saya tidak mempercayai apa pun kecuali akibat langsung dari pengamatan dan perhitungan.” Jadi mereka tidak percaya pada wahyu dan juga “pengalaman mistik” sebagai salah satu sumber pengetahuan. Meskipun dalam tradisi epistemologi Islam, bahwa ada tiga sumber pengetahuan – yang Mulla Sadra (w.1050/1640) seorang filsuf muslim di abad ke-17, sebut sebagai ” burhan, irfan dan Qur’an“- yang diterima sebagai sumber pengetahuan yang valid sebagai yang hal yang sama dengan akal inderawi.[28]
Kaum Positivis, tentu saja, hanya menerima indra (via pengamatan) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid dan satu-satunya yang terpercaya. Sumber pengetahuan lainnya, seperti wahyu dan intuisi, dianggap tidak bisa dipercaya karena tidak mendasarkan pada realitas tetapi pada ilusi manusia. Alasan mengapa mereka mengatakan itu adalah karena wahyu dan pengalaman mistik membutuhkan hubungan yang erat dengan alam metafisik, sehingga validitasnya tergantung pada status keberadaan (ontologi) metafisika alam itu sendiri. Setelah keberadaan alam metafisik ditolak, maka validitas sumber pengetahuan – yang bergantung pada mereka – juga secara otomatis ditolak. Karena wahyu dan pengalaman mistik memiliki karakteristiknya, maka validitas mereka dapat diterima jika kita menegaskan status ontologis wilayah metafisiknya. Sekali keberadaan realitas yang ditolak, maka kemungkinan adalah, bahwa wahyu dan pengalaman mistik yang didasarkan pada mereka juga ditolak secara otomatis dan dianggap tidak memiliki dasar logis. Bahkan kita tahu apa yang terjadi jika wahyu (dalam hal ini al- Qur’an) ditolak sebagai sumber pengetahuan yang valid, sehingga semua sistem kepercayaan, teologi, dan filsafat-mistik Islam akan runtuh. Inilah yang Prof. Mulyadhi Kartanegara sebut sebagai tantangan filosofis kontemporer serius dari positivisme Barat yang telah menganggap tiadanya Sistem Epistemologi Islam. Maka Kita sebagai intelektual muslim memiliki kewajiban untuk memberikan respon filosofis yang sama, bahkan lebih baik dan lebih meyakinkan daripada argumen mereka.[29]
Tantangan lain yang berkaitan dengan serangan dari kaum positivis terhadap metafisika, juga telah mempengaruhi bangunan etika Islam, baik secara agama dan secara filosofis, tentu saja sampai tingkat tertentu berdasarkan perintah Allah SWT. Tetapi jika keberadaan Tuhan itu sendiri sebagai entitas metafisik ditolak, ajaran etika Islam sehingga kehilangan dasar mereka. Freud mengatakan: “Jika validitas norma etika berdasarkan Perintah Tuhan, sehingga masa depan etika berdiri dan runtuh dengan ada atau tidak adanya Kepercayaan pada Tuhan. Dan karena Freud menganggap bahwa bila iman keagamaan menghilang, jadi dia percaya bahwa jika kita mempertahankan hubungan antara agama dan etika, itu akan menghancurkan nilai-nilai moral untuk dirinya sendiri. “
Oleh karena itu, bagi modernism Freud, satu-satunya sistem etika yang mereka terima adalah sistem etika humanisme saja, berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan manusiawi, bukan berasal dari sumber transenden lainnya. Untuk mereka, apa yang disebut sebagai wahyu, yang tidak sekedar pemikiran manusia (dalam hal ini: Nabi), dan bukan sebagai emanasi (pancaran ciptaan) dari alam ilahi, yang mereka tolak keberadaannya. Jadi, nilai-nilai apa saja yang ada dalam wahyu dilihat tidaklah mutlak dan tidak dapat diterapkan untuk sepanjang waktu, seperti yang diyakini oleh pengikutnya. Wahyu, untuk mereka serta pemikiran manusia lainnya, dan tentu saja relatif dan tenggelam di bawah perubahan ruang dan waktu, sehingga dapat berubah jika diperlukan oleh zaman. Ini adalah pandangan kaum positivis tentang nilai-nilai etika skriptural, yang serta karya-karya filsafat umum, yang aneh dan tidak stabil terhadap perubahan dan bahkan total wajib dikoreksi .
Kritik yang sama juga ditujukan kepada pengalaman mistik mereka dan keabsahannya sebagai etika yang bias. Kaum Positivis pernah mengasumsikan pengalaman mistik sebagai salah satu halusinasi. Bahkan mereka mengalamatkan validitas pengalaman intelektual yang mendukung realitas metafisik. Semua itu mereka lakukan karena mereka telah kehilangan iman kepada alam metafisik. Bagi mereka, satu-satunya dasar yang dapat kepercayaan untuk etika adalah justru pengetahuan berdasarkan pengalaman dengan alam. Etika menurut Freud tidak didasarkan pada kepercayaan agama yang merupakan “ilusi”, tapi dengan memberdayakan akal manusia.
Ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Cendekiawan Muslim saat ini, tantangan yang lebih radikal dan serius dari tantangan yang dihadapi oleh Muslim Intelektual pada saat al-Ghazali.[30]
- L. Krisis Eksistensial: Sumber Krisis Multidimensional
Menurut Dr. Hussein Heriyanto, dunia Eropa abad keenam belas telah menyatakan kedaulatan manusia itu sendiri. Dengan berakar pada rasionalisme, manusia (di Barat/Eropa) merasa telah menemukan identitasnya melalui gerakan renaissance, dengan filsafat antroposentrisme/pemikiran modern, reformasi dan pencerahan (enlightenment/Aufklarung). Dengan motto Sapere Aude (berani berpikiran sendiri! ) manusia menghendaki otonom dan bebas dari segala belenggu otoritas dan tradisi (agama & budaya). Zaman Aufklarung, abad ke-18 Masehi, adalah puncak dari kekuatan optimisme dan rasionalisme sebagai pengganti kesejahteraan pembawa obor iman umat manusia.[31]
Manusia modern telah memberontak terhadap cara pandang metafisik atau pemikiran teologis. Langit suci dihancurkan oleh interpretasi prematur kosmologi Copernican. Ilmu pengetahuan transendental Ilahiyah didesakralisasi (sekularisasi) melalui rasionalisme dan empirisme. Pesona alam semesta ini dihancurkan oleh ‘cogito ergo sum’ dari Descartes dan mekanika Newton. Agama dan gereja bersama-sama dengan pendetanya lah yang meminggirkannya. Nilai-nilai moral tradisional dibuang. Norma agama dikatakan sebagai belenggu kebebasan dan otonomi subjek.
Seiring dengan perkembangan kesadaran modernitas, sekularisasi adalah menjadi klaim historis dan kesadaran manusia modern. Sekularisasi adalah suatu proses di mana manusia berpaling dari “dunia luar” (di luar dunia atau akhirat) dan hanya terfokus pada “kehidupan di sini dan sekarang”. Dengan sekularisasi ini, orang-orang merasa bebas dari kontrol dan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Kesadaran sekuler diwujudkan dalam pemisahan agama dari dimensi kehidupan, terutama dalam bidang sains, sosial, ekonomi, dan politik. Agama hanya dipandang sebagai fenomena warisan budaya dan manusia. Agama hanyalah subjek belaka antropologi dan sejarah.
Pendulum peradaban manusia, yang mengarah kepada pemberontakan terhadap agama manusia modern, terus terjadi. Setelah agama, teologi dan metafisika berhasil dihapus dari wacana ilmiah, kehidupan sosial dan kemanusiaan, dengan membuatnya hanya sebagai urusan murni individual; pemberontakan diarahkan langsung ke jantung keyakinan agama, yaitu Tuhan Allah. Feuerbach menyebutkan bahwa yang disebut Tuhan itu tidak lain adalah cita-cita (ciptaan pikiran) manusia, yang hanya merupakan proyeksi dari nilai-nilai harapan kemanusiaan itu sendiri, seperti pengetahuan, kekuasaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Feuerbach mengusulkan untuk menghapuskan dan menggantinya dengan teologi antropologi. Karl Marx menyebutkan Tuhan sebagai karakter atau konsep penemuan kapitalis-borjuis untuk membius kaum proletar. Kemudian Nietzsche menyatakan pembebasan kematian Tuhan sebagai puncak dari swasembada manusia.
Namun, tidak cukup berhenti di situ, oposisi sekuler dan pelecehan ateisme terhadap agama terus berlangsung. Kaum Positivis ini menilai agama sebagai satu susunan khayalan (ilusi dan delusi) apa pun, karena mereka tidak dapat diverifikasi secara logis ilmiah. Freud bahkan menyebutkan kesadaran beragama adalah produk atau sublimasi dari aspirasi libido seksual yang tidak dapat disalurkan; bahwa orang-orang beragama adalah orang-orang yang memiliki penyakit mental.
Jarum jam sejarah terus bergerak. Abad ke-20 adalah masa menuai badai. Psikoanalisis Freud tidak hanya menghina agama. Melampaui harapan manusia modern, sejauh ini menjatuhkan prestise dan kebanggaan rasionalitas psikoanalisis dan kesadaran otonomi subjek. Freud yang sangat dipengaruhi oleh Darwinisme, mengumumkan hasil penelitiannya, bahwa sebagian besar perilaku manusia didorong oleh libido biologis semata, insting bawah sadar hewaniyah; bahwa rasio kesadaran manusia yang dimainkan hanyalah sedikit seperti dari puncak gunung es di lautan yang merupakan alam bawah sadar manusia. Darwinisme dan Freudianisme telah mengguncang pilar keimanan manusia modern dengan kehebatan rasio.
Abad ke-20 dan 21 adalah abad menuai badai. The “New Left“, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Mazhab Frankfurt melengkapi kejatuhan rasionalitas modernisme. Melalui analisis filosofis-sosiologis dan psikoanalisis, mereka mengekspos perilaku masyarakat modern seperti keserakahan terhadap sumber daya alam, irasionalitas, konsumerisme, tirani, hegemoni, fasisme, tribalisme. Horkheimer mengatakan bahwa kebebasan individu saat ini adalah palsu, karena kebebasan hanya dibayangkan saja, sementara pada kenyataannya individu secara tidak sadar diperbudak oleh masyarakat yang didorong oleh kekuatan pasar dan modal. Individu dan masyarakat modern didorong oleh “kekuatan impersonal” kapitalisme-konsumerisme yang digaungkan oleh dunia periklanan dan hiburan, dan pasar raya (mall), dan pasar modal. “Kekuatan impersonal” itu siang-malam menarik dan menjanjikan semua harapan. Orang-orang modern terpesona dengan slogan iklan dan hiburan, dan mereka bersedia untuk memberikan diri mereka diperbudak oleh “kekuatan impersonal”. Manusia modern telah menjadi robot dan sekrup kecil mesin sosial yang tidak bisa lagi berpikir jernih memilih apa yang benar-benar baik baginya, berdasarkan sifat kesadarannya sendiri.
Akibatnya, proyek pembebasan manusia, yang diprakarsai oleh renaissance, reformasi, dan Aufklarung telah gagal, karena manusia modern telah dibelenggu oleh mitos-mitos baru, berhala baru, ilusi baru, takhayul baru, dan dewa-dewa baru, yang diromosikan secara intenfif dan masif serta global oleh kekuatan intelektual konspirasi illuminati-freemasonry global.
Dunia di abad ke-20 sampai ke awal abad 21, telah menuai badai. Perkembangan terbaru dari setiap ilmu pengetahuan, melampaui harapan dan harapan manusia modern, manusia modern telah merusak kepercayaan dari pemahaman ilmiah positivisme[32], yang tampaknya sejauh ini menjadi dua pilar iman mereka .
Munculnya fisika modern dengan munculnya teori relativitas Einstein dan Mekanika kuantum telah merubuhkan teori mekanika klasik dan paradigma mekanistik-positivis Newtonian yang selama tiga abad dianut oleh manusia modern. Alam semesta faktual adalah misteri yang ternyata menyimpan review tak berujung. Kesadaran muncul pada manusia modern, terutama di kalangan akademisi dan berpendidikan, bahwa mereka belum tahu apa-apa tentang seluruh alam semesta dan realitas; bahwa manusia secara faktual dan alam semesta saling berhubungan secara mendalam.
Kesadaran ini, untuk mereka yang berpendidikan, dapat menghancurkan keinginan manusia modern untuk membungkuk dan mengeksploitasi alam, karena secara bersamaan alam telah memberontak terhadap eksploitasi sewenang-wenang manusia, dalam bentuk polusi udara, air dan tanah, memanasnya iklim dan cuaca global, penipisan lapisan ozon. Pada tingkat teori, yaitu epistemologi dan kosmologi, kesadaran yang mengguncang kepercayaan manusia modern dalam ilmu pengetahuan. Akibatnya, pergerakan skeptisisme dan nihilisme yang telah dikembangkan yang tidak lagi memiliki apresiasi ilmu pengetahuan dan juga bahkan, terhadap semua pengetahuan manusia. Generasi sofisme modern telah dilahirkan kembali. Manusia telah mundur 2500 tahun kembali ke zaman sofisme Yunani klasik .
Abad ke-20 ke abad ke-21 menuai badai. Ilmu pengetahuan dan teknologi diandalkan oleh manusia modern untuk mencapai kebahagiaan ternyata berbalik mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Dua perang dunia yang besar telah terjadi dengan ratusan juta korban manusia dengan rekayasa teknologi senjata. Berbagai senjata canggih, mulai dari senjata kimia untuk bom nuklir, yang dirancang untuk membunuh banyak manusia, atau setidaknya digunakan untuk mengancam dan menggertak negara-negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap negara-negara yang tidak mau menyerah kepada arogansi Amerika Serikat & Israel.
Manusia modern melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara faktual tidak berkorelasi positif terhadap kesejahteraan umat manusia. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di ulang tahun PBB 24 Oktober 1999 lalu, menyebutkan bahwa abad ke-20 sebagai abad paling gelap dan paling keras dalam sejarah umat manusia, abad yang paling ramai dengan cerita penderitaan manusia. Para pemikir yang bijaksana dan intelektual akan mengkhawatirkan munculnya berbagai bencana kemanusiaan dan bencana alam di abad ke-21 mendatang[33]. Oleh karena itu, Anthony Giddens menyebutkan saat ini ditandai dengan ketidakpastian yang diproduksi yaitu periode ketidakpastian dan menyebabkan konsekuensi risiko tinggi.[34]
Kisah penderitaan manusia untuk menemukan realitasnya sendiri, belum berakhir. Krisis modernisme tidak berhenti pada irasionalitas dan krisis moral, krisis epistemologis, krisis ekologi dan krisis kekerasan saja. Tapi krisis modernisme, yang juga melanda Indonesia, tidak berhenti hanya pada krisis epistemologis dan metodologis seperti ini. Lebih akut, terjadi pada tingkat ontologis berkenaan dengan krisis eksistensial manusia mengenai sifat, tujuan dan makna dalam hidupnya. Manusia modern telah dilemparkan ke dalam sebuah krisis eksistensial, kehampaan spiritual, krisis legitimasi makna dan misi hidupnya, serta kehilangan penglihatan dan terasing dari alam semesta, dari Tuhan dan dirinya sendiri. Albert Camus menjelaskan bagaimana segala upaya manusia untuk menemukan esensi dari siapa dia, selalu bertemu dengan kegagalan, sehingga sampai kesimpulan bahwa hidup ini adalah tidak masuk akal, tidak memiliki arti. Kehidupan adalah seperti orang yang berjuang untuk mendaki gunung tanpa harapan tidak akan pernah mencapai tujuan. Albert Camus sehingga mempertanyakan mengapa manusia, yang tidak tahu dan tidak punya tujuan dalam hidup masih akan hidup di dunia yang tidak berarti ini. Mengapa manusia tidak lebih baik bunuh diri?
Abad ke-20 abad ke-21 menuai badai. Setelah 6 abad manusia menyatakan kedaulatannya dan menyatakan kematian Tuhan sendiri, situasi sekarang terbalik. Jarum sejarah telah mengguncang sendi kepercayaan manusia modern; rukun iman mereka itu jatuh. Rasionalitas , subjek otonom, antroposentrisme, positivisme, ilmu pengetahuan dan teknologi, kini bersiap-siap menjadi puing-puing fosil peradaban. Energi yang hilang. Roh telah menghilang. Bulan Purnama dari peradaban manusia modern telah menjulang di kelopak mata. Manusia modern telah meninggal.
Manusia harus mati? Beberapa dari mereka kemudian membuat dirinya tampil seperti dalam perilaku Cheerful Robot (robot yang ceria), orang yang mencoba melarikan diri dari kecemasan mental mereka dan kecemasan eksistensial dengan menerjunkan diri dalam hiburan, kesenangan sensual (terutama seksual), konsumsi produk-produk mewah, melakukan perjalanan ke tempat terdekat yang menyenangkan, dan sibuk dengan daya tarik permainan yang beragam. Semua itu dilakukan secara tidak sadar, dan sepenuhnya tunduk pada rekayasa psikologis kapitalis-imperialis “pedagang kesenangan”. Banyak lagi yang berperilaku seperti zombie, zombie yang menghantui di jalan-jalan mencari mangsa, tanpa emosi berdarah dingin, bertindak anarkis–destruktif, seperti yang ditampakkan oleh bebagai aksi terorisme seperti serangan militant ISIS di Syiria dan Serangan Koalisi Arab Saudi kepada sesama Muslim di negeri Yaman (2015) atau pembantaian rakyat Palestina oleh tentara Israel.
Lebih Jauh, terutama di kalangan terdidik, ditandai dengan kecemasan eksistensial mereka dengan meninggalkan eksistensi mereka sendiri, yaitu dengan mengambil sikap apatis, skeptis terhadap semua hal, nihilistik, dan jika perlu, bunuh diri dan bergelimang dengan kemabukan minuman keras, candu dan narkoba.[35]
Menurut Dr. Jalaluddin Rakhmat: “Ketika mereka menyingkirkan Tuhan Allah, mereka sebenarnya tidak hanya terasing dari Allah. Mereka terlemparkan ke dunia tanpa mengetahui ke mana mereka harus pergi. Mereka tersesat. “Sebagai hasil dari proyek kedaulatan manusia yang diresmikan oleh Renaissance dan Aufklarung (reformasi) yang telah gagal, karena manusia modern telah dibelenggu oleh mitos-mitos baru, berhala baru, ilusi baru, takhayul baru, dan para dewa baru! Orang-orang telah terbelenggu oleh petualangan liarnya sendiri, sampai hilang dan terlemparkan dari dirinya sendiri, terasing dari alam semesta dan dari Tuhan Yang Sejati.[36]
Krisis eksistensial ini berlandaskan pada aspek ontologis atau masalah metafisika yang telah ditutup korelasi dan implikasinya dengan mode epistemologis Barat modern mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern, jadi kita juga harus menjelaskan dan mendiskusikan masalah-masalah epistemologis ilmu modern.
Istilah epistemologi digunakan pertama kali pada tahun 1854 oleh JF Feriere. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mencoba untuk menjawab pertanyaan dasar seperti yang Kant Katakan: “Was kann ich wissen?” (“Apa yang bisa saya ketahui?”).[37] Karena jawabannya adalah tentang masalah pusat pemikiran manusia, sehingga epistemologi memiliki posisi sentral, sebagai mana Ayn Rand sebutkan, epistemologi adalah dasar dari ilmu-ilmu filosofis. Epistemologi merupakan salah satu bidang utama Filsafat. Hal ini berkaitan dengan sifat, sumber dan batas pengetahuan.[38]
Istilah Epistemologi ini berasal dari kata Yunani: ‘Episteme’ dan ‘Logos’. Episteme berarti ‘pengetahuan’ atau ‘kebenaran’ dan ‘logos‘ berarti ‘berpikir’, ‘kata’, atau ‘teori’. Runes mengatakan bahwa ‘epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan sumber, struktur, dan metode dan validitas pengetahuan.[39]
Pada abad ke-5 SM, para sofis Yunani mempertanyakan kemungkinan pengetahuan yang dapat diandalkan dan obyektif. Dengan demikian, seorang sofis terkemuka, Gorgias, berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar ada, bahwa jika sesuatu memang ada itu tidak bisa diketahui, dan bahwa jika pengetahuan itu mungkin, itu tidak bisa dikomunikasikan. Sofis lain yang menonjol, Protagoras, menyatakan bahwa tidak ada pendapat seseorang dapat dikatakan lebih benar dari yang lain, karena masing-masing adalah satu-satunya hakim dari pengalaman sendiri.[40]
Plato, mengikuti gurunya yang terkenal Socrates, mencoba untuk menjawab kaum Sofis dengan mendalilkan adanya dunia yang berubah dan tak terlihat bentuknya, atau ide-ide, tentang mana yang dimungkinkan untuk memiliki pengetahuan yang tepat dan pasti. Hal-hal yang orang melihat dan menyentuhnya, yang mereka pertahankan, adalah salinan sempurna dari bentuk-bentuk murni yang dipelajari dalam matematika dan filsafat. Dengan demikian hanya penalaran abstrak dari disiplin ilmu ini yang menghasilkan pengetahuan sejati, sedangkan ketergantungan pada persepsi rasa menghasilkan pendapat tidak jelas dan tidak konsisten. Mereka menyimpulkan bahwa kontemplasi filosofis dunia gaib adalah bentuk tujuan tertinggi dari kehidupan manusia.
Epistemologi juga dapat didefinisikan sebagai ‘The Theory of Knowledge’. Epistemologi dalam penjelasannya terdiri dari dua bagian: ‘epistemologi umum’ dan ‘epistemologi khusus’ atau ‘teori pengetahuan khusus’, terutama untuk pengetahuan ilmiah; sehingga dapat menyebutkan sebagai “Filsafat Ilmu”[41]. The Philosophy of Science (Pengetahuan) dan Epistemologi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Filsafat Ilmu didasarkan pada epistemologi, terutama pada masalah validitas ilmiah.[42] Validitas ilmiah terdiri dari tiga konsep teori kebenaran: korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Korespondensi membutuhkan keselarasan antara ide dan fakta eksternal (alam semesta), kebenarannya adalah empiris-deduktif; koherensi membutuhkan keharmonisan antar pernyataan logis, kebenaran ini bersifat formal-deduktif; sementara pragmatis memerlukan kriteria instrumental atau kebutuhan, kebenaran ini adalah bersifat fungsional.
Produk Korespondensi adalah ilmu-ilmu empiris seperti: fisika, kimia, biologi, sosiologi; produk koherensi adalah ilmu abstrak seperti: matematika dan logika, sedangkan produk-produk pragmatis diterapkan ilmu seperti: kedokteran. Jadi epistemologi merupakan dasar fundamental filsafat ilmu, terutama untuk membuat identifikasi untuk pengetahuan ilmiah, atau pengetahuan sehari-hari, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat dan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.[43]
- Implikasi Agama Kristen terhadap Ilmu Pengetahuan /Sains
Sebagian besar entri ini difokuskan pada implikasi dari ilmu agama. Namun, juga terjadi bahwa agama memiliki implikasi bagi ilmu pengetahuan. Telah dikatakan bahwa ajaran Kristen adalah kontributor penting untuk kebangkitan ilmu pengetahuan modern: kebebasan Allah mensyaratkan bahwa fitur dari dunia alam tidak bisa disimpulkan apriori dari prinsip-prinsip rasional, namun kebaikan dan kesetiaan Tuhan menyatakan bahwa dunia tidak akan begitu kacau untuk dapat dipahami. Keberadaan agama adalah pengingat yang berharga bahwa ada batas-batas luar yang tidak bisa dijelasan secara ilmiah, dan doktrin-doktrin yang membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar batas-batas itu. Era Newtonian melihat pemisahan filsafat alam (science) dari teologi natural, dan sejak saat itu telah menjadi anggapan metodologis dari ilmu yang harus memberikan penjelasan murni alami. Ilmu pengetahuan telah demikian menetapkan batas-batas kompetensi sendiri, tapi ini tidak berarti bahwa apa yang di luar kompetensinya karena itu tidak penting (atau tidak ada/eksis).
Kosmologi dan fisika menimbulkan pertanyaan yang mereka tidak bisa menjawabnya: Mengapa proses alam berperilaku seperti hukum? Apa yang menyebabkan Big Bang? Mengapa ada alam semesta sama sekali? Sementara teologi dan sains dapat berinteraksi dengan cara yang kecil dalam setiap domain yang tepat, itu adalah di sini bahwa penjelasan teologis datang dengan sendirinya.
- Hubungan Tak langsung antara Metafisika dan Epistemology
Jika konflik langsung antara teologi Kristen dan berbagai teori ilmu pengetahuan modern telah sering ditekankan, efek merusak pada teologi adalah konflik tak langsung antara agama dan ilmu pengetahuan yang telah terlalu sedikit menerima perhatian. Interaksi tak langsung ini dapat dianggap di bawah judul metafisika dan epistemologi.
Pandangan Mekanika Descartes tentang materi sebagai perpanjangan murni, yang disertai dengan pandangan pikiran sebagai ‘berpikir substansial ala Descartes’, yang telah meresmikan dualisme metafisik, yang telah menggantikan pandangan yang lebih tua dan lebih bernuansa pandangan antropologi Kristen. Sejauh dualisme ini telah terbukti secara filosofis tidak bisa dipertahankan, Kristen, dengan pandangannya tentang jiwa dan kehidupan setelah kematian, telah muncul dipertahankan juga.
Gambaran alam semesta sebagai Jarum jam seperti suatu sistem partikel yang bergerak tertutup, yang diatur ketat oleh hukum fisika (gambaran yang dicontohkan pada abad kesembilan belas oleh karya Laplace), menciptakan masalah dalam memandang tindakan ilahiyah Tuhan. Berbagai deisme populer menawarkan akun yang paling masuk akal: Tuhan adalah pencipta alam semesta, dan bertanggung jawab atas hukum alam, tetapi tidak memiliki interaksi yang berkelanjutan dengan dunia alam atau dengan sejarah manusia. Alternatif untuk theis (mereka yang masih percaya Tuhan) adalah perhitungan intervensi ajaib atau pertimbangan Allah sebagai penopang imanen proses alam (Miracles). Yang pertama tampaknya membuat Allah irasional (bertentangan dengan ketetapan Tuhan Allah sendiri) atau tidak kompeten (perlu menyesuaikan sistem). Pandangan yang terakhir membuatnya sulit untuk mempertahankan rasa lebih keterlibatan pribadi Tuhan Allah dalam kehidupan manusia daripada yang mungkin untuk Deists tersebut. Sebagian besar perbedaan antara kaum Kristen liberal dan konservatif dapat ditelusuri ke dalam teori tindakan Tuhan: kaum konservatif cenderung untuk mengambil Tuhan yang bisa intervensi, sebuah pandangan kaum liberal tentang Tuhan yang imanentis (menyelemuti).
Epistemologi. Teolog abad pertengahan memiliki dua set kategori epistemologis yang mereka miliki, yang berkaitan dengan scientia (pengetahuan demonstratif atau ilmiah) dan yang berkaitan dengan opinio (‘kemungkinan’ keyakinan, termasuk yang didasarkan pada otoritas). Jadi kesimpulan teologis tersebut yang tidak bisa disimpulkan dari prinsip-prinsip pertama yang bisa dengan senang hati didasarkan pada otoritas tak tercela, sangat bernuansa firman Allah. Namun, pada periode modern, berbagai ilmu pengetahuan yang dikontrak oleh bidang matematika dan logika formal; Hume dan Kant keduanya memberikan kritik kuat argumen deduktif bagi keberadaan Allah dan teologi alam pada umumnya. Selanjutnya, ketika kemungkinan pengetahuan mengambil rasa pengetahuan kontemporer berdasarkan bukti empiris yang berat, menarik menjadi tidak relevan bagi otoritas, dan yang paling dinilai mustahil untuk memberikan bukti empiris untuk klaim teologis. Jadi pertanyaan sentral bagi para teolog modern liberal adalah bagaimana, jika teologi adalah mungkin sama sekali.
Teologi liberal menyimpang dari rekening yang lebih tradisional sebagai hasil dari strategi untuk memenuhi masalah yang diangkat langsung atau tidak langsung oleh ilmu pengetahuan. Setelah Friedrich Schleiermacher, banyak teolog liberal telah memahami agama untuk membentuk bola sendiri dari pengalaman, tidak berhubungan dengan pengetahuan ilmiah. Doktrin teologis adalah ekspresi dari kesadaran religius, bukan rekening dari alam supranatural. Tuhan bekerja secara imanen, bukan oleh intervensi, baik dalam dunia alam atau sejarah manusia. Dengan demikian teologi liberal telah menghindari konflik langsung dengan ilmu pengetahuan modern, pada biaya (atau dengan konsekuensi menguntungkan) dari revisi sangat radikal tentang konsep agama dan teologi. Namun, Isu Ian Barbour dalam Sains dan Agama (1966) mempresentasikan gambaran ensiklopedis titik-titik di mana klaim ilmiah yang relevan dengan pemikiran keagamaan, dan dalam Mitos, Model, dan Paradigma (1974) ia berpendapat kesamaan epistemologis yang signifikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Sejak saat itu, semakin banyak ilmuwan ulama dari sayap liberal dari Kristen telah mulai memanggil divisi modern wilayah dipertanyakan.
- Pentingnya Merevisi Epistemologi tersebut
Mengapa epistemologi sangat penting bagi kehidupan manusia? Menurut Murthadha Muthahhari: “Dalam era baru-baru ini, banyak filsafat sosial, mazhab pemikiran (Mazhab), isme, ideolog , itu sudah hal penting, karena semua orang perlu memiliki suatu bentuk pemikiran tertentu bahwa kegiatan kehidupannya akan bergantung pada dan berdasarkan itu. Pada zaman kontemporer sering ada konflik yang terjadi di antara berbagai ideologi dan aliran pemikiran dari banyak kelompok, masyarakat, bangsa, negara.”[44]
Bahkan menurut Samuel J. Huntington, katanya ada ‘pertentangan peradaban’ di milenium ketiga di dunia. Saat ini, kita melihat Militer Amerika dan Inggris yang menaklukkan sumber-sumber alam yang besar seperti minyak dan gas dan untuk melindungi ambisi Zionisme-Israel telah membuat Irak dan Afghanistan serta Syiria diserang dan diinvasi.
Semuanya dilakukan oleh manusia didasarkan pada pemikiran dan ideologinya. Dan ‘ideologi’ tertentu tergantung pada ‘pandangan dunia’ tertentu.[45] Sementara ‘pandangan dunia’ didasarkan pada epistemologi dalam filsafatnya. Itulah sebabnya epistemologi sangat penting untuk kajian dan penelitian.
Menurut Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi dalam Buku Daras Filosofis (Philosophycal Instructions), Sebuah Pengantar Filsafat Islam Kontemporer [46]: “Ada serangkaian masalah mendasar yang dihadapi manusia sebagai makhluk sadar yang kegiatannya muncul dari kesadarannya; dan jika manusia menjadi lalai dalam usahanya untuk menemukan jawaban yang benar untuk masalah ini, ia akan menemukan diri fakta sebaliknya dari ia telah melintasi batas antara kemanusiaan dan kebinatangan. Tetap dalam keraguan – selain ketidakmampuan untuk memenuhi kebenaran nuraninya – tidak akan ada yang memungkinkan manusia untuk menghilangkan kecemasan tentang kemungkinan tanggung jawab-nya. Ia akan ditinggalkan merana atau, seperti yang kadang-kadang terjadi, berubah menjadi makhluk yang berbahaya. Karena solusi yang keliru dan menyimpang, seperti materialisme dan nihilisme, tidak bisa memberikan kenyamanan psikologis atau sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus mencari penyebab mendasar korupsi individual dan sosial dalam pandangan dan pikiran yang menyimpang. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk mencari jawaban atas masalah ini dengan tegas dan resolusi tak kunjung padam. Kita tidak mungkin berusaha sampai kita membangun cadangan dasar bagi kehidupan manusia kita sendiri dan dengan cara ini membantu orang lain juga, dan menangkap pengaruh dalam masyarakat pikiran yang tidak benar dan ajaran yang menyimpang, yang saat ini.
Sekarang bahwa perlunya sebuah upaya intelektual dan filosofis telah menjadi jelas dan tidak ada ruang yang telah ditinggalkan untuk keraguan atau ketidakpastian, tetap bagi kita untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan wajib ini dan tidak dapat dihindari atas mana kita telah selesaikan dengan menghadap ke pertanyaan berikut: Apakah akal manusia dapat memecahkan masalah ini?
Pertanyaan ini membentuk inti tentang masalah di mana epistemologi dipusatkan. Sampai kita memecahkan masalah cabang filsafat ini, kita tidak akan dapat sampai pada solusi terhadap masalah-masalah ontologi atau untuk cabang lain dari filsafat. Sampai nilai pengetahuan intelektual ditentukan, klaim yang disajikan sebagai solusi nyata untuk masalah tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak dapat diterima. Akan selalu tetap ada pertanyaan seperti tentang bagaimana kecerdasan dapat memberikan solusi yang tepat untuk masalah ini.
Banyak tokoh terkenal dari filsafat Barat, seperti Hume, Kant, August Comte, dan semua kaum positivis yang telah melakukan kesalahan. Dengan pandangan yang tidak benar, mereka telah tidak dapat menemukan dasar-dasar budaya masyarakat Barat, dan bahkan para sarjana dari ilmu-ilmu lainnya, mereka telah tersesatkan terutama kalangan psikolog behavioris. Sayangnya, pemukulan dan penghancuran gelombang ajaran tersebut juga telah menyebar ke bagian lain dari dunia, dan terpisah dari puncak yang tinggi dan tebing ketidakpastian dengan alasan yang tersisa dan menetapkan latar filsafat ilahi, semuanya kurang lebih telah datang di bawah pengaruh mereka.
Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengambil langkah pertama yang mantap dengan meletakkan dasar-dasar bagi rumah ide-ide filosofis kita dengan kokoh dan sampai tegap, dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, kita layak untuk menapak melalui tahap lainnya dan tiba di tujuan yang kita inginkan.
- Q. Epistemologi dan Bahasa
Pergeseran dari epistemologi abad pertengahan ke empirisme modern memerlukan revisi radikal dalam epistemologi agama. Berbagai strategi yang digunakan selama periode modern untuk menunjukkan teologi menjadi epistemologis yang terhormat. Namun, peningkatan prevalensi ateisme di kalangan ilmiah menunjukkan bahwa strategi ini belum berhasil. Pada titik dalam sejarah intelektual di mana beberapa akan menyebutnya sebagai akhir periode modern, teori pengetahuan telah cukup berubah bahwa pertanyaan tentang status epistemic teologi perlu diperiksa lagi. Perhatian kita di sini akan hanya dengan perubahan yang berkaitan langsung dengan ilmu pengetahuan.
Pernyataan teolog terkadang telah berhenti dengan alasan bahwa mereka menggambarkan keadaan urusan yang tak terbayangkan. Namun, teori fisika kuantum dan perkembangan ilmiah baru lainnya menggambarkan realitas fisik yang sama tak terbayangkan dan, sebagian orang akan mengatakan, panggilan ke dalam logika tradisional pertanyaan dua-nilai. Argumen ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pandangan pengetahuan lebih rendah hati daripada periode modern disebut untuk; realitas yang lebih kompleks dan misterius dari apa bahasa kita dan konsep memungkinkan kita untuk menangkap .
Hal ini sering dikatakan (terutama oleh para teolog) bahwa teologi berbeda secara radikal dari ilmu pengetahuan dalam hal ilmu pengetahuan yang obyektif sementara semua ilmu agama adalah pengetahuan diri –yang melibatkan, produk dari interaksi antara Tuhan dan subjek manusia. Cara lain di mana ilmu pengetahuan telah marah terhadap pandangan tua pengetahuan, dan mempersempit perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teologi, dalam pengakuan bahwa pengetahuan ilmiah itu sendiri adalah interaktif. Pengukuran interaksi dengan fenomena yang diukur, terutama pada tingkat sub-atomik.
Kebanyakan pemikir modern telah dinilai mustahil untuk memberikan dukungan empiris untuk teologi. Namun, dimulai dengan karya Ian Barbour (1974), telah ada penyelidikan dari cara di mana penalaran teologis menyerupai ilmu pengetahuan, termasuk rekening data yang sesuai untuk teologi. Perkembangan ini dimungkinkan oleh kemajuan dalam filsafat ilmu yang menunjukkan ilmu itu sendiri menjadi lebih rumit, dan lebih manusiawi, usaha yang diasumsikan daripada kaum positivis.
SARAN SEYYED HOSSEIN NASR:
“KEMBALI KE ILMU PENGETAHUAN SUCI TRADISIONAL DAN KEARIFAN ABADI (PERENNIALISM)” Untuk Menyelesaikan Krisis Multidimensi Manusia Modern
Dalam Bab ini, saya ingin mencoba untuk mengetahui beberapa penjelasan singkat yang menjadi saran atau resep dari cara pandang alternatif untuk mengatasi krisis multidimensi manusia modern yang telah disebabkan oleh pandangan dunia materialistik-sekuler dalam modernisme-materialisme, yaitu dengan menghidupkan kembali Traditional Sacred Science, atau kearifan tradisional yang sakral/suci yang merupakan Sophia Perennialism atau Kearifan dan Kebijaksanaan Abadi yang dibawa oleh para Nabi Allah dan orang-orang suci (para filosof-irfani dan para wali dan panditha-pujangga) sepanjang sejarah umat manusia.
- Filsafat dan Tradisi Kenabian
Menurut Seyyed Hossein Nasr ketika ia menulis dalam pengantarnya tentang hubungan antara Filsafat dan Kenabian: “Dalam iklim budaya saat ini di Barat serta bagian lain dari dunia yang dipengaruhi oleh modernisme dan postmodernisme, filsafat dan kenabian dipandang sebagai dua hal yang sangat berbeda, dan di mata banyak orang, pendekatannya dianggap bertentangan dengan pemahaman tentang sifat realitas.
Sepertinya tidak begitu, bagaimanapun, dalam kasus ini berbagai peradaban tradisional sebelum munculnya dunia modern. Juga tidak terjadi bahkan hari ini untuk sejauh bahwa pandangan dunia tradisional telah bertahan. Tak perlu dikatakan, dengan “kenabian/nubuwah” berarti kita meramalkan masa depan, tetapi kenabian membawa pesan dari perintah dari yang lebih tinggi atau lebih dalam realitas “kenabiannya” yang jelas sebagaimana dalam dunia Mesir kuno, Yunani klasik, dan Hindu, jika tidak berbicara tentang Monoteisme Abrahamik di mana peran kenabian jadi pusatnya.
Jika kita tidak membatasi pemahaman kita tentang kenabian kepada tampilan Ibrahimik itu, kita bisa melihat adanya kenabian dalam iklim keagamaan yang sangat beragam di hampir semua yang tidak hanya dari makna hukum, etika dan spiritual, tetapi juga dari satu sapiensial (kebijaksanaan-kearifan) bersangkutan dengan pengetahuan.
Kita melihat kenyataan ini dalam dunia resi di India dan Dukun agama (Shamans) dalam perdukunan yang beragam sebagaimana dalam iatromantis (Nabi-Penyembuh) di dalam agama Yunani dan Taoisme yang abadi, dalam penerangan Buddha dan kemudian di dalam master Zen Buddha yang memiliki pengalaman pencahayaan/pencerahan atau satori, serta para nabi dari agama-agama Iran seperti Zoroaster dan tentu saja para nabi Abrahamik. Akibatnya dalam semua dunia ini, kapanpun dan di manapun filsafat dalam arti universal telah berkembang, telah berhubungan dengan kenabian dalam berbagai cara.”[47]
Bahkan jika kita membatasi definisi Filsafat dengan aktivitas intelektual di Yunani kuno, yang pemahaman sejarah Barat modern anggap sebagai tempat asal spekulasi filosofis, hubungan antara filsafat dan kenabian dapat dilihat menjadi sangat dekat pada saat asal-usul paling awal filsafat Yunani. Kami juga menyadari bahwa kerenggangan hanya terjadi kemudian, tapi tidak dipisahkan satu sama lain pada awal tradisi filsafat Yunani. Mari kita hanya mempertimbangkan tiga tokoh yang paling penting pada asal spekulasi filsafat Yunani. Pythagoras, yang dikatakan telah menciptakan istilah Filsafat, itu tentu bukan filsuf biasa seperti Descartes atau Kant. Dia dikatakan telah memiliki kekuatan kenabian yang luar biasa dan dirinya seperti seorang nabi yang mendirikan sebuah komunitas religius baru.[48] Kaum Muslim sebenarnya menyebutnya monoteis (muwahhid) dan beberapa menyebutnya sebagai seorang nabi.
Orang yang sering disebut “Bapak logika Barat dan Filsafat“ adalah Parmenides, yang biasanya ditampilkan sebagai rasionalis, yang kebetulan telah menulis sebuah puisi berkualitas biasa-biasa saja. Tapi sebagaimana hasil studi baru-baru ini, Peter Kingsley secara brilian telah jelas menunjukkan, jauh dari menjadi rasionalis dalam pengertian modern, ia telah terbenam dalam dunia kenabian dalam arti agama Yunani dan merupakan seorang pelihat yang visioner.[49] Dalam puisinya, yang berisi pesan-pesan filosofis, Parmenides telah terpimpin ke dunia lain oleh Putri Matahari yang datang dari Istana Cahaya (Mansion of Light) yang terletak di tingkat eksistensi yang terjauh.[50] Jawaban untuk Pertanyaan bagaimana perjalanan ini berlangsung adalah “inkubasi”, “sebuah praktek spiritual yang terkenal dalam agama Yunani, di mana seseorang akan diam beristirahat sepenuhnya, sampai jiwanya akan dibawa ke tingkat realitas yang lebih tinggi, dan misteri keberadaan akan terungkap.
Dengan demikian Parmenides melakukan perjalanan batin sampai ia bertemu “para dewa/malaikat Tuhan” yang mengajarkan segala yang penting, yaitu, mengajarkan kepadanya apa yang dianggap menjadi puncak asal spekulasi filsafat Yunani. Sungguh luar biasa bahwa ketika “Dewa” menemui Parmenides, Dewa menyebut dia sebagai Kouros, artinya anak muda. Fakta ini luar biasa dan menarik karena dalam tradisi Islam istilah yang sangat tepat untuk ksatria spiritual (Futuwwah dalam bahasa Arab, dan jawãnmardi di bahasa Persia) dikaitkan dengan kata untuk pemuda (FATA / Jawan), dan ksatria spiritual ini dikatakan telah ada sebelum Islam dan telah diberi kehidupan baru dalam Islam di mana sumbernya dikaitkan dengan ‘Ali bin Abi Thalib [51], yang menerima Islamnya dari Nabi dan di mana hal itu diintegrasikan ke dalam tasawuf. Selain itu, Syaidina Ali telah dikaitkan oleh sumber-sumber Islam tradisional dengan pendirian metafisika Islam. [52]
Sosok lain Yunani yang diberi gelar kouros adalah Epimenides dari pulau Kreta yang juga berangkat ke dunia lain, di mana ia bertemu Keadilan dan yang membawa kembali hukum ke dunia ini. Seperti Parmenides, ia juga menulis puisi. Sekarang Epimenides dikenal sebagai nabi-penyembuh atau iatromantis yang kepadanya semuanya telah terungkap melalui inkubasi (Meditasi/uzlah) pada saat ia berbaring tak bergerak di sebuah gua selama bertahun-tahun.[53] Parmenides terkait dengan tradisi ini. Perjalanan Iatromantis ke dunia lain seperti dukun shamans dan tidak hanya mereka telah mampu menggambarkan perjalanannya, tetapi juga menggunakan bahasa sedemikian rupa untuk membuat perjalanan ini mungkin bagi orang yang lainnya untuk memahaminya. Mereka menggunakan mantra/doa-doa dalam puisi mereka yang kita juga lihat di karya-karya Parmenides. Mereka juga memperkenalkan cerita dan legenda Timur bahkan sejauh Tibet dan India, yang sangat menarik karena komunitas Parmenides di Anatolia di Italia selatan itu sendiri dipuji berasal dari Timur di mana dewa Apollo telah mengadakan penghargaan khusus sebagai model ilahi dari iatromantis yang ia terinspirasi sebagai nabi untuk menulis puisi hipnotis yang berisi pengetahuan tentang realitas.
Penggalian arkeologis dalam beberapa dekade terakhir di Velia di Italia selatan, yang merupakan rumah Parmenides, telah mengungkapkan prasasti yang menghubungkan secara langsung ke Apollo dan iatromantis. Sebagaimana Kingsley tulis, “Kami sedang dipertunjukkan bahwa Parmenides sebagai anak dewa Apollo, yang bersekutu dengan tokoh-tokoh puisi iatromantis misterius, yang ahli dalam penggunaan puisi incantory dan untuk membuat perjalanan ke dalam dunia.”[54] Jika kita ingat bahwa, bila berbicara secara esoteric: “Apollo bukanlah dewa Cahaya tetapi Cahaya Tuhan itu sendiri”[55], menjadi jelas seberapa dalam filsafat, sebagai mana diuraikan oleh Pastor Yunani Parmenides, terkait tentang saat asal usulnya dengan kenabian bahkan dipahami dalam terminology (Nabi) Ibrahimik telah menyediakan seseorang dengan tidak mengabaikan makna batin kenabian yang segera kita akan bahas. Sebuah tradisi semua para imam penyembuh telah diciptakan dalam pelayanan Apollo Oulios (Apollo Sang Penyembuh), dan dikatakan bahwa Parmenides adalah pendirinya. Sangat menarik untuk dicatat bahwa meskipun aspek-aspek ajaran Parmenides kemudian dilupakan di Barat, mereka diingat justru dalam kalangan filsafat Islam di mana sejarawan Muslim yang tergabung dalam filsafat tidak hanya Islam, tetapi juga filsafat Yunani yang erat dengan kenabian[56]. Seseorang harus ingat di sini terkenal diktum Arab: “yanba ‘al-Hikmah min Mishkat al-nubuwwah”, yaitu “filsafat/hikmah muncul dari ceruk kenabian”
Menarik untuk dicatat bahwa guru Parmenides telah dikatakan jelas miskin dan bahwa apa yang diajarkannya di atas segalanya kepada murid-muridnya adalah keheningan (nyepi) atau hesychia. Ini sangat penting bahwa figur yang kemudian seperti Plato, berusaha untuk memahami Parmenides yang menggunakan istilah hesychia lebih daripada kata lain untuk menggambarkan pemahaman berikutnya terhadap realitas. “Bagi Parmenides, melalui keheningan itu kita datang ke keheningan. Melalui keheningan kita mengerti keheningan. Melalui praktek keheningan kita datang untuk mengalami realitas yang ada di luar dunia indra ini.[57] “Sekali lagi itu adalah kepentingan yang luar biasa untuk mengingat penggunaan hesychia terkait dengan diwujudkan oleh ajaran esoterik dari Gereja Ortodoks, ajaran yang tujuannya adalah pencapaian kesucian dan gnosis/irfan.
Dalam puisi Parmenides dia diberitahu secara eksplisit oleh para dewa (Tuhan YME) untuk mengambil apa yang dia telah pelajari, untuk diajarkan kembali ke dunia dan menjadi utusan-Nya. Kingsley membuat jelas apa artinya istilah utusan dalam konteks ini. “Ada satu nama tertentu yang menggambarkan dengan baik jenis utusan Parmenides yang menemukan dirinya menjadi: nabi (prophets). Arti sebenarnya dari kata ‘nabi’ tidak ada hubungannya dengan kemampuan melihat (peramal) ke masa depan. Istilah itu hanya berarti seseorang yang tugasnya adalah untuk berbicara atas nama suatu “kekuatan besar, seseorang atau sesuatu yang lain.”[58] “Fungsi kenabian” Parmenides ini termasuk tidak hanya menjadi seorang filsuf, penyair, dan penyembuh tetapi juga, seperti Epimenides, seorang pembawa hukum.
Hubungan antara Parmenides dan kenabian, bagaimanapun, tidak terutama hanya dalam hubungan sosial, hukum, dan eksoteris, tapi lebih dalam, yang memulai dan esoteris. Puisinya, jika dipahami dengan benar, itu sendiri merupakan inisiasi ke dunia lain, dan “semua tanda-tanda bahwa hanya orang bodoh akan memilih untuk melewatkan, adalah bahwa ini adalah teks untuk inisiasi (bai’at).”[59] Dalam hal ini ia bergabung dengan Pythagoras dan Empedocles yang filsafatnya juga ditujukan hanya untuk mereka yang mampu menerima pesannya dan berbicara dengan benar secara dimensi esoteris (batiniah) ketimbang dimensi eksoteris (syariah-lahiriyah) dari agama Yunani, yang membutuhkan inisiasi untuk pemahaman penuh. Sungguh luar biasa lagi dalam pertanyaan ini, bagaimana filsafat Islam menyerupai begitu banyak visi dan pemikiran filosofis figur tokoh-tokoh pra-Socrates seperti Pythagoras, Parmenides, dan Empedocles, yang semuanya sangat dihormati oleh para filosof Islam, terutama dari mazhab Isyraqi (illuminationist/Pencerahan bathin).
Menjupai sosok misterius Empedocles, sekali lagi kita melihat seorang filsuf yang juga seorang penyair serta penyembuh dan yang dianggap oleh banyak orang sebagai juga seorang nabi. “Selain sebagai seorang dukun (Sorcerer), dan penyair, ia juga seorang nabi dan penyembuh. Salah satu nabi-penyembuh yang saya telah bicarakan tentangnya.”[60] Empedocles juga menulis tentang kosmologi dan ilmu alam seperti fisika, tetapi bahkan dalam hal ini domain karya-karya ini tidak ditulisnya hanya untuk sekedar memberikan fakta-fakta, tetapi “untuk menyelamatkan jiwa manusia”[61], sangat mirip dengan kosmologi sejumlah filsuf Islam, termasuk Suhrawardi dan bahkan Ibnu Sina dalam bukunya Visionary resital.[62] Apa yang penting adalah menyadari sebagian besar dari semua bahwa Empedocles melihat dirinya sebagai seorang nabi dan puisinya sebagai karya esoteris (kebatinan/ruhaniyah).
Menarik untuk menyebutkan bahwa ketiga tokoh tersebut yang datang pada asal-usul tradisi filsafat Yunani juga adalah penyair/sastrawan. Ini merupakan karakteristik dari banyak filosof yang berkembang selama berabad-abad di bawah sinaran matahari kenabian. Kita hanya butuh untuk ingat bahwa para bijak Hindu kuno juga penyair/sastrawan dan juga para bapak pemikiran filsafat Hindu dalam arti tradisional atau banyak orang bijak Cina yang menyatakan ekspresi dirinya dalam bentuk puisi. Dalam dunia monoteisme Nabi Ibrahim, hal ini harus terlihat di antara sejumlah filsuf Yahudi dan Kristen, tetapi lagi-lagi ini dapat ditemukan terutama di kalangan filsuf Islam seperti Ibnu Sina, Nasir-I Khusraw, Umar Khayyam, dan Suhrawardi sampai ke Afdal al-Din Kasyani, Mir Damad, dan Mulla Sadra sampai ke Haji Mulla Hadi Sabziwari, yang hidup pada abad ketiga belas masehi.[63]
Dalam dunia di mana kita hidup saat ini, filsafat telah direduksi menjadi hanya sekedar rasionalisme atau terlebih menjadi irrationalism dan di mana tidak hanya esoterisme, tetapi bahkan agama itu sendiri itu ditolak atau dipinggirkan, interpretasi yang diberikan tentang para pendiri Filsafat Barat tersebut di atas akan ditolak dalam banyak kalangan, dan hubungan antara filsafat dan kenabian pada umumnya dan filsafat, puisi dan esoterisme pada khususnya akan dihentikan atau dianggap sebagai konsekuensi yang kecil saja.
Tapi anehnya bagi pembaca Barat, hubungan antara filsafat, kenabian, dan esoterisme, justru ditegaskan oleh sejumlah sarjana Barat kontemporer, yang ditemukan menjadi pusat tradisi filsafat Islam, yang dengannya sebagian besar dari buku-buku SH Nasr ini akan peduli. Kami telah menyertakan pembahasan tokoh-tokoh Yunani di sini untuk menunjukkan bahwa hubungan antara filsafat dan kenabian, meskipun terputus ke tingkat yang semakin besar di Barat dari akhir Abad Pertengahan dan seterusnya, adalah sangat penting, tidak hanya untuk pemahaman Filsafat Islam, tetapi juga untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul filsafat Barat itu sendiri, asal-usul bahwa filsafat Barat telah berbagi saham dengan filsafat Islam, tetapi dapat dipahami dengan cara yang sangat berbeda oleh dua arus pemikiran filsafat Barat yang datang kemudian, yang semakin besar menjauhkan diri dari filsafat perennial dan dari teologi Kristen.
Tentu saja ada mode-mode dan derajat kenabian yang berbeda, sebuah fakta bahwa jika seseorang menyadarinya, ketika mempelajari berbagai tradisi agama dan bahkan jika seseorang membatasi diri untuk tradisi tunggal, seperti yang kita lihat dalam Yudaisme dan Islam di mana peran kenabian Yunus atau Daniel tidak sama seperti yang dilakukan Musa atau Nabi Islam (Muhammad SAW). Namun ada unsur-unsur umum dalam berbagai pemahaman kenabian sejauh tantangan yang dimiliki filsafat yang bersangkutan. Pertama-tama kenabian menyiratkan tingkatan realitas, apakah ini dipertimbangkan sebagai hirarki objektif atau subyektif. Jika hanya menjadi ada satu tingkat realitas obyektif yang terkait dengan dunia jasmani dan subyektif dengan kesadaran biasa, kami menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk kesadaran yang sah dan diterima, kenabian sebagai fungsi membawa pesan dari dunia lain atau tingkat Kesadaran lain, akan menjadi tidak berarti karena akan ada dunia lain atau tingkat kesadaran, dan suatu klaim bahwa keberadaan mereka akan ditolak dan dianggap sebagai halusinasi subyektif. Seperti pada kenyataannya dengan kasus saintisme modern dan pandangan umum desakralisasi dunia, yang keduanya mengecualikan perspektif Realitas transenden mereka dan tingkat yang lebih tinggi dari keberadaan (eksistensi) vis-à-vis dunia ini serta Diri imanen dan tingkat kesadaran yang lebih dalam dari yang biasa-biasa saja.
Tetapi dalam dunia di mana semua realitas kenabian telah dijalankan dengan satu atau lain cara, penerimaan tingkat yang lebih tinggi dari realitas dan/atau level kesadaran yang lebih dalam yang telah diambil untuk diberikan sebagai cara yang benar untuk memahami sifat dari realitas total di mana manusia hidup.[64] Diformulasikan dengan cara ini, pernyataan ini termasuk monoteisme Ibrahim bersama dengan agama-agama India, Taoisme dan Konghucu serta agama kuno Mediterania dan Iran, dan Shamanisme bersama dengan Buddhisme, yang menekankan tingkat kesadaran daripada derajat eksistensi objektif.
Di dalam dunia ini, di mana semua kenabian merupakan realitas utama, yang menciptakan konsekuensi, yang dengannya filsafat harus berurusan. Kenabian memberikan ajaran moral dan hukum, etika, politik, dan hukum bagi masyarakat, sehingga filsafat harus mempertimbangkannya. Selain itu, klaim kenabian memberikan pengetahuan tentang hakikat realitas, termasuk pengetahuan tentang Asal atau Sumber dari segala sesuatu, dari penciptaan kosmos dan strukturnya atau kosmogoni dan kosmologi, sifat jiwa manusia, yang akan mencakup apa yang tepat harus disebut “Pneumatology” dan psikologi tradisional dan akhir segala hal, hal akhirat atau eskatologi. Buah dari kenabian adalah pengetahuan tentang semua aspek utama dari realitas yang dialami atau spekulasi tentang manusia, termasuk sifat ruang dan waktu, bentuk dan substansi, hukum sebab-akibat/kausalitas, takdir, dan berbagai masalah lain yang dengannya filsafat secara umum juga bersangkutan.
Selain itu, bentuk-bentuk tertentu dari kenabian harus dilakukan dengan pengetahuan batin, dengan esoteris dan mistiskal, dengan visi tingkat lain dari realitas yang tidak dimaksudkan untuk masyarakat umum yang luas. Kita telah melihat hubungan asal-usul filsafat Yunani dengan dimensi esoteris agama Yunani, dan kita dapat menemukan banyak contoh lain dalam tradisi-tradisi lain, termasuk tradisi agama Buddha dan khususnya Islam, di mana filsafat menjadi terkait lebih dalam di abad kemudian dengan dimensi batin wahyu Quran. Hubungan antara filsafat dan esoterisme, yang merupakan dimensi kenabian sebagaimana didefinisikan di sini dalam arti universal, juga memiliki sejarah panjang di Barat yang berlangsung sampai gerakan Romantic Jerman.
Dari abad ketujuh belas dan seterusnya, filsafat Barat merasa dipaksa untuk berfilsafat tentang gambaran dunia yang dilukis oleh ilmu pengetahuan modern dan menjadi lebih merupakan hamba ilmu pengetahuan modern terutama dengan pemikiran Emanuel Kant, dan mencapai banyak puncaknya pada abad kedua puluh dengan filsafat Anglo-Saxon, yang lebih sedikit terikat daripada jejak logika pada pandangan dunia ilmiah.
Dalam cara yang serupa, di berbagai dunia tradisional di mana realitas kenabian dan wahyu adalah menjadi pusatnya, apakah perwujudan dari kenabian ini telah menjadi kitab suci atau bentuk lain dari pesan yang dibawa dari surga atau utusan Tuhan sebagai mana dalam kasus para avatar Hindu, Buddha, atau Kristus, filsafat tidak punya pilihan selain untuk mengambil realitas sentral ini menjadi pertimbangannya. Filsafat harus berfilsafat tentang sesuatu, dan di dunia tradisional tersebut bahwa sesuatu selalu mencakup realitas yang terungkap melalui kenabian, yang berkisar dalam bentuk dari iluminasi dari rhesi Hindu dan Buddha, seperti Tuhan Allah berbicara kepada Nabi Musa di Gunung Sinai atau malaikat Jibril yang mewahyukankan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
Dalam dunia tradisional pertanyaan tersebut, filsafat belum menjadi sesederhana teologi, karena beberapa orang telah berpendapat begitu, kecuali satu batasan definisi positivistik filsafat modern, jika dalam kenyataannya tidak ada filsafat non-Barat atau dalam hal ini filsafat Barat abad pertengahan, yang tidak membicarakannya.
Tetapi jika kita menerima definisi filsafat yang diberikan oleh orang yang dikatakan pertama kali telah menggunakan istilah itu yaitu Pythagoras – dan melihatnya sebagai cinta (philo) kepada Shopia (kebenaran), atau jika kita menerima menurut definisi Plato filsafat sebagai “praktek persiapan kematian” yang menurut filosofinya meliputi aktivitas intelektual dan latihan rohani, maka pasti ada banyak mazhab filsafat di berbagai dunia tradisional, beberapa yang masih ada sampai sekarang, hanya dalam bentuk lisan sebagai salah satunya yaitu tradisi pribumi Australia (aborigin) dan penduduk asli Amerika (indian),[65] sementara yang lain telah menghasilkan volume tulisan-tulisan filosofis selama berabad-abad.
Bahkan jika ada orang yang memutuskan untuk hanya berurusan dengan karya-karya filsafat tertulis, orang bisa menulis volume tentang subjek filsafat di tanah kenabian yang berurusan dengan Tao dan tradisi filsafat Konfusianisme Cina, dengan orang-orang Tibet dan Buddhisme Mahayana termasuk mazhab-mazhab Jepang, semua yang memiliki karakteristik khusus mereka sendiri, dan tentu saja dengan tradisi filsafat yang sangat kaya dari Hindu India.
Kita juga bisa beralih ke dunia tradisi agama Ibrahimik dan menulis tentang mazhab filsafat Yahudi, Kristen dan Islam dari perspektif kegiatan filosofis dalam dunia yang didominasi oleh kenabian. Juga tak satu pun menemukan perawatan semacam ini benar-benar lengkap paralel untuk tiga adik tradisi-agama Ibrahimik, meskipun terkenal kesamaan, karena sementara konsepsi kenabian Yahudi dan Islam dan kitab sucinya yang berdekatan, namun bahwa Kekristenan agak berbeda, di mana pendiri agamanya (Yesus) dipandang sebagai inkarnasi dari Keilahian, berbeda dalam banyak hal baik dari materi Yahudi dan pandangan Islam. Perbedaan ini sangat penting secara filosofis seperti yang kita lihat dalam perlakuan filosofis inkarnasi dalam filsafat Kristen dan “filsafat kenabian” dalam konteks Islamnya. [66]
Untuk memberikan argumen mengapa kita perlu untuk mencari saran atau resep alternatif untuk memecahkan masalah dan krisis modernisme, saya menemukan beberapa artikel yang baik dan jelas dari situs The Center of Science Sacred (http://www.centerfor sacredsciences.org) bellow:
- Mengapa Kita Perlu Pandangan Dunia yang Baru?
Ketika astronom Polandia Nicholas Copernicus, hampir lima ratus tahun yang lalu, mengusulkan bahwa matahari-lah, dan bukan bumi, yang menjadi pusat alam (tata surya), ia memulai sebuah revolusi ilmiah yang telah mengubah kehidupan manusia dengan cara yang dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk satu hal, ilmu pengetahuan dan teknologi (sains-tek) baru yang dilahirkan ini mungkin telah membuat perbaikan yang cepat dalam bidang-bidang seperti pertanian, manufaktur, obat-obatan, perjalanan, komunikasi dan pendidikan, yang kesemuanya telah memperbaiki standar hidup untuk sebagian besar populasi dunia. Namun, karena seperti yang mungkin menyambut perkembangan ini, hal ini tidak datang tanpa harga. Seiring dengan manfaatnya yang tidak dapat dipungkiri, sains-teknologi ini telah juga membawa di belakangnya sejumlah masalah yang tidak terduga. Kelebihan dan kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, degradasi ekologi (menurunnya kualitas lungkungan), pemanasan global, dan penemuan senjata pemusnah massal, semuanya telah mengancam kita dengan bencana yang jauh bisa lebih besar daripada apa pun akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang telah begitu jauh terjadi. [67]
Bagaimanapun yang lebih mengkhawatirkan, adalah kenyataan bahwa meskipun solusi teknologi bagi banyak masalah-masalah ini sudah diketahui, tampaknya kita semakin tidak mampu mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Kelumpuhan psiko-spiritual ini menjadi poin kolektif kami, yang lebih halus namun kita harus tidak/kurang serius membayarnya dengan harga mahal, karena sains-teknologi dengan tidak perlu diragukan lagi, telah merusak keimanan seperti – hilangnya bantalan moral dan spiritual.
Sebenarnya, kerugian ini tidak datang begitu banyak dari sains per-se (yang, tegasnya, hanyalah merupakan metode), tapi dari kita telah menerima pandangan dunia materialisme-nya yang menjadi basis sains-teknologi. Masalah pada pandangan dunia materialisme ini adalah bahwa banyak penjelasan tentang bagaimana kosmos bekerja, bertentangan penjelasannya dengan yang pandangan-dunia agamis yang lebih tua, yang telah memberikan panduan moral dan spiritual bagi sebagian besar sejarah umat manusia. Apalagi, mengingat keberhasilan yang tampak dari penjelasan materialis itu telah menjadi lebih mengeras dan sulit bagi orang yang terdidik untuk menganggap serius setiap penjelasan keagamaan. Apakah para petani modern, misalnya, akan mengandalkan doa-doa dan mantera, daripada pupuk untuk meningkatkan hasil panen? Apakah ibu-ibu modern akan memilih ritual perdukunan tinimbang obat antibiotik untuk mengobati infeksi anaknya?
Perbedaan antara penjelasan yang ditemukan di dalam pandangan-dunia materialis ini dengan pandangan-dunia agamis mungkin tidak dengan sendirinya menjadi masalah, jika bukan karena fakta bahwa fungsi penting dari setiap pandangan dunia adalah untuk memberi pengikutnya pertimbangan internal yang koheren dan konsisten tentang realitas. Akibatnya, bila kita mempertanyakan satu aspek dari pandangan dunia tentu menimbulkan pertanyaan terhadap semua aspek lainnya juga. Dalam merusak penjelasan agama tentang cara kerja kosmos (alam Semesta), pandangan dunia materialisme juga menggerogoti nilai-nilai moral dan spiritual agama-agama tradisional yang telah mapan. Dan, yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, karena pandangan dunia materialisme tidak mengakui dimensi spiritual dari kosmos, maka pada dasarnya tidak mampu memasok nilai-nilai spiritual dan moral itu sendiri.
Akibatnya, hari ini banyak orang (terutama di Barat) yang telah meninggalkan pandangan-dunia agama mereka sama sekali dan hidup dalam kekosongan moral dan spiritual. Orang lain telah menyerah kepada sejenis ‘skizofrenia filosofis’ di mana mereka bergantung pada pandangan dunia materialisme untuk pelaksanaan urusan praktis mereka, sementara mencari pandangan dunia agama yang bertentangan untuk membimbing kehidupan rohani mereka.
Pertanyaannya, kemudian, secara alami muncul: “Apakah mungkin untuk menciptakan pandangan dunia baru yang dapat menjelaskan dengan baik keberhasilan ilmu pengetahuan modern sambil mempertahankan nilai-nilai fundamental moral dan spiritual? Sebelum menjawab pertanyaan penting ini, bagaimanapun, kita pertama harus jelas mengenai apa pengertian pandangan dunia itu.
- Definisi Pandangan Dunia (Worldview)
Secara ringkas, pandangan dunia adalah sebuah konsep yang koheren, yang disepakati tentang peta kosmos. Secara lebih spesifik, pandangan dunia dapat memasok suatu komunitas tertentu dengan:
- asumsi dasar tentang apa yang nyata dan apa yang tidak nyata, dan kriteria untuk membedakan apa yang benar dari apa yang salah;
- terminologi untuk membahas asumsi-asumsi dasar dan kriteria tersebut, dan untuk menarik kesimpulan logis darinya;
- nilai-nilai yang memberikan bimbingan moral dan spiritual bagi tindakan-tindakan kita;
- contoh-contoh historis yang berfungsi sebagai model peran tentang bagaimana asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai bisa berhasil digunakan dalam rangka untuk memberikan makna hidup kita dan koherensinya.
Apakah kita menyadarinya atau tidak akan hal itu, semua kita memiliki pandangan dunia. Sebagian besar dari kita menerima pandangan dunia kita dari masyarakat di mana kita dilahirkan dan tetap berkomitmen untuk itu sepanjang hidup kita. Beberapa dari kita, bagaimanapun juga, menghadapi situasi atau memiliki pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan pandangan dunia yang kita warisi tersebut. Ini biasanya berupa endapan krisis kepercayaan yang dapat diselesaikan dalam satu dari dua cara: entah kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan dunia yang kita warisi, yang menunjukkan bagaimana dapat menjelaskan situasi anomali (keanehan) atau pengalaman, atau kita mengubahnya dengan pandangan dunia lain, yang dianut oleh sebuah komunitas yang berbeda, yang telah memiliki penjelasan built-in untuk anomali yang kita temui.
Kadang-kadang seluruh anggota komunitas akan menghadapi anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh pandangan dunia yang ada. Ketika ini terjadi, masyarakat secara keseluruhan memasuki masa krisis. Orang-orang di masyarakat mulai kehilangan indera arah. Mereka tidak lagi merasa jelas tentang apa yang mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukannya. Pada titik ini, anggota kaum intelektual masyarakat mulai mencari pandangan dunia baru. Jika mereka gagal untuk menemukannya, masyarakat akhirnya akan hanyut ke sejenis disintegrasi (perpecahan) yang digambarkan oleh Yeats sebagai: “Hal-hal yang berantakan, pusat tidak bisa menahannya; anarki dilepaskan atas dunia.” Konflik antara pandangan dunia ilmu pengetahuan materialisme dan pandangan-dunia agama tradisional telah membawa umat manusia hanya kepada krisis seperti itu, dan krisis ini hanya bisa diselesaikan melalui penciptaan pandangan dunia baru.
Kami, penulis buku ini dan beberapa sarjana yang ada di Center for Sacred Sciences, percaya adalah sangat mungkin untuk menciptakan pandangan dunia baru di mana kebenaran sains dan agama dipandang sebagai cara yang cocok (kompatibel) dalam melihat Realitas dasar yang sama. Ada beberapa alasan mengapa kami percaya hal ini mungkin:
Beberapa ilmuwan di Center for Sacred Sciences (Pusat Ilmu Suci), sama seperti kami, percaya adalah mungkin untuk menciptakan sebuah pandangan dunia baru di mana kebenaran sains dan agama dipandang sebagai cara yang kompatibel (cocok satu sama lain) dalam melihat Realitas dasar yang sama.[68] Ada beberapa alasan mengapa kami percaya hal ini mungkin:
- 1. Fisika Modern Bertentangan Materialisme
Alasan pertama adalah bahwa munculnya fisika kuantum pada kuartal pertama abad kedua puluh telah memberikan gambaran bahwa pandangan dunia materialisme ilmiah tidak dapat lagi dipertahankan. Asumsi dasar dari pandangan dunia materialisme adalah bahwa benda-benda fisik ada secara independen dari kesadaran, yang dianggap sebagai epiphenomenon hanya proses fisik yang terjadi di otak. Menurut fisika kuantum, bagaimanapun, ini tidak benar. Benda-benda tidak ada dalam cara yang pasti terlepas dari kesadaran subjek yang mengamati mereka. Kedua aspek realitas kesadaran dan kesadaran-benda tidak dapat dipisahkan.[69] Dengan demikian, bukti ilmu itu sendiri bertentangan dengan perhitungan murni materialistik alam semesta. Akibatnya, ilmu pengetahuan telah harus meninggalkan pandangan dunia materialism-nya dan saat ini sedang mencari beberapa penjelasan lain untuk hasil temuannya.
Ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan saat ini telah memberikan bukti untuk pandangan dunia spiritual, sebagaimana beberapa pemikir modern secara prematur menyimpulkannya. Bagaimanapun ini berarti bahwa materialisme adalah tidak pernah dapat lagi memberikan dasar yang kuat untuk ilmu pengetahuan. Dengan demikian, suatu hambatan yang besar untuk setiap pemulihan hubungan antara sains dan agama telah efektif telah dihapus.
- 2. Kesepakatan Perjanjian antara Mistikus
Alasan kedua kita percaya adalah mungkin untuk menciptakan pandangan dunia yang komprehensif berasal dari perkembangan modern dalam pemahaman kita tentang perbedaan antara tradisi-tradisi keagamaan. Seringkali konsep agama sendiri telah bertentangan dengan satu sama lain, masing-masing mengklaim bahwa pandangan dunia tertentu sendiri adalah satu-satunya yang sah. Tapi situasi ini, juga telah berubah. Selama beberapa dekade terakhir para ulama-ilmuwan dan para penerjemah telah menyediakan sebuah badan pengetahuan yang semakin besar dari teks asli kitab suci yang diambil dari semua tradisi agama besar di dunia. Dari perspektif global yang diberikan oleh studi perbandingan teks-teks ini, kita sekarang dapat mulai melihat bahwa, sementara para filsuf dan teolog dari berbagai tradisi ini masih memiliki banyak perbedaan pendapat tentang Nature of Ultimate Reality, hal ini tidak terjadi dengan mistik (dunia kebatinan/ruhaniyah/spiritualitas). Sebaliknya, kesaksian mereka menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat tinggi. Antara lain, mereka semua bersikeras bahwa Nature of Ultimate Reality bisa langsung direalisasikan meskipun Gnosis (Ma’rifat/Pencerahan) yang melampaui segala pandangan dunia, bahkan dari orang-orang tradisi mereka sendiri. Jika kita mengambil Realisasi mistis ini atau Gnosis untuk membentuk wawasan inti yang memunculkan berbagai tradisi agama, maka semua yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama adalah untuk membuat sambungan antara sains dan mistisisme (Irfan).
- E. Koneksi antara Sains dan Mistisisme (Irfan)
Pada kenyataannya, ada dua koneksi antara sains dan mistisisme. Yang pertama, berkaitan dengan kesamaan dalam metodologi mereka. Sama seperti para para ilmuwan mempertahankan bahwa kebenaran teori mereka dapat diverifikasi (diuji kebenarannya) oleh siapa saja yang melakukan pengamatan yang tepat dan eksperimen, para mistikus juga mempertahankan bahwa Kebenaran ajaran mereka dapat diverifikasi oleh siapa saja yang bersedia untuk melakukan disiplin dan praktek spiritual yang sesuai. Dengan demikian, perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama tidak (karena banyak orang mengira) bahwa salah satu bergantung pada penyelidikan empiris dan yang lainnya pada keyakinan yang membuta. Sebaliknya, perbedaan terletak pada domain yang akan diselidiki dan jenis kebenaran yang akan diverifikasi.
![]() Picture 1: Diagram hubungan antara Science and Mysticism
Picture 1: Diagram hubungan antara Science and Mysticism
Sementara para ilmuwan memfokuskan investigasi mereka pada perilaku objek dalam kesadaran, para mistikus berkonsentrasi pada kesadaran subjek – yang ‘diri’ atau ‘aku’ kepada siapa objek itu tampil. Dan sementara para ilmuwan berusaha untuk mengembangkan teori-teori yang lebih halus dan komprehensif tentang bagaimana realitas bekerja, para mistikus berusaha untuk Mewujudkan Kebenaran tentang alam fundamental yang terletak di luar jangkauan teori apapun. Perlu dicatat bahwa, jauh dari menempatkan sains dan mistisisme dalam konflik, perbedaan-perbedaan antara domain masing-masing dan fungsi sebenarnya apa yang membuat kompatibilitasnya mungkin.
Tidak hanya ilmu pengetahuan dan mistisisme memiliki metodologi yang paralel/sejajar, tetapi mistik benar-benar dapat memberikan pemahaman spiritual/filosofis yang koheren tentang bagaimana ilmu pengetahuan bekerja. Salah satu ajaran penting yang disepakati oleh para mistikus dari semua tradisi menyangkut hubungan antara kesadaran dan objek-nya hubungan yang sangat terletak di jantung dari krisis filosofis dalam fisika modern (seperti yang telah kita lihat). Apa yang para mistikus klaim bahwa perbedaan antara subjek pada kesadaran dan benda-benda yang timbul dalam kesadaran adalah imajiner. Pada kenyataannya, Kesadaran (tentang Allah, Brahman, Buddha-Pikiran, atau Tao) merupakan lahan dasar yang tak berbentuk (Formless Ground) dari mana semua bentuk timbul sebagai tak terpisahkan sebagai gelombang yang timbul dari lautan yang tunggal. Dengan demikian, ajaran-ajaran mistisisme mengambil tepat di mana teori-teori ilmiah modern telah meninggalkannya. Dan itu ada di sini, pada saat ini antara dua domain mereka, bahwa kontinuitas sebenarnya antara ilmu pengetahuan dan mistisisme mulai menampakkan dirinya. (lihat dan renungkan kembali diagram hubungan sains dan mistisisme di atas).
Setelah ini dipahami, masalah membangun pandangan dunia baru pada dasarnya bermuara untuk formulasi pertanyaan: “Dapatkah kontinuitas (keberlangsungan) antara ajaran-ajaran mistisisme dan teori-teori ilmiah dinyatakan dalam bahasa ketat tunggal yang dipahami oleh keduanya?
Hal ini membawa pada alasan terakhir untuk kita percaya bahwa pandangan dunia baru adalah sangat mungkin. Sudah ada bahasa yang dapat mengekspresikan kesinambungan antara sains dan mistisisme. Bahkan, bahasa ini pada awalnya dikembangkan untuk tujuan ini oleh keturunan mistikus Yunani kuno yang dimulai dengan Pythagoras dan Plato. Dan, meskipun sebagian besar telah kehilangan pandangan tentang asal-usul mistik sendiri, hari ini diakui sebagai bahasa universal ilmu pengetahuan modern. Kami, tentu saja, mengacu pada bahasa matematika.
Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan sains mengagumkan justru berasal dari kemampuannya untuk hubungan menyatakan hubungan matematis antara fenomena fisik, pertanyaan yang dimiliki ilmuwan yang paling bingung sendiri adalah: Mengapa karya ini, mengapa alam semesta ini obyektif begitu sempurna mematuhi persamaan matematik yang berasal dari pikiran subjektif ? Hebatnya, jika klaim mistik adalah benar – bahwa perbedaan antara kesadaran dan benda-benda adalah imajiner – maka pertanyaan yang mendalam ini memiliki jawaban yang radikal meskipun sederhana: Matematika tidak menggambarkan dunia objek yang ada secara independen; namun menciptakan benda-benda ini dengan tindakan imajinasi dalam Kesadaran itu.
Bahkan, proses ini telah diberikan formulasi matematis yang eksplisit. Dalam karya yang berpengaruh: Law of Forms (1969), matematikawan G. Spencer-Brown menunjukkan bagaimana, mulai dari kekosongan yang tak berbentuk, tindakan sederhana membuat perbedaan secara alami dapat menimbulkan hukum yang paling primitif yang mendasari logika dan aritmatika. Sekarang, jika kita mengambil kekosongan (suwung) ini adalah bahwa Kesadaran tak berbentuk yang disaksikan oleh kaum mistik, bahasa pembedaan ini dapat memberikan ekspresi matematika yang tepat untuk beberapa ajaran mistik tertinggi (misalnya, seperti yang digambarkan di Thomas McFarlane “The Play of Distinction“). Terlebih lagi, pekerjaan berikutnya oleh Jack Engstrom, Louis Kauffman, Jeffrey James, dan Thomas McFarlane membawa kita percaya bahwa untuk seluruh tubuh matematika yang dipekerjakan oleh ilmu pengetahuan modern dapat ditelusuri kembali dari undang-undang tentang bentuk (laws of forms) di garis yang tak terputus antara bentuk yang sama dan Void (kekosongan) yang dari mereka muncul.
Jika ini terbukti menjadi kasus, maka kedua temuan ilmu pengetahuan modern serta ajaran-ajaran mistik telah akan dibawa ke dalam lingkup bahasa yang umum untuk semacam pandangan dunia baru yang hanya kita miliki dalam pikiran. Dalam pandangan dunia seperti kebenaran ilmu pengetahuan akan terlihat mengalir mulus dari dalam Realitas Kebenaran yang lebih disadari oleh para mistikus dari semua tradisi keagamaan, sedangkan tradisi-tradisi itu sendiri akan dipandang sebagai berbagai cabang dari Tradisi Besar yang tunggal yang telah menghiasi kemanusiaan dengan moral yang sangat diperlukan dan bimbingan rohani sejak fajar kerberadaan spesies kita.
Membantu untuk membangun dan mengembangkan cara pandangan dunia seperti ini adalah salah satu tujuan utama Pusat Ilmu Suci didirikan. Mereka tidak berada di bawah ilusi bahwa pandangan dunia baru dapat sepenuhnya dibangun atau disebarluaskan dalam semalam. Pemenuhan visi seperti itu adalah tugas sejarah yang mungkin memakan waktu beberapa generasi untuk menyelesaikan. [70]
- F. Tradisionalisme, Filsafat Perennial, dan Studi Islam
Salah satu aspek yang paling dikenal dari penolakan terhadap modernisme Barat telah terjadi di pinggiran pertemuan peradaban Eropa dengan Islam. Meskipun para ilmuwan sosial yang bekerja dalam studi Timur Tengah telah merasa aman mampu mengabaikan Filsafat perennial/abadidan eksponen Tradisi, para spesialis dalam studi agama tiba-tiba memiliki lebih banyak eksposur ke mazhab pemikiran post-modern ini. [71]
The Journal of the American Academy of Religion telah menampilkan artikel tentang eksponen Perennialism,[72] dan Konsultasi Esotericism dan Perennialism (dengan organisasi saudaranya, Academy Hermetik) yang telah selama beberapa tahun menyelenggarakan panel makalah pada konferensi tahunan AAR. Asal-usul filosofi ini dapat dicari dalam posisi tradisionalis yang dikembangkan oleh sejumlah pemikir ultramontane Katolik Perancis abad kesembilan belas, terutama Joseph de Maistre (w. 1821), L. de Bonald (w. 1840), dan FR de Lammenais (w. 1854). Tradisionalisme pada dasarnya merupakan filsafat sejarah yang menentang rasionalisme para filsuf Pencerahan, dan tradisi yang terlalu ditinggikan (terutama gereja Katolik) ke posisi otoritas ilahi dan mutlak. Jadi ini adalah oposisi ekstrem dari beberapa tradisionalis kepada modernisme sehingga mereka dikucilkan pada tahun 1855 untuk penolakan mereka terhadap akal (reason).
Namun kritik tradisionalis kepada modernisme masih memegang daya banding, dan kemudian diadopsi oleh anggota okultisme dan esoteris bawah tanah Perancis pada pergantian abad. Adalah gagasan penting dari tradisi, yang bahkan untuk Lammenais termasuk wahyu primitif atau primordial yang tidak terbatas pada agama Kristen (ini nanti akan muncul kembali sebagai monoteisme primitif Wilhelm Schmidt). Tradisi suci bisa diberi nomor dalam bentuk jamak, dan dengan demikian semua agama itu harus dianggap sebagai manifestasi dari Filsafat Perennial yang satu dan abadi (frase “filsafat perennial” dari karya Latin Philosophia perennis oleh sarjana Renaissance Augustinus Steuchus, ditulis dalam tahun 1540, dan itu kemudian dijemput oleh Leibniz, tapi tidak halnya dengan implikasi ekumenis yang luas seperti dalam Tradisionalisme kontemporer).
Apa yang sangat relevan untuk studi Islam adalah bahwa, meskipun penghormatan teoretis mereka untuk Katolikisme, sebagian besar penganut Filsafat perennial/abadilebih tertarik dengan Islam, meskipun ada beberapa yang lebih erat terkait dengan Buddhisme (Marco Pallis, AK Coomaraswamy) atau Taoisme (de Pourvourville). Apa daya tarik tradisionalisme, dan mengapa mayoritas tradisionalis menemukan Islam menjadi tradisi suci tunggal yang memenuhi aspirasi mereka?
Ketidakpuasan terhadap ekses dari Pencerahan Eropa dan modernisme tampaknya menjadi alasan utama. Abad kesembilan belas melahirkan sejumlah keturunan ideologis yang memiliki pengaruh yang sangat buruk: nasionalisme pseudo-agama, keyakinan positivistik dalam ilmu pengetahuan, rasisme dan evolusionisme sebagai alasan untuk imperialisme yang tak terkendali, erosi peran publik agama. Terhadap usaha Promethean ini yang kaum Perennialists bertahan lebih dari manusia yang punya otoritas wahyu primordial, gnosis ilahiyah disesuaikan untuk memberi rahmat kepada keadaan yang berbeda dalam bentuk agama, dan pandangan sejarah devolutionistic yang melihat modernitas sebagai pemberontakan yang direndahkan dan setan terhadap realitas.
Dengan tempat ini dalam pikiran, kita dapat melihat bagaimana Islam sebagai tradisi suci secara alami akan menempati posisi sentral. Penekanan teologis persatuan Islam, konsep historiografi Islam sebagai wahyu terakhir dalam urutan turunnya kenabian, dan posisi oposisi dari negara-negara Islam sebagai blok terbesar mengalami kolonisasi Eropa, semuanya membuat sudut pandang alami tradisionalis Islam untuk mencari afiliasi otentik. Kristen telah babak belur terlalu parah dan rusak untuk melayani sebagai tempat berlindung (ultra-Katolik Rama Coomaraswamy menganggap kepausan saat ini tidak sah karena telah meninggalkannya ritual abad pertengahan). Hal ini tidak mudah untuk mengkonversi ke agama Hindu, Yahudi ortodoks, atau tradisi suku, dan agama Buddha mungkin bukan pilihan yang valid di Barat. Yang tampaknya meninggalkan Islam.
Kaum Tradisionalis yang berpindah agama ke Islam, beberapa di antaranya berafiliasi dengan tarekat Sufi Alawi-Shadhili, termasuk pelukis Swedia Ivan Aguéli (`Abd al-Hadi, d. 1917), esotericists Perancis: Leon Champrenaud (`Abd al-Haqq) dan René Guenon (‘Abd al-Wahid Yahya, d. 1951 di Kairo), dan rekan Guenon yang orang Swiss, Titus Burckhardt dan Frithjof Schuon (Isa Nur al-Din, sekarang tinggal di Bloomington, Indiana). Terjemahan dari teks-teks mistik Islam mereka (terutama dari mazhab Ibn `Arabi) dan serangkaian buku tentang Islam dan agama menemukan pembaca yang menerimanya. Jurnal Perancis, Études Traditionnelles, dan imbangannya yang berbahasa Inggris, Tommorow, yang kemudian dinamai Studies in Comparative Religion mempopulerkan pandangan mazhab ini, perwakilan koleksi esai ditemukan dalam The Sword of Gnosis (1974), yang diedit oleh Jacob Needleman. Perspektif tradisionalis kini dibagi bersama terutama oleh sejumlah kecil intelektual tapi berpengaruh, pada sebagian besar Muslim di Eropa dan Amerika, tetapi semakin juga di negara lain seperti Pakistan, Indonesia dan Malaysia. Buku-bukunya yang dikaji semuanya ditulis oleh penulis Muslim yang tradisionalis, penganut Filsafat perennial/abadidalam arti hanya menjelaskan, meskipun masing-masing memiliki penekanan khusus dan sudut pandangnya sendiri.
King of the Castle karya Charles Le Gai Eaton adalah ulangan dari karya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1977, dengan kata pengantar singkat baru yang mengomentari karakter pribadi dari buku dan asal usulnya dari karya yang lebih tua disebut The Riches Vein (1947). Tujuannya adalah “untuk mewartakan keanehan zaman modern dan membuka kedok pretensinya”. Judul ironisnya menggambarkan situasi manusia modern dalam hal permainan satu-upmanship anak-anak. Dalam serangkaian delapan esai seperti bab (tidak ada indeks), Eaton berturut-turut mengambil topik masyarakat, ekonomi, antropologi filosofis, dan agama. Lebih bersedia memberikan komentar secara langsung sebagai konservatif politik daripada tradisionalis lainnya, Eaton dikutip telah melihat totalitarianisme (baik Nazi dan Komunis) sebagai produk modernitas anti-tradisional yang paling khas.
Serangan terhadap pejabat birokrasi dibenarkan oleh kebangkitan nostalgia kemerdekaan pengusaha kecil dan petani (di sini konservatif Katolik Gustave Thibon disebut dalam faksi yang mendukung). Gayanya intens, dramatis, dan ironis verging pada sarkasme ketika modernitas ditujukan (yaitu, sebagian besar waktu). Otoritas spiritual seperti Al-Qur’an dan Rumi yang sering dikutip, dan banyak analogi dan anekdot yang digunakan sebagai kaitan untuk menggantung argumen. Tujuan utamanya, bagaimanapun, tidak menganjurkan mistik, tetapi untuk menanamkan doktrin yang akan memperkuat daya tahan seseorang terhadap kekuatan korosif modernitas; ini merupakan khotbah yang diperpanjang, dari posisi Islam universal, memperjuangkan peran agama yang kesepian di zaman yang jahat.
Martin Lings yang dikenal sebagai Islamicists dalam studi kaligrafi Al Qur’an, untuk biografi Sufi Aljazair Syaikh Ahmad al-`Alawi (A Sufi Saint of the Twentieth Century), dan untuk biografi Nabi Muhammad. Sebelumnya sebagai seorang kurator naskah Oriental di British Museum, ia juga menulis tentang Shakespeare dan mata pelajaran lain. Buku kecil ini adalah kumpulan dari sepuluh esai tentang simbolisme dalam berbagai tradisi agama. Bab pertama, “What is Symbolism?” menggunakan contoh-contoh Al-Qur’an untuk mendefinisikan simbol sebagai refleksi dari realitas yang lebih tinggi dalam gambar yang mengungkapkan hubungan antara mikrokosmos ke makrokosmos; pengetahuan tentang hubungan ini, diperoleh melalui kitab suci dan ritual tradisional, yang diperlukan untuk mengatasi jatuh dari kesempurnaan manusia primordial. Esai berikutnya mencerminkan relatif tentang pentingnya simbol seperti benteng batu bentrok yang menghalangi jalan ke dunia spiritual (“The Decisive Boundary”), polaritas (“The Simbolism of Pairs), trinitas (“The Symbolism of the Triad of Primary Colours“), Raja-Paus/King-Pontiff (“The Archetypes of Devotional Homage“), dan liturgi suci (“The Language of the Gods“). Topik yang lebih khusus dipertimbangkan dalam “The Quranic Simbolisme of Water“, “The Symbolism of the Luminaries in Old Lithuanian Songs“, “The Seven Deadly Sins” dan “The Symbolism of the Mosque and the Cathedral.” Metode analisis yang digunakan adalah komparatif, mengikuti Coomaraswamy dalam menggunakan beberapa contoh dari tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda dan mengurangi mereka untuk makna metafisik tunggal. Lings percaya diri untuk menggunakan satu tradisi untuk menjelaskan yang lain, misalnya, Brahma, Siwa, dan Wisnu menjelaskan Trinitas Kristen, sedangkan Injil Yohanes menggambarkan karakter Nabi Muhammad. Buku ini adalah contoh yang baik dari program penafsiran dari metafisika tradisionalis sebagai disistematis-kan oleh Schuon.
Karya Seyyed Hossein Nasr Traditional Islam and the Modern World (Tradisional Islam dan Dunia Modern) adalah kumpulan dari delapan belas esai yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1987, yang membela Islam tradisional terhadap kedua modernisme (apakah Eropa atau Islam) dan yang bertentangannya: fundamentalisme (ekstrimisme-radikalisme, pent). Nasr, yang terkenal karena banyak studi ilmu pengetahuan Islamnya, budaya, dan spiritualitas, di sini menyinggung beragam subjek dalam upaya untuk memperbaiki, tidak hanya distorsi standar Orientalisme, tetapi juga salah tafsir yang berasal dari jurnalisme politik, Marxisme, dan apa yang disebut “kebangkitan kembali Islam.”
Bagian pertama, “Facets of the Islamic Tradition” (Wajah Tradisi Islam), membahas jihad, etos kerja, dan hubungan pria-wanita untuk menunjukkan gagasan tradisi sebagai wahyu suci yang mencakup segalanya melalui sejarah dan alam. Bangunan eksplisit Filsafat perennial/abadiini menurut Guenon dan Schuon, bagian ini khusus mengikat touchstones/tombol sentuh Tradisi Islam: istilah din dan sunnah, koleksi hadits standar (baik Sunni dan Shi`i), dan tasawuf Safawi Iran. Pada saat yang sama, mungkin akan dikatakan bahwa abstraksi sangat neologisme tertentu yang digunakan di sini (misalnya, “Islamicity/keislaman“, “Syariat“), dan ketegangan sintetis transendensi sejarah seperti antara Sunni dan Syiah, titik arah alam baru-baru ini dan sifat retrospektif pertahanan tradisi.
Bagian II, “Traditional Islam and Modernism,” menggali lebih lanjut tetang kontras antara kurangnya prinsip-prinsip antropomorfik modern dan keutuhan dan karakteristik transendensi dari sikap tradisional. Kritik Nasr tentang sifat modernistik (terutama pengurangan politik agama kepada ideologi dan etika) sering cerdik dan mengungkapkan.
Bagian III, “Tradition and Modernism—tensions in Various Cultural Domains” (Ketegangan Tradisi dan Modernisme di Berbagai Wilayah Budaya,)” membangun kritik modernisme kumulatif dengan tujuh esai yang segera memanggil intelektual Muslim untuk peduli kepada penderitaan mereka. Area utama yang dibahas di sini adalah pendidikan, filsafat, dan arsitektur, dalam semua yang, menurut pendapat Nasr pengaruh Barat secara sistematis telah mengikis dasar asli Islam di sebagian besar negara-negara Muslim.
Bagian IV, “Western Interpreters of the Islamic Tradition (Penafsir Barat atas Tradisi Islam)” memberikan kesaksian hangat tentang sedikit sarjana Eropa yang telah melampaui Orientalisme dengan keterlibatan pribadi yang intens dengan Islam. Seorang Katolik (Louis Massignon), seorang Protestan (Henry Corbin), dan Muslim (Titus Burckhardt) telah ditampilkan sebagai pengingat bahwa mungkin telah terjadi pertemuan spiritual asli dengan Islam pada bagian dari intelektual Barat yang belum menyerah pada sekularisme dan modernisme. Bagian penutup “Postscript” menambahkan mesianisme ke daftar tanggapan Muslim terhadap modernisme, dan memberikan refleksi akhir tentang pentingnya modernisme itu sendiri, berbagai tren yang biasa disatukan sebagai “fundamentalisme”, dan wakil-wakil yang tersisa dari Islam tradisional. Nasr berbicara dengan penuh semangat tapi ironisnya abai dari kebutuhan untuk dimensi intelektual terhadap kritik modernisme. Buku ini mungkin adalah contoh terbaru terbaik dari perspektif tradisionalis Islam.
Volume yang disunting oleh Seyyed Hossein Nasr, Islamic Spirituality Manifestation adalah pasangan dari Islamic Spirituality Foundation. Kedua volume tentang Islam ini telah berusaha untuk menghindari historisisme dan skeptisisme rasionalistik, yang keduanya kecenderungan yang digambarkan sebagai asing bagi Islam.
Sebagai bagian dari seri Spiritualitas Dunia, buku ini memperlakukan tasawuf sebagai aspek batin atau spiritual Islam, dan editor menggambarkan koleksi ini dari artikel sebagai upaya pertama untuk memperlakukan tasawuf dalam skala global. Seperti dalam volume pertama, penulis artikel terpisah ini adalah sebagian besar umat Islam (termasuk sejumlah tradisionalis).
Pendahuluan dan Prelude tentang Tarekat Sufi ini adalah kontribusi oleh Nasr, yang diikuti oleh dua puluh lima esai tentang topik yang terpisah.
Bagian Satu, “Spiritualitas Islam yang diwujudkan dalam tasawuf di dalam Ruang dan Waktu,” berisi lima belas esai tentang sufi tertentu, mazhab, dan daerah.
Bagian Kedua, “Sastra Islam sebagai Cermin Spiritualitas Islam,” memiliki enam esai tentang sastra Islam dalam bahasa Arab, Persia, Turki, Indo-Muslim, Melayu, dan literatur Afrika.
Bagian Ketiga, “Pesan Spiritual Seni dan Pemikiran Islam”, memiliki empat esai umum topik khusus tentang teologi dan filsafat, ilmu yang tersembunyi, musik dan tari, dan seni. Sayangnya tidak ada daftar ilustrasi selain dari kredit judul untuk tujuh belas foto yang direproduksi di sini. Dalam jumlah ruang terbatas yang tersedia, maka hal tersebut pasti memerlukan tinjauan singkat dan ringkasan yang akan membantu terutama untuk siswa dalam mencari orientasi pertama bibliografi topik tertentu.
Sejumlah penulis sarjana terkemuka dalam studi tasawuf (yaitu KA Nizami, A. Schimmel, J. Nurbaksh) yang memiliki presentasi padat terpaksa dibuat dalam penjelasan penuh rinci di tempat lain. Namun, beberapa artikel singkat dan sepintas yang mengecewakan, sejauh menjadi tidak lebih dari daftar nama; yang sangat tidak memadai adalah artikel tentang sastra Sufi Arab, subjek yang berteriak untuk perlakuan penuh.
Menurut Carl W. Ernst artikel yang paling sukses adalah oleh William Chittick tentang Ibn `Arabi dan Rumi, yang merupakan esai programatik oleh Nasr tentang “Teologi, Filsafat, dan Spiritualitas,” dan survei yang dilakukan oleh Jean-Louis Michon tentang “Tarian Suci dan Musik dalam Islam”. Karena tidak semua kontributor berbagi perspektif filosofis yang sama, kita tidak mendapatkan dari sebuah volume pandangan Perennialist atau tasawuf yang jelas dan seragam
Apa arti penting dari mazhab tradisionalis untuk studi Islam? Penolakan mereka terhadap historisisme menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar ahli tentang Islam, apakah dia humanis atau ilmuwan sosial. Jika premis dari Filsafat Perennial kebobolan, maka banyak aparat keulamaan/kesarjanaan modern, yang mengakui produk Pencerahan, telah dihukum. Sketsa yang diberikan di atas mencoba untuk menguraikan latar belakang intelektual tradisionalisme sebagai respon terhadap modernisme Eropa; penempatan sejarah ironisnya membuat Tradisionalisme tidak tradisional atau khas Islam. Sebelum krisis budaya tertentu yang disebabkan oleh modernisme, itu tidak perlu dan tidak mungkin untuk merumuskan pembelaan tradisi seperti itu. Namun kita juga dapat melihat mengapa Filsafat perennial/abadiakan menjadi pilihan yang menarik bagi para pemikir Muslim dalam mencari posisi yang melawan imperialisme budaya Barat yang sekuler. Jika pemikir Muslim menerima alasan otonom pencerahan Eropa, tidak ada lagi ruang untuk transendensi, maupun pembenaran intelektual untuk Muslim sisanya. Tradisionalisme, kemudian, adalah kritik teologis terhadap modernisme yang telah menemukan titik kumpul alami dalam tradisi yang paling terancam oleh Barat, yaitu Islam. Modernisme ditantang di berbagai bidang. Penegasan perlunya doktrin suci dan Tradisi, bagaimanapun, terus terang otoriter, dan itu hanya akan menarik bagi minoritas; sementara saingannya fundamentalis yang berusaha untuk mencari pengikut massal, Tradisionalisme akan terus menjadi pilihan intelektual untuk beberapa Muslim (dan non-Muslim) dalam dunia post-modern.
Dalam bukunya What is Tradition, S.H. Nasr menjelaskan hubungan antara tradisi dan agama dari perspektif filsafat perennial yang dapat diringkas sebagai berikut: Sifat tradisi adalah merangkul semua, dan agama terletak pada asal-usul tradisi tersebut. Dipahami dalam pengertian agama ini adalah apa yang mengikat manusia dengan Tuhan dan pada saat yang sama mengikat orang-orang satu sama lain. Agama Hindu dan Buddha Dharma, al-din al-Islam, Taoist Tao, dan sejenisnya erat terkait dengan makna dari tradisi panjang tersebut, tapi tidak identik dengan itu, walaupun tentu saja dunia atau peradaban yang diciptakan oleh Hindu, Buddha, Taoisme, Yahudi, Kristen, Islam, atau dalam hal ini agama otentik lainnya, adalah dunia tradisional (SH Nasr 1989 hal.67). Dari perspektif itu, tradisi karena itu bertentangan prinsip modernisme. Ini ingin membunuh dunia modern dalam rangka menciptakan sesuatu normal (Needleman (end) 1974). Tujuannya bukan untuk menghancurkan apa yang positif dari modernism, tetapi untuk menghapus selubung ketidaktahuan modernism yang memungkinkan ilusi muncul sebagai nyata, negatif positif dan palsu sebagai benar (SH Nasr 1989).
- G. Filsafat perennial/abadi (Filsafat yang Abadi)
The philosophia perennis atau Filsafat perennial/abadi menegaskan bahwa wawasan langsung ke dalam sifat dari Realitas adalah kemungkinan universal manusia – apakah itu bisa diperoleh setelah latihan disiplin spiritual dan studi kitab suci tertentu, atau melalui sepenuhnya pengalaman pencerahan menjadi persatuan tak terduga dengan Tuhan atau the Ultimate. Hasil dari kesadaran tersebut adalah keyakinan bahwa kita telah berasal dari Satu Sumber tunggal dan proses pembangunan spiritual kita itu selesai dan disempurnakan ketika kita kembali kepada Yang Satu itu.
![]()
Menyebut perennial ini adalah untuk mengatakan bahwa wawasan semacam itu muncul kembali dalam waktu dan tempat yang beragam, yang tidak terbatas pada budaya khusus, kelas, atau masyarakat tertentu. Dalam kata-kata yang lebih formal, filosofi ini telah digambarkan sebagai “metafisika yang mengakui Realitas illahiyah di balik segala dunia benda, jiwa dan pikiran; psikologi yang menemukan dalam diri seseorang yang identik dengan Realitas illahiyah dan etika yang menempatkan tujuan akhir [seseorang] dalam pengetahuan tentang latar Imanen (yang mencakup/meliputi) dan Transenden (yang luhur) dari segala sesuatu. “
Dalam kata lain, istilah philosophia perennis dimaksudkan untuk menggambarkan filosofi yang telah dirumuskan oleh orang-orang yang telah mengalami penyatuan (Itihad /manunggaling) langsung dengan Allah atau The Ultimate. Betapapun singkatnya, pengalaman itu mengubah pemikiran orang yang mengalaminya, sehingga mereka tidak pernah sama lagi. Penyataan pengalaman tersebut, dapat ditangkap, namun tampak samar-samar dalam simbol-simbol yang disediakan oleh bahasa manusia atau apapun ekspresi yang artistik, namun sering kali diulang selama berabad-abad oleh orang-orang dari semua ras, jenis kelamin, budaya dan keyakinan agama, yang terbuka kepada Perennial Philosophy.
Lebih dari setengah abad yang lalu, Aldous Huxley memberikan judul ini kepada sebuah antologi yang ia edit. Dalam jenis pengalaman yang berpusat padanya, apakah yang disebut yang kuno atau primordial atau mistis, selubung materialitas adalah pinjaman dan kepastian yang keliru yang akan terhalau.
Untuk para pembaca, antologi Huxley mungkin dapat memvalidasi dan memverifikasi saat di mana self-knowledge seseorang merasa bergerak melampaui keterbatasan diri dari sekedar “a foul stinking lump of himself, (sebuah benjolan bau busuk dari dirinya sendiri),” sebagai mana teks Inggris klasik tentang instruksi spiritual, The Cloud of Unknowing telah menggambarkannya. Apakah teks-teks seperti instruksi spiritual dan pengalaman mistik tradisional ini masih bernilai saat ini? Filsafat Perennial merespon dengan tegas, Ya !
Salah satu cara untuk mengungkapkan wawasan sentral dari Filsafat perennial/abadi adalah dengan kalimat That Thou Art, yang diambil dari bahasa Sansekerta dari kitab Upanishad kuno. Ungkapan ini mengajarkan bahwa Diri abadi yang imanen diwujudkan menjadi satu dengan Prinsip Absolute/Mutlak dari semua Eksistensi, dan bahwa takdir sejati manusia adalah untuk menemukan fakta ini untuk diri mereka sendiri, untuk mengetahui Siapa dan Apakah mereka sebenarnya. Di antara ekspresi hidup lain dari pandangan ini adalah:
- BYAZID OF BISTUM: “Saya pergi dari Tuhan Allah kepada Tuhan Allah, sampai mereka menangisi saya dari dalam diri saya,” O Dia – Aku”!
- ST. CATHERINE OF GENOA: “Saya adalah (bagian dari) Tuhan Allah, juga saya tak mengenali yang lain kecuali Tuhan Allah sendiri.”
- YUNG-CHIA-TA-SHIH: “Cahaya batin adalah di luar dari pujian dan sikap menyalahkan, seperti ruang, itu tidak mengenal batas, bahkan di sini, di dalam diri kita, pernah mempertahankan ketenangan dan kepenuhannya, hanya ketika Anda memburunya, Anda kehilangan itu. Anda tidak dapat memegang itu, tapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa menyingkirkan itu. “
- MEISTER ECKHART:. “Semakin Tuhan ada dalam segala hal, semakin Dia berada di luar mereka, semakin Dia berada di dalam, semakin tanpanya. Hanya yang transenden, yang lainnya yang lengkap, dapatkah menjadi yang imanen tanpa mengubah oleh yang menjadi di dalamnya yang berdiam.”
- Dan apakah itu yang Engkau dapat menemukan dirinya untuk menjadi?
- RUYSBROECK: “Dalam Realitas Kemenyatuan yang dikenal dengan mistik … kita tidak bisa berbicara makhluk apapun lagi, melainkan hanya dari satu Being (Keberadaan) … Ada kita semua adalah Satu sebelum penciptaan kita, karena ini adalah esensi-super kita. “
- ST. BERNARD: “Siapakah Tuhan Allah? Saya bisa memikirkan tidak ada jawaban yang lebih baik daripada siapa Dia. Tidak ada yang lebih sesuai dengan kekekalan sebagaimana Tuhan Allah. Jika Anda sebut Allah itu baik, atau Maha Besar, atau Maha memberkati atau Maha Bijaksana, atau apa pun semacam ini.., itu termasuk dalam kata-kata ini, yaitu, Dia lah. “
Bagaimana seseorang dapat mencapai kepastian batin itu?
Filsafat Perennial menawarkan jawaban yang tampaknya paradoks. Hambatan bagi pengetahuan Kemenyatuan (Unitive) itu adalah kesadaran obsesif menjadi diri yang terpisah.Yang dilampirkan kepada aku, saya atau milik saya, tidak termasuk pengetahuan unitive tentang Allah.
- WILLIAM LAW: “Manusia tidak berada di neraka karena Allah marah dengan mereka … mereka berdiri di bagian kedaaan perpecahan dan pemisahan dengan gerakan mereka sendiri, yang mereka telah membuatnya untuk diri mereka sendiri.
- ST. JOHNTHE CROSS: “Jiwa yang masih melekat pada apa pun, betapapun banyaknya kebaikan yang mungkin ada di dalamnya, tidak akan sampai pada kebebasan kesatuan ilahiyah … yang diselenggarakan oleh ikatan kasih sayang manusiawi, … betapapun mereka mungkin sedikit, kita tidak bisa, selagi masih ada, membuat jalan kita kepada Tuhan Allah. “
- ALDOUS HUXLEY: “Kita melewati dari waktu kepada keabadian ketika mengidentifikasi dengan spirit/semangat dan melewati lagi dari keabadian kepada waktu ketika kita memilih untuk mengidentifikasi dengan tubuh.”
- Bantuan apa yang tersedia?
- PHILO DARI ALEKSANDRIA: “Mereka berada di jalan kebenaran yang memahami Tuhan Allah dengan cara yang ilahi, diterangi oleh Cahaya (Cahaya di atas Cahaya.)”
- Kapan tersedia? Pertimbangkan afirmasi berikut ini:
- JOEL GOLDSMITH:. “Saya dalam persatuan dengan Kecerdasan Ilahiyah masa lalu, masa kini dan masa depan. Tidak ada rahasia spiritual yang tersembunyi dari saya … Ada Being yang Transendental ini dalam diri saya, yang adalah saya dan yang saya memiliki akses Itu selamanya …. Kesadaran ilahiyah yang tak terbatas dari Tuhan Allah, Kesadaran dari masa lalu, dan masa sekarang dan masa depan, adalah kesadaran saya saat ini. “
- ALDOUS HUXLEY:.. “Kita berada di dalam sebuah proses menyapu kembali menuju titik yang sesuai dengan tempat awal di kebinatangan kita, tapi ada ketidaksamaan di atasnya. Sekali lagi kita hidup tinggal di saat itu. Kehidupan sekarang dari makhluk yang cintanya telah mengusir rasa takut, visi telah mengambil tempat harapan duniawi, dan mementingkan diri sendiri telah menghentikan egoisme positif dari puasnya kenangan dan egoisme negatif penyesalan.”
- “Saat ini adalah satu-satunya singkapan melalui mana jiwa bisa lewat dari waktu ke dalam kekekalan, di mana karunia kasih bisa lulus dari keabadian ke dalam jiwa, dan di mana cinta dapat lulus dari satu jiwa pada waktunya untuk jiwa lain dalam waktu.
Lebih dari dua puluh lima abad telah berlalu sejak apa yang telah disebut Filsafat perennial/abadi pertama kali berkomitmen untuk ditulis; dan dalam perjalanannya berabad-abad telah ditemukan ekspresi, kadang bersifat parsial, kadang lengkap, kadang dalam bentuk ini, kadang dalam hal itu, lagi dan lagi. Dalam tradisi kenabian Vedanta dan Ibrani, dalam Tao The King and Dialog Plato, dalam kitab Injil menurut St John dan teologi Mahayana, dalam Plotinus dan Aeropagite, di antara para Sufi Muslim Persia dan mistikus Kristen Abad Pertengahan dan Renaissance, Filsafat perennial/abadi telah dibicarakan hampir dalam semua bahasa di Asia dan Eropa, dan telah membuat penggunaan istilah dan tradisi dari setiap salah satu agama yang lebih tinggi. Tetapi di bawah semua kebingungan ini dalam tradisi lisan dan mitos, dari sejarah lokal dan doktrin partikularistik, tetap ada Faktor umum Tertinggi yang merupakan Filsafat perennial/abadi dalam apa yang kimiawi-nya disebut dalam keadaan murni. Kemurnian akhir ini tidak pernah, tentu saja, akan dapat diungkapkan oleh pernyataan lisan filsafat, bagaimana pun pernyataan ini tak-dogmatis, namun sengaja sinkretis. Kenyataan bahwa itu ditetapkan pada waktu tertentu oleh seorang penulis tertentu, menggunakan ini atau bahasa itu, secara otomatis membebankan bias sosiologis dan pribadi tertentu pada doktrinnya begitu dirumuskan. Ini hanyalah tindakan kontemplasi ketika kata-kata dan bahkan kepribadian yang melampaui, bahwa dalam keadaan murni Filsafat perennial/abadi sebenarnya dapat diketahui. Catatan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dikenal dengan cara ini membuatnya sangat jelas bahwa mereka semua, apakah Hindu, Buddha, Yahudi, Tao, Kristen, atau Islam, sedang berusaha untuk menggambarkan Fakta dasarnya sama yang tak terlukiskan.
Tulisan suci asli dari kebanyakan agama adalah puitis dan tidak sistematis. Teologi, yang umumnya mengambil bentuk sebuah komentar yang menalar perumpamaan dan kata-kata mutiara dari kitab suci, cenderung membuat penampilan pada tahap berikutnya dari sejarah agama. Bhagavad Gita menempati sebuah posisi perantara antara Kitab Suci dan teologi; karena itu menggabungkan kualitas puitis yang pertama dengan methode yang jelas yang kedua. Buku yang dapat dijelaskan, yang ditulis Ananda K. Coomaraswamy dalam bukunya yang Mengagumkan: Hindu dan Budha , “Sebagai sebuah ringkasan dari seluruh doktrin Veda yang dapat ditemukan dalam Veda sebelumnya, dalam Brahmana dan Upanishad, dan karena itu menjadi dasar dari semua perkembangan yang kemudian, yang dapat dianggap sebagai fokus dari semua agama India”, yang juga merupakan salah satu ringkasan paling jelas dan paling komprehensif dari Filsafat Perennial yang pernah telah dibuat.
Oleh karena itu nilainya itu bertahan, tidak hanya untuk orang India, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Pada intinya dari Filsafat perennial/abadi kita menemukan empat doktrin fundamental.
Pertama: dunia fenomenal materi dan kesadaran individual – dunia benda dan hewan dan manusia dan bahkan para dewa – adalah manifestasi dari Latar Ilahiyah di mana semua realitas parsial memiliki keberadaan mereka, dan bila terlepas dari-NYA, mereka akan tidak ada (tidak eksis).
Kedua: manusia mampu tidak hanya dapat mengetahui tentang Latar Ilahiyahnya dengan penalaran; mereka juga dapat menyadari keberadaan-Nya oleh intuisi langsung, yang lebih unggul dari penalaran diskursif. Pengetahuan langsung ini menyatukan yang mengetahui dengan apa yang diketahui.
Ketiga: manusia memiliki sifat alami ganda, ego fenomenal dan Diri yang abadi, yang merupakan batiniah manusia, semangat (spirit/ruh), percikan keilahian dalam jiwa. Hal ini dimungkinkan bagi seorang manusia, jika ia menginginkan, untuk mengidentifikasi dirinya dengan Semangat (Spirit/Ruh), dan oleh karena itu dengan Latar Ilahiyah, yang merupakan sifat yang sama atau mirip dengan Semangat (Spirit/Ruh),.
Keempat: kehidupan manusia di bumi hanya memiliki satu ujung dan tujuan: untuk mengidentifikasi dirinya dengan Diri abadinya dan sebagainya untuk datang ke pengetahuan kemenyatuan (unitive/itihad) dengan Latar Ilahiyah.
Dalam agama Hindu yang doktrin pertamanya dari empat doktrin yang dinyatakan dalam istilah yang paling kategoris. Landasan/Latar Ilahiyah/Ketuhanan adalah Brahman, Tuhan Yang Maha Pencipta, Yang Maha mempertahankan dan mengubah aspek yang diwujudkan trinitas Hindu. Sebuah hirarki manifestasi yang menghubungkan benda mati dengan manusia, dewa, para dewa tinggi, dan Ketuhanan yang tak dapat dibedakan dari luar.
Dalam Landasan/Latar Ketuhanan Mahayana Buddhisme disebut Pikiran atau Cahaya Kesunyian Murni, tempat para dewa tertinggi telah diambil oleh Dhyani-Buddha.
Konsepsi serupa yang cocok sempurna dengan Kristen dan kenyataannya telah dihibur, secara eksplisit maupun implisit, oleh banyak mistik Katolik dan Protestan, ketika merumuskan filsafat agar sesuai fakta yang diamati oleh intuisi super-rasional. Jadi, bagi Eckhart dan Ruysbroeck, ada ruang dalam tanpa dasar (Abyss) Ketuhanan yang mendasari Trinitas, seperti Brahman mendasari Brahma, Wisnu dan Siwa. Suso bahkan telah meninggalkan diagram gambar dari hubungan kehidupan antara Ketuhanan, Trinitas Tuhan dan Makhluk. Dalam gambaran yang sangat memancing rasa ingin tahu dan menarik ini, rantai manifestasi menghubungkan simbol misterius Latar Ilahiyah dengan tiga Pribadi Tritunggal, dan Tritunggal pada gilirannya terhubung dalam skala yang turun dengan malaikat dan manusia. Yang Terakhir ini, seperti gambaran jelas menunjukkan, dapat membuat salah satu dari dua pilihan. Mereka dapat baik menjalani kehidupan manusia lahiriah, kehidupan kedirian yang separatis; dalam hal ini mereka hilang (karena, dalam kata-kata dari Theologia Germanica, “tidak ada yang terbakar di neraka tapi akibat diri sendiri”). Atau mereka dapat mengidentifikasi diri mereka dengan batiniah manusia, dalam hal ini menjadi mungkin bagi mereka, seperti Suso tunjukkan, untuk naik lagi, melalui pengetahuan unitive, kepada Trinitas dan bahkan, di luar Trinity mereka, dengan Ultimate Unity (Kemenyatuan Mutlak) dari Ground/ Latar Ilahiyah.
Dalam tradisi Islam rasionalisasi seperti pengalaman mistik langsung ini akan menjadi berbahaya bagi kaum unortodoks. Namun demikian, kita memiliki kesan, pada saat membaca teks-teks sufi tertentu, bahwa yang penulis mereka lakukan adalah benar, memunculkan al–haqq, the Real, sebagai Latar/Landasan Ilahiyah atau Kesatuan/Keesaan Allah (Tauhidullah), yang mendasari aspek aktif dan pribadi Ketuhanan.
Doktrin kedua dari Filsafat perennial/abadi – adalah bahwa mungkin untuk mengetahui latar Ilahi oleh intuisi langsung yang lebih tinggi daripada penalaran diskursif – yang dapat ditemukan dalam semua agama besar dunia. Seorang filsuf yang puas hanya untuk mengetahui tentang Realitas utama – secara teoritis dan melalui desas-desus – dibandingkan dengan Buddha dengan laki-laki gembala sapi lain. Mohammad bahkan menggunakan metafora lumbung rumahan. Baginya filsuf yang belum menyadari metafisika adalah seperti keledai yang hanya membawa beban buku. Para guru Kristen, Hindu, guru Tao tidak kurang tegas menulis tentang pretensi absurd bila hanya belajar dari penalaran analitik. Dalam kata-kata Buku Doa Anglikan, kehidupan kekal kita, sekarang dan selanjutnya, “berdiri dalam pengetahuan tentang Allah”; dan pengetahuan ini tidak diskursif, tetapi “di dalam hati”, intuisi supra-rasional, langsung, sintetis dan abadi .
Doktrin ketiga Perennial Philosophy, bahwa yang menegaskan sifat ganda manusia, jika mendasar dalam semua agama yang lebih tinggi. Pengetahuan unitive (kemenyatuan/Manunggaling) Latar/Landasan Ilahiyah sebagai kondisi yang diperlukannya, telah siap untuk pengorbanan diri dan amal baik. Hanya dengan cara pengorbanan diri dan amal baik yang bisa membersihkan kita dari kejahatan, kebodohan dan ketidaktahuan yang merupakan hal yang kita sebut kepribadian kita, dan yang mencegah kita dari menyadari percikan keilahian yang menerangi batiniah manusia, tapi percikan dalam ini mirip dengan latar Ilahiyah. Dengan mengidentifikasi diri dengan yang pertama kita bisa datang ke pengetahuan unitive kedua. Fakta-fakta empiris dari kehidupan spiritual ini telah dirasionalisasikan dalam berbagai teologi dari berbagai agama. Hindu secara kategoris menegaskan bahwa Engkau Itu – bahwa berdiamnya Atman sama dengan Brahman. Untuk Kristen ortodoks tidak ada identitas antara percikan Tuhan dan Tuhan. Penyatuan jiwa manusia dengan Tuhan terjadi – penyatuan begitu lengkap sehingga kata pendewaan diterapkan untuk itu; tetapi bukan penyatuan identik substantial/zat. Menurut teologi Kristen, orang suci (santo) adalah” didewakan”, bukan karena Atman adalah Brahman, tetapi karena Tuhan Allah telah berasimilasi pada jiwa manusia yang dimurnikan ke substansi ilahiyah dengan tindakan karunia kasih Nya. Teologi Islam tampaknya membuat perbedaan serupa. Sufi, Mansur al-Hallaj, yang dieksekusi karena memberikan kata-kata “Persatuan” dan “Penuhanan” yang makna literalnya sama dengan yang ada dalam tradisi Hindu. Untuk tujuan kita ini, bagaimanapun, fakta penting adalah bahwa kata-kata ini benar-benar digunakan oleh orang Kristen dan Muslim pengikut Muhammad atau Mohamedan untuk menggambarkan fakta-fakta empiris realisasi metafisika dengan cara langsung, intuisi super-rasional .
Dalam kaitan dengan tujuan akhir manusia, semua agama yang lebih tinggi dalam perjanjian lengkap. Tujuan hidup manusia adalah penemuan kebenaran, pengetahuan unitive Ketuhanan. Sejauh mana pengetahuan unitive ini dicapai di bumi akan menentukan sejauh mana itu akan dinikmati di akhirat. Kontemplasi kebenaran adalah tujuan akhir, tindakan adalah alat. Di India, di Cina, di Yunani kuno, di Eropa Kristen, hal ini dianggap sebagai bagian yang paling jelas dan aksiomatik dari ortodoksi. Penemuan mesin uap yang dihasilkan revolusi industri, tidak hanya dalam teknik industri, tetapi juga jauh lebih signifikan dalam filsafat. Karena mesin bisa dibuat semakin lebih maju dan lebih efisien, orang Barat kemudian percaya bahwa manusia dan masyarakat secara otomatis akan mendaftarkan perbaikan moral dan spiritual yang sesuai. Perhatian dan kesetiaan datang yang harus dibayar, bukan untuk keabadian, tapi untuk masa depan utopis datang dianggap sebagai lebih penting bahwa keadaan pikiran tentang keadaan eksternal, dan akhir kehidupan manusia dianggap tindakan, dengan kontemplasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Doktrin-doktrin palsu dan historis, yang menyimpang dan sesat kini secara sistematis diajarkan di sekolah-sekolah kita dan diulang, hari demi hari, oleh para penulis naskah iklan anonim yang, lebih dari guru-guru lain, memberikan orang dewasa Eropa dan Amerika dengan filosofi pada saat mereka ini hidup. Dan propaganda ini telah begitu efektif sehingga bahkan orang Kristen yang mengaku menerima ajaran sesat tanpa bertanya dan cukup sadar lengkap ketidakcocokan dengan agama mereka sendiri atau orang lain.
Keempat doktrin yang merupakan Filsafat perennial/abadi dalam bentuk minimal dan dasar. Seorang manusia yang dapat mempraktekkan apa yang orang India menyebutnya Jnana yoga (disiplin diskriminasi metafisik antara yang nyata dan tampak) tak meminta apa-apa lagi. Hipotesis yang bekerja sederhana ini sudah cukup untuk tujuan-Nya. Tapi diskriminasi tersebut sangat sulit dan hampir tidak dapat dipraktekkan, pada setiap tingkat pada tahap awal kehidupan spiritual, kecuali oleh orang yang diberkahi dengan jenis tertentu dari konstitusi mental. Itulah sebabnya sebagian besar pernyataan dari Filsafat Perennial/abadi telah memasukkan doktrin lain, menegaskan keberadaan satu atau lebih adalah reinkarnasi manusia dari Latar (Ground) Ilahiyah, yang oleh mediasi dan rahmat penyembah dibantu untuk mencapai tujuannya – bahwa pengetahuan unitive Ketuhanan, manusia dan kebahagiaan yang hidup yang kekal. Bhagavad Gita adalah salah satu pernyataan seperti itu. Di sini, Krishna adalah inkarnasi Latar Ilahi dalam bentuk manusia. Demikian pula, dalam teologi Kristen dan Buddha, Yesus dan Gautama adalah inkarnasi keilahian. Namun, sementara di dalam Hindu dan Buddha lebih dari satu Inkarnasi Ketuhanan adalah mungkin (dan dianggap sebenarnya telah terjadi), bagi orang Kristen telah ada dan bisa hanya satu.
Sebuah Inkarnasi dari Ketuhanan dan, pada tingkat lebih rendah, setiap saint (wali) yang teosentris, bijak atau nabi adalah manusia yang tahu siapa dia dan karena itu dia dapat secara efektif mengingatkan manusia lain dari apa yang telah membiarkan diri mereka lupa: yaitu, bahwa jika mereka memilih untuk menjadi apa yang mereka sudah berpotensi, mereka juga bisa selamanya bersatu dengan Ground/Latar Ilahiyah.
Ibadah dari Inkarnasi dan perenungan sifat-sifat-Nya yang bagi kebanyakan pria dan wanita adalah persiapan terbaik untuk pengetahuan unitive Ketuhanan. Namun apakah pengetahuan itu sendiri dapat dicapai dengan cara ini adalah pertanyaan lain. Banyak penganut mistik Katolik telah membenarkan bahwa, pada tahap tertentu dari doa kontemplatif, di mana, menurut para teolog paling otoritatif, kesempurnaan kehidupan Kristen akhirnya terdiri, perlu untuk mengesampingkan semua pikiran dari Inkarnasi sebagai hal yang mengganggu dari pengetahuan yang lebih tinggi itu yang telah menjelma. Dari fakta ini telah muncul kesalahpahaman di banyak intelektual dan sejumlah kesulitan. Di sini, misalnya, adalah apa yang Abbot Josh Chapman tulis dalam salah satu Surat Spiritual mengagumkan-nya: “Masalah rekonsiliasi (bukan hanya menyatukan) mistisisme dengan agama Kristen lebih sulit. The Abbot (Abbot Marmion) mengatakan bahwa St Yohanes of The Cross adalah seperti penuh spons kekristenan. Anda dapat menekan semuanya, dan teori mistis tetap penuh. Akibatnya, selama lima belas tahun atau lebih, aku benci St Yohanes of Th Cross dan memanggilnya sebagai seorang Buddhis. Aku mencintai St Teresa, dan membaca-nya berulang-ulang, pertama Dia seorang Kristen, hanya secara sekunder seorang mistik. Kemudian saya menemukan bahwa saya telah menyia-nyiakan lima belas tahun, sejauh doa khawatir. “Namun, ia menyimpulkan, meskipun dari karakter “Buddhis”, praktik mistisisme (atau, untuk memasukkannya ke dalam istilah lain, realisasi Filsafat perennial/abadi) membuat orang Kristen jadi yang baik. Dia mungkin telah menambahkan bahwa hal itu juga membuat umat Hindu yang baik, Buddha yang baik, Tao yang baik, Muslim yang baik dan Yahudi yang baik.
Solusi untuk masalah Abbot Chapman harus dicari dalam domain, bukan filsafat, tetapi psikologi. Manusia tidak dilahirkan identik. Ada banyak temperamen dan konstitusi yang berbeda; dan dalam setiap kelas psiko-fisik seseorang dapat menemukan orang-orang pada tahap perkembangan spiritual yang berbeda. Bentuk ibadah dan disiplin spiritual yang mungkin berharga untuk satu individu mungkin tidak berguna atau bahkan positif berbahaya bagi yang lain yang memiliki kelas yang berbeda dan berdiri, dalam kelas itu, pada tingkat lebih rendah atau lebih tinggi dari perkembangan. Semua ini jelas diatur dalam Gita, di mana fakta-fakta psikologis terkait dengan kosmologi umum melalui dalil dari Gunas.
Krishna, yang ada di sini adalah potongan mulut/lisan Hindu dalam segala manifestasinya, sangat alamiah menemukan bahwa manusia yang berbeda harus memiliki metode yang berbeda dan bahkan tampaknya obyek ibadah berbeda. Semua jalan menuju Roma – asalkan, tentu saja, bahwa itu adalah Roma dan bukan kota lain yang wisatawan benar-benar ingin mencapainya. Sikap serupa amal inklusivitas, agak mengejutkan dalam Islam, dengan indah dinyatakan dalam perumpamaan Musa dan penggembala hewan, diberitahu oleh Jalaluddin Rumi dalam buku kedua dari Masnawi. Dan lebih eksklusif dalam tradisi Kristen masalah dari temperamen dan tingkat pembangunan ini telah diselidiki dalam hubungannya dengan cara Maria dan cara Martha pada umumnya dan khususnya untuk panggilan dan pengabdian pribadi individu .
Kami sekarang harus mempertimbangkan prasyarat etis dari Filsafat Perennialism-abadi. “Kebenaran”, kata St. Thomas Aquinas, “adalah akhir final untuk seluruh alam semesta, dan kontemplasi kebenaran adalah pekerjaan utama dari kebijaksanaan.” Kebajikan moral, katanya di tempat lain, milik kontemplasi, memang tidak esensial dasarnya, tetapi sebagai predisposisi/pendahuluan yang diperlukan. Kebajikan, dengan kata lain, bukanlah akhir, tetapi sarana yang sangat diperlukan untuk pengetahuan tentang realitas ilahiyah. Shankara, komentator tentang Gita, yang terbesar dari India, memegang doktrin yang sama. Tindakan yang benar adalah cara untuk pengetahuan; untuk itu memurnikan pikiran, dan itu hanya untuk memurnikan pikiran dari egoisme bahwa intuisi Latar Ilahiyah bisa datang.
Pengorbanan diri, menurut Gita , dapat dicapai dengan praktek dua kebajikan – cinta inklusif bagi semua dan ketidak-melekatan (non–attachment), yang terakhir adalah hal yang sama seperti yang “ketidakpedulian yang suci”, di mana St Francois de Sales tidak pernah lelah bersikeras. “Dia yang mengacu setiap tindakan kepada Tuhan Allah”, tulis Camus, meringkas ajaran tuan gurunya”, dan tidak memiliki tujuan menyimpan kemuliaan-Nya, yang akan menemukan sisanya di mana-mana, bahkan di tengah-tengah keributan paling kejam. “Selama kita berlatih ketidakpedulian suci ini ke hasil dari tindakan”, tidak ada pekerjaan yang sah yang akan memisahkan kita dari Tuhan Allah; Sebaliknya, hal itu dapat kita jadikan sarana penyatuan yang lebih dekat. “Di sini kata ‘halal’ memasok kualifikasi yang diperlukan untuk pengajaran yang, tanpa itu, tidak lengkap dan bahkan berpotensi berbahaya. Beberapa tindakan pada hakekatnya adalah jahat atau tidak; dan tidak adanya niat baik, tidak ada kesadaran yang menawarkan mereka kepada Allah, tidak ada penolakan dari buah dapat mengubah karakter dasar mereka. Ketidakpedulian Kudus membutuhkan untuk diajarkan dalam hubungannya tidak hanya dengan satu set perintah yang melarang kejahatan, tetapi juga dengan konsepsi yang jelas tentang apa yang di Delapan Jalan Buddha disebut sebagai “mata pencaharian yang benar.” Dengan demikian untuk Buddhis, penghidupan benar tidak sesuai dengan pembuatan senjata mematikan dan minuman keras; bagi orang Kristen abad pertengahan, dengan pengambilan bunga rente dan dengan berbagai praktek monopoli yang sejak datangnya dianggap sebagai bisnis yang sah baik. John Woolman, Quaker Amerika, memberikan contoh yang paling mencerahkan dari cara di mana seorang manusia bisa hidup di dunia, saat berlatih ketidak-melekatan (non-attachment) sempurna dan tersisa sangat sensitif terhadap klaim penghidupan yang benar. Jadi, meskipun itu akan menjadi menguntungkan dan sempurna halal baginya untuk melihat gula India Barat dan rum kepada pelanggan yang datang ke tokonya, Woolman menahan diri dari melakukannya, karena hal-hal ini adalah produk dari tenaga kerja budak. Demikian pula, ketika ia berada di Inggris, itu akan menjadi baik halal dan nyaman bagi dia untuk bepergian dengan pemanggul kursi/kereta. Namun demikian, ia lebih suka untuk membuat perjalanannya dengan berjalan kaki. Mengapa? Karena kenyamanan perjalanan cepat hanya bisa dibeli dengan mengorbankan kekejaman besar untuk kuda dan kondisi kerja yang paling mengerikan untuk anak laki-laki-pemanggul. Di mata Woolman itu, sistem transportasi seperti itu adalah intrinsik yang tidak diinginkan, dan tidak ada jumlah pribadi non-ikatan bisa membuat apa-apa, tapi tidak diinginkan. Jadi dia memanggul sendiri ranselnya dan berjalan.
Di halaman-halaman sebelumnya Huston Smith telah mencoba untuk menunjukkan bahwa Filsafat perennial/abadi dan prasyarat etika yang merupakan Faktor umum tertinggi, hadir dalam semua agama besar di dunia. Untuk menegaskan kebenaran ini tidak pernah lebih penting daripada imperatif pada saat ini. Tidak pernah akan ada perdamaian abadi kecuali dan sampai manusia datang untuk menerima filsafat hidup yang lebih memadai untuk fakta kosmik dan psikologis ini, daripada pemberhalaan gila terhadap iklan nasionalisme dan iman apokaliptik manusia dalam Kemajuan menuju Yerusalem Baru yang mekanik. Semua elemen dari filosofi ini hadir, seperti telah kita lihat, dalam agama-agama tradisional. Namun dalam situasi yang ada tidak ada kesempatan sedikit pun bahwa salah satu agama-agama tradisional akan memperoleh penerimaan universal. Orang Eropa dan Amerika akan melihat tidak ada alasan untuk diubah menjadi Hindu, misalnya, atau Buddhisme.
Dan orang-orang Asia tidak dapat diharapkan untuk meninggalkan tradisi mereka sendiri untuk tulus untuk mengaku Kristen, yang oleh kaum imperialis yang selama empat ratus tahun dan lebih, telah secara sistematis diserang, dieksploitasi, dan ditindas, dan sekarang berusaha untuk menyelesaikan penghentian karya perusakan oleh “upaya mendidik” mereka. Tapi bahagianya masih ada Faktor umum tertinggi dari semua agama dalam pandangan Filsafat Perennial yang selalu dan di mana-mana menjadi sistem metafisik para nabi, orang-orang suci/kudus dan orang bijak. Hal ini sangat mungkin bagi orang untuk tetap menjadi Kristen yang baik, Hindu, Budha, atau Muslim yang baik dan walau belum bersatu dalam perjanjian penuh pada ajaran-ajaran dasar Perennial Philosophy.
Bhagavad Gita mungkin adalah pernyataan kitab suci yang paling sistematis dari Filsafat perennial/abadi ke sebuah dunia saat perang, sebuah dunia yang, karena tidak memiliki prasyarat intelektual dan spiritual untuk perdamaian, hanya bisa berharap untuk menambal semacam gencatan senjata bersenjata yang genting, ia berdiri menunjuk, jelas dan jelas-jelas, satu-satunya jalan untuk melarikan diri dari kebutuhan diri dikenakan penghancuran diri. Untuk alasan ini kami harus berterima kasih kepada Swami Prabhavananda dan Mr. Isherwood karena telah memberi kita versi baru dari buku ini – versi yang dapat dibaca, tidak hanya tanpa rasa sakit kusamnya estetika yang diakibatkan oleh terlalu banyak terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Sansekerta, tapi secara positif dengan kenikmatan.
- Inti Mistik Tradisi Agama Besar
Enam agama besar telah membentuk peradaban utama yang ada saat ini: ketiga agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam) dan tiga agama Timur (Hindu, Buddha, dan Taoisme/ Konghucu). Agama-agama ini tampaknya cukup bertentangan satu sama lain ketika kita lihat dari luar, atau dari bentuk eksoteris mereka. Tidak hanya apakah mereka memiliki ritual, doa dan ajaran yang berbeda tetapi dalam banyak kasus doktrin mereka yang paling mendasar tentang sifat Realitas tampaknya bertentangan satu sama lain. Misalnya, Yudaisme menagatakan: “Jangan ada Allah lain selain Aku” tampaknya berdiri bertentangan secara langsung dengan penyembahan orang Hindu terhadap tiga juta dewa. Ketuhanan Tritunggal Kekristenan kontras tajam dengan Jalan Taoisme yang tak berbentuk, sementara prinsip utama Islam: “Tidak ada tuhan selain Allah”, muncul benar-benar bertentangan dengan desakan Buddhisme bahwa tidak ada Tuhan sama sekali. [73]
Jika kita menggali lebih dalam, bagaimanapun, kami menemukan dalam masing-masing tradisi agama itu, aspek batin atau esoteris, aliran ajaran yang diberikan oleh kaum mistik – orang pria dan wanita mereka yang mengklaim telah memiliki Realisasi langsung, atau Gnosis (Makrifat), dari Alam Realitas Mutlak. Apalagi jika kita membandingkan kesaksian mistik ini tentang Sifat Realitas ini, kami menemukan bahwa, meskipun ada pemisahan luas dalam waktu, tempat, bahasa, dan budaya, mereka sangat mirip – begitu banyak sehingga banyak sarjana telah datang untuk melihat mereka sebagai ajaran yang merupakan filsafat abadi tunggal yang, seperti beberapa bunga tak tertahankan, terus mekar lagi dan lagi dalam jiwa manusia.
Salah satu tujuan utama dari Pusat Ilmu Suci (Center for Sacred Sciences) adalah untuk melestarikan dan mempromosikan ajaran mistik ini dan untuk menunjukkan secara tepat apa yang mereka memiliki kesamaan. Di sini, misalnya, sembilan point disepakati oleh mistikus dari semua tradisi besar, bersama-sama dengan contoh kutipan yang menunjukkan Kesepakatan ini.
- Semua mistikus setuju bahwa Ultimate Reality (Realitas Mutlak) – apakah itu disebut Allah, Brahman, sifat-Buddha, En-Sof, Tuhan, atau Tao – tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia atau dinyatakan dalam kata-kata. (Bahkan, arti kata mistik berhubungan dengan kata bisu, yang keduanya berasal dari akar kata mustes Yunani, yang berarti “tutup-mulut.”)
“Tao yang dapat diberi nama bukanlah Tao yang sejati.” – Lao Tzu (Tao)
“Roh tertinggi adalah tak dapat diukur, tidak dapat dipahami, di luar konsepsi, tidak pernah dilahirkan, di luar penalaran, di luar pikiran.” – Upanishad (Hindu)
“Kata dan kalimat yang diproduksi oleh hukum sebab-akibat dan saling mengkondisikan – mereka tidak bisa mengungkapkan Realitas tertinggi.” – Lankavatara Sutra (Buddha)
“Salah satu yang yang melampaui semua pikiran, tidak dapat dibayangkan oleh semua pikiran.” – Dionysius, anggota majelis Areopagus (Kristen)
“Kaum Gnostik (Arifin) tahu, tapi apa yang mereka ketahui tidak bisa dikomunikasikan. Hal ini tidak dalam kuasa para pemilik maqom (kedudukan) paling menyenangkan ini … untuk membentuk kata yang akan menunjukkan apa yang mereka ketahui.” – Ibn ‘ Arabi ( Muslim )
- Alasan Realitas Mutlak tidak dapat ditangkap oleh pikiran atau dikomunikasikan dengan kata adalah bahwa pikiran dan kata-kata, menurut definisi, membuat perbedaan dan, karenanya, merupakan dualitas. Bahkan tindakan sederhana penamaan sesuatu menciptakan dualitas karena membedakan hal yang diberi nama dari semua hal lain yang tersisa, yang tidak disebutkan namanya. Namun, para mistikus dari semua tradisi besar setuju bahwa segala perbedaan adalah khayalan dan bahwa Alam Ultimate Reality adalah non-ganda.
“Pada dasarnya hal-hal, tidaklah dua tapi satu. Semua dualitas adalah yang secara palsu dibayangkan.” – Lankavatara Sutra (Buddha)
“Tidak peduli apa seorang manusia tertipu mungkin berpikir bahwa dia memahami, dia benar-benar melihat Brahman dan tidak lain selain Brahman. … Alam semesta ini, yang ditumpangkan pada Brahman, tidak lain hanyalah sebuah nama.” – Shankara (Hindu)
“Jika kita akan melihat hal-hal yang benar-benar, mereka adalah asing untuk kebaikan, kebenaran dan segala sesuatu yang mentolerir perbedaan apapun. Mereka adalah kawan karib dari Yang Satu, yang telanjang dari apapun keragaman dan perbedaan.” Meister Eckhart – (Kristen)
“Kesatuan yang ada, di sisi lain dari deskripsi dan keadaan. Tidak ada sesuatu tapi dualitas memasuki lapangan permainan kata-kata itu.” – Rumi (Muslim)
“Segala sesuatu yang Ada adalah sebagai Satu; Perbedaan antara “hidup” dan “mati”, “tanah” dan “laut”, telah kehilangan maknanya. – Master Hasid Anonim (Yahudi)
- 3. Meskipun mistik tidak dapat mendefinisikan Realitas Mutlak dalam kata-kata, mereka masih menggunakan kata-kata untuk menunjuk kepada Hal yang melampaui kata-kata. Misalnya, semua mistikus setuju bahwa, sementara Realitas Mutlak itu merupakan sifat sejati dari segala sesuatu, dalam dirinya sendiri Hal ini adalah bukan.
“Neti neti” (bukan ini, bukan itu) – Upanishad (Hindu)
“Kekosongan (shunyata) … adalah sifat utama dari segala sesuatu yang ada.” – Lama Yeshe (Buddha)
“Makhluk-makhluk segudang di dunia yang lahir dari sesuatu, dan sesuatu dari bukan apa-apa.” – Lao Tzu (Tao)
“Ini adalah dalam kecerdasan kita, jiwa dan tubuh, di surga, di bumi, dan sementara tetap sama dalam Dirinya sendiri, Hal ini sekaligus dalam, di sekitar dan di atas dunia, langit-super, esensi-super, sebuah matahari, bintang, api, air, semangat, embun, awan, batu, batu, semua itu adalah; semua hal ini bukanlah apa-apa. – Dionysius, anggota majelis Areopagus (Kristen)
“Dia tidak disertai dengan keapaan, kami juga tidak menganggap hal itu kepada-Nya. Negasi dari kekosongan dari-Nya merupakan salah satu sifat penting-Nya. – Ibn ‘Arabi (Muslim)
“Tuhan Allah yang tersembunyi, menjadi yang terdalam Being-Ketuhanan sehingga untuk membicarakan-NYA, kita tidak memiliki kualitas atau atribut. – Gerson Scholem (Yahudi)
- Meskipun mistik mengatakan Realitas Mutlak bukanlah suatu hal, mereka juga setuju bahwa kekosongan ini atau ke-bukan-apa-apa-an adalah vakum belaka. Hal ini bersinar dengan terang Roh Murni, Kesadaran Primordial, Pikiran Buddha, atau Kesadaran Diri
“Dia adalah Abadi di antara hal-hal yang berlalu, Kesadaran murni makhluk yang sadar.” – Upanishad (Hindu)
“Semua Buddha dan semua makhluk hidup tidak lain adalah Satu Pikiran, selainnya yang tidak ada.” Huang Po – (Buddha)
“Lampu di mana jiwa diterangi, agar dapat melihat dan benar-benar memahami segala sesuatu … adalah Tuhan Allah sendiri.” – St . Augustine (Kristen)
“Dia adalah roh kosmos, pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, serta tangan-Nya. Melalui Dia kosmos mendengar, melalui Dia itu melihat, melalui Dia itu berbicara, melalui Dia itu menggenggam, melalui Dia berjalan.” – Ibn ‘Arabi (Muslim)
“Pikiran ini berasal dari sumber yang luhur dan benar-benar bersatu di atas; itu terbagi hanya karena masuk ke dalam alam semesta perbedaan.” – Menahem Nahum (Yahudi)
- Kaum Mistik dari semua tradisi juga setuju bahwa ketika perbedaan yang diciptakan oleh imajinasi diambil untuk menjadi nyata – khususnya perbedaan antara ‘subyek’ dan ‘obyek‘ , ‘aku’ dan ‘lainnya’, ‘diri’ dan ‘dunia‘ – kita kehilangan pandangan Sifat Mutlak dari Realitas dan jatuh ke dalam delusi/khayalan. Ini adalah penyebab semua penderitaan kita.
“Disfungsi mendasar pikiran kita mengambil bentuk pemisahan antara saya dan yang lainnya. Kita secara palsu berpegang pada “Aku” yang merupakan lampiran cangkokan diri sendiri pada saat yang sama seperti yang kita pahami dari “yang lain” yang merupakan dasar dari penghindaran.” – Bokar Rinpoche (Buddha)
“Selama rasa “aku” dan “milikku” tetap ada, terikat menjadi kesedihan dan inginkan dalam kehidupan individu. – Anandamayi Ma (Hindu)
“Setiap orang memiliki banyak alasan untuk kesedihan tapi dia sendiri memahami alasan universal yang mendalam bagi kesedihan yang dia alami.” –Cloud of Unknowing (Kristen)
“Selama Anda adalah ‘kamu’, Anda akan sengsara dan miskin.” – Javad Nurbaksh (Muslim)
“Bagaimana bisa setiap kapal (kendaraaan) yang terbatas berharap untuk mengandung Tuhan yang tak berujung? Oleh karena itu, melihat diri Anda sebagai bukan apa-apa; satu-satunya yang merasa bukan apa-apa dapat berisi kepenuhan Kehadiran.” – Menahem Nahum (Yahudi)
- 6. Fakta bahwa perbedaan pada akhirnya tidak berarti nyata, bahwa kita bukan diri yang benar-benar terpisah. Dalam Realitas, semua mistikus menyatakan, Alam Sejati kita adalah Tuhan Allah, Brahman, Buddha – Nature, Tao, atau Kesadaran itu
“Jati Diri kita yang Sangat adalah Buddha, dan terpisah dari alam ini tidak ada yang lain selain Buddha.” – Hui-Neng (Buddha)
“Setelah meninggalkan ke samping Hidup dan Kematian, sekarang ia benar-benar dengan Transmutasi universal.” – Kuo Hsiang (Tao)
“Allah adalah Diri sendiri Seseorang, nafas-nafas dari seseorang yang bernafas, kehidupan dari hidup seseorang, Atman.” – Anandamayi Ma (Hindu)
“Beberapa orang sederhana berpikir bahwa mereka akan melihat Tuhan Allah seolah-olah Dia sedang berdiri di sana dan mereka di sini. Hal ini tidak begitu. Tuhan dan saya, kita adalah satu.” Meister Eckhart – (Kristen)
“Engkau adalah Dia, tanpa salah satu dari keterbatasan ini. Kemudian jika kamu mengetahui keberadaan-Mu sendiri dengan demikian, maka engkau tahu Tuhan Allah; dan jika tidak, maka tidak.” – Ibn ‘Arabi (Muslim)
“Untuk saat ini ia tidak lagi dipisahkan dari Tuan Guru, dan lihatlah dia tuannya dan Gurunya dia.” – Abraham Abulafia (Yahudi)
- 7. Meskipun kebenaran identitas seseorang dengan Realitas Mutlak tidak dapat ditangkap oleh pikiran, semua mistikus bersaksi bahwa Hal ini dapat Direalisasikan/Diwujudkan atau Dikenali melalui Kebangkitan Makrifat/Gnostik (Pencerahan) yang olehnya – pikiran melewati berpikir sama sekali .
“Saatnya akan datang ketika pikiran Anda tiba-tiba akan berhenti seperti tikus tua yang menemukan dirinya di dalam cul-de-sac. Kemudian akan ada orang terjun ke hal yang tidak diketahui dengan teriakan, “Ah, ini!” – Yun Man – (Buddha)
“Ketika cermin dari pikiran saya menjadi jelas … saya melihat bahwa Tuhan Allah tidak lain dari pada saya dan pengetahuan non-dualistik ini benar-benar menghancurkan semua pikiran dari “kamu” dan “Saya”. Aku datang untuk mengetahui bahwa seluruh dunia ini tidak berbeda dari Tuhan Allah. – Lalleshwari (Hindu)
“Di sini, menyangkal semua bahwa pikiran dapat mengandungnya, dibungkus sepenuhnya dalam hal yang tak berwujud dan tak terlihat, ia milik sepenuhnya Dia yang kepadaNya, orang yang berada di luar segalanya. Di sini yang tidak diri sendiri maupun orang lain, seseorang sangat disatukan oleh ketidaktahuan yang tidak aktif sama sekali dari semua pengetahuan, dan tahu di luar pikiran dengan tak mengetahui apa-apa. – Dionysius, anggota majelis Areopagus (Kristen)
“Dia hanya melihat Tuhan sebagai apa yang ia lihat, mengamati pelihat untuk menjadi sama dengan yang terlihat. Ini cukup, dan Tuhan Allah adalah pemberi rahmat, Panduan.”- Ibn ‘Arabi (Muslim)
“Hal ini dengan turun ke kedalaman diri sendiri bahwa manusia mengembara melalui semua dimensi dunia; dalam dirinya sendiri ia mengangkat hambatan yang memisahkan satu lingkungan dari yang lain; dalam diri sendiri, akhirnya , ia melampaui batas-batas nalar dan pada akhir dari jalan, tanpa, seolah-olah, satu langkah di luar dirinya, ia menemukan bahwa Tuhan Allah adalah ‘semuanya’ dan ada ‘apa-apa kecuali dia’.” – Gerson Scholem (Yahudi)
- Semua mistikus setuju bahwa mewujudkan Identitas kita dengan Realitas Mutlak ini membawa kebebasan dari penderitaan dan kematian .
“Ketika seorang manusia mengenal Tuhan Allah, ia bebas: kesedihannya berakhir, dan kelahiran dan kematian tidak ada lagi.” – Upanishad (Hindu)
“Apa itu penderitaan? Apa itu kematian? Pada kenyataannya, mereka tidak memiliki eksistensi apapun. Mereka muncul dalam kerangka manifestasi yang dihasilkan oleh pikiran yang terbungkus dalam sebuah ilusi. … Dalam kekosongan pikiran, tidak ada kematian. Tidak ada yang meninggal. Tidak ada penderitaan dan tidak takut.” – Bokar Rinpoche (Buddha)
“Ketika penangkapan palsu dinegasikan … dari jantung hati yang tercerahkan, maka “kematian akan ditelan selamanya dan Allah akan menghapus air mata dari setiap wajah.” – Abraham Abulafia (Yahudi)
“Tiba-tiba saya menyadari … ” itu benar-benar seperti ini, pada kenyataannya tidak ada satu hal! ” Dengan pikiran tunggal ini, semua belitan yang rusak. Tiba-tiba, seolah-olah beban seratus pound jatuh ke tanah dalam sekejap. Seolah-olah kilat telah menembus tubuh dan menembus kecerdasan.”- Kao – P’an – Lung (Konghucu)
“Manusia ini tinggal di satu Cahaya dengan Allah, dan karena itu tidak ada dalam dirinya baik penderitaan atau berlalunya waktu, tapi keabadian yang tak berubah.” Meister Eckhart – (Kristen)
“Aku telah diselamatkan dari ego dan kehendak-diri, hidup atau mati, apa penderitaan! Tapi hidup atau mati, saya tidak punya tanah air selain Karunia Allah.” – Rumi (Muslim)
- 9. Akhirnya, mistikus dari semua tradisi setuju bahwa ajaran mereka tentang Sifat Realitas Mutlak tidak harus diambil pada keimanan itu sendiri. Sama seperti teori-teori ilmiah yang dapat diverifikasi oleh siapa saja yang bersedia untuk melakukan eksperimen yang tepat, ajaran-ajaran mistis dapat diverifikasi oleh siapa saja yang bersedia untuk terlibat dalam praktek-praktek spiritual yang tepat dan disiplin. (Ini, kebetulan, adalah mengapa kita di Pusat percaya ajaran dan praktik mistis yang dikatakan benar merupakan ilmu pengetahuan yang kudus.)
“Mereka yang mempraktekkan tahu apakah realisasi dapat dicapai atau tidak, sama seperti mereka yang minum air tahu apakah itu panas atau dingin.“ – Dogen (Buddha)
“Kebenaran murni Atma , yang terkubur di bawah dunia Maya dan efek Maya, dapat dicapai dengan meditasi, kontemplasi dan disiplin spiritual lainnya seperti orang berpengetahuan Brahman mungkin meresepkan.” – Shankara (Hindu)
“Jika Anda tidak mencuci batu dan pasir, bagaimana Anda dapat memilih emas? Turunkan kepala dan masuklah ke dalam lubang terbuka membosankan yang non-reifikasi, hati-hati mencari jantung langit dan bumi dengan tekad kuat. Tiba-tiba, Anda akan melihat hal yang asli!” – Liu I- ming (Tao)
“Para patriarkh membuka saluran pikiran di dunia, mengajarkan semua orang yang datang ke dunia bagaimana menggali dalam diri mereka musim semi air kehidupan, untuk bersatu dengan sumber mereka, akar kehidupan mereka.” – Menahem Nahum (Yahudi)
“Jalan orang sufi adalah cara dari gnosis (Irfan) yang tepat dari Tuhan Allah, dan pengetahuan tentang cara-cara beragam pelatihan diri yang diperlukan untuk Arif bi Allah (Mengenal Allah)” – ‘Abd al-Wahab Sya’rani (Muslim)
“Jika Anda mengikuti ajaran saya, maka Anda benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan datang ke sebuah Makrifat (Gnosis) dari kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.” – Yesus dari Nazaret (Kristen)
- Apakah Fisika Quantum dan Spiritualitas terkait ?
Sangatlah berharga untuk mendiskusikan pertanyaan tentang fisika kuantum dan spiritualitas bersama-sama, untuk melihat hubungan antara mereka dari sudut pandang Gereja Baru dan juga dari perspektif Filsafat Islam Nusantara. Ada alasan mendesak untuk mendiskusikan link ini, karena ada orang yang ingin mengidentifikasi hal-hal ini. Ada perasaan yang meluas bahwa entah bagaimana mereka terhubung, tetapi di beberapa ‘zaman baru’ orang ingin mengatakan bahwa fisika kuantum mengatakan pada kita tentang spiritualitas. Kita tahu dari Swedenborg Scientific Association bahwa ada sambungan yang tidak begitu sederhana, jadi kita perlu memahami lebih terinci apa yang sedang terjadi.
D. Peran Pikiran
Semua filsuf Muslim percaya bahwa di atas indra ada jiwa rasional. Ini memiliki dua bagian: intelek praktis dan teoritis. Intelek teoritis bertanggung jawab untuk pengetahuan; intelek keprihatinan praktis sendiri hanya dengan manajemen yang tepat dari tubuh melalui ketakutan hal tertentu sehingga dapat melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Semua filsuf Muslim utama, dimulai dengan al-Kindi, menulis risalah tentang sifat dan fungsi intelek teoritis, yang dapat disebut sebagai rumah pengetahuan.
Selain indra dan intelek teoritis, filsuf Muslim termasuk dalam diskusi mereka dari instrumen pengetahuan faktor ketiga. Mereka mengajarkan bahwa dunia ilahi berisi, antara lain, kecerdasan, yang terendah dari yang adalah apa yang al-Kindi menyebut Akal Pertama (al-‘Aql al-Awwal), lebih dikenal dalam filsafat bahasa Arab sebagai ‘agen intelek’ (al -‘aql al-fa’al), nama yang diberikan kepadanya oleh al-Farabi, or’the pemberi bentuk ‘(Wahib as-suwar). Mereka berpendapat bahwa dunia di sekitar kita diperlukan untuk pencapaian pengetahuan filosofis. Beberapa, seperti Ibnu Bajja, Ibnu Rusyd dan kadang-kadang Ibnu Sina, mengatakan bahwa universal dicampur dalam imajinasi yang telah berasal dari dunia luar melalui indera pada akhirnya dimurnikan sepenuhnya oleh cahaya intelek agen, dan kemudian tercermin ke intelek teoritis.
Al-Farabi dan pandangan umum Ibnu Sina, bagaimanapun, adalah bahwa ini universal membayangkan hanya menyiapkan akal teoritis untuk penerimaan universal dari intelek agen yang sudah berisi mereka. Ketika mengekspresikan pandangan ini, Ibnu Sina menyatakan bahwa itu bukan universal dalam imajinasi sendiri yang ditransmisikan ke intelek teoritis tapi bayangan mereka, yang dibuat ketika cahaya intelek agen ditumpahkan pada universal ini. Hal ini mirip, katanya, untuk bayangan obyek, yang tercermin pada mata ketika sinar matahari dilemparkan pada objek itu. Sedangkan cara di mana universal dalam imajinasi dapat mempersiapkan akal teoritis untuk pengetahuan pada umumnya tidak jelas, itu samar-samar berkomentar oleh al-Farabi dan Ibnu Sina bahwa persiapan ini adalah karena kesamaan universal ini ke universal murni, dan untuk keakraban intelek teoritis dengan universal dibayangkan karena kedekatannya dengan imajinasi. Dengan kata lain, keakraban intelek ini dengan apa yang menyerupai benda yang tepat mempersiapkan untuk itu. Penerimaan dari benda-benda ini dari intelek agen.
E. filosofis dan Pengetahuan Nabi
Cara kenabian adalah jauh lebih mudah dan sederhana path (lihat Prophecy). Tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk menerima universal ilahi yang diberikan; satu-satunya persyaratan tampaknya menjadi milik jiwa yang kuat mampu menerima mereka. Sedangkan cara filosofis bergerak dari imajinasi ke atas untuk intelek teoritis, cara kenabian mengambil jalur sebaliknya, dari intelek teoritis untuk imajinasi. Untuk alasan ini, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan tentang sifat dari hal-hal sendiri, sementara pengetahuan tentang nubuatan adalah pengetahuan tentang sifat dari hal-hal seperti terbungkus dalam simbol-simbol, bayangan imajinasi.
Kebenaran filosofis dan kenabian adalah sama, tetapi dicapai dan dinyatakan secara berbeda. Ibnu Tufail yang Hayy ibn Yaqzan adalah ilustrasi terbaik dari harmoni filsafat dan agama (lihat Ibnu Tufail). Yang disebut teori kebenaran ganda salah memandang dua jalur ini untuk pengetahuan sebagai dua jenis kebenaran, sehingga menghubungkan Ibnu Rusyd pandangan asing untuk filsafat Islam. Salah satu kontribusi paling penting dari filsafat Islam adalah upaya untuk mendamaikan filsafat Yunani dan Islam dengan menerima jalur filosofis dan kenabian sebagai mengarah ke kebenaran yang sama.
Filsuf Muslim setuju bahwa pengetahuan intelek teoritis melewati tahap. Bergerak dari potensi ke aktualitas dan dari aktualitas untuk refleksi pada kenyataannya, sehingga memberikan intelek teoritis nama masing-masing potensi kecerdasan, kecerdasan yang sebenarnya dan diperoleh intelek. Beberapa filsuf Muslim menjelaskan bahwa yang terakhir adalah yang disebut ‘diperoleh’ karena pengetahuan datang untuk itu dari luar, sehingga dapat dikatakan untuk memperolehnya. Intelek yang diperoleh adalah pencapaian manusia tertinggi, keadaan suci yang conjoins manusia dan alam ilahi oleh conjoining intelek teoritis dan agen.
Mengikuti jejak Alexander dari Aphrodisias, al-Farabi, Ibn Bajja dan Ibnu Rusyd percaya bahwa kecerdasan teoritis potensi oleh alam, dan karena itu hancur kecuali menggenggam benda abadi, universal penting, untuk diketahui dan berpengetahuan adalah satu . Ibnu Sina menolak pandangan bahwa kecerdasan teoritis potensi oleh alam. Dia berpendapat sebaliknya bahwa itu adalah kekal oleh alam karena kecuali itu, itu tidak dapat memahami benda-benda yang kekal. Baginya, kebahagiaan dicapai dengan menggenggam ini intelek tentang obyek kekal, untuk menggenggam seperti menyempurnakan jiwa. Filsuf Muslim yang percaya keabadian yang dicapai hanya melalui pengetahuan juga setuju dengan Ibnu Sina pengetahuan yang sempurna dan kesempurnaan adalah kebahagiaan.
F. Konsep Pengetahuan Islam[17]
Berbagai isu epistemologis telah dibahas dalam filsafat Islam dengan orientasi berbeda dari epistemologi Barat. Upaya saat ini sedang dilakukan untuk memahami isu-isu dasar epistemologis dalam hal orientasi itu.
Dengan pandangan ini, dilakukan usaha dalam makalah ini untuk menggambarkan nuansa yang berbeda dan konotasi dari ilm istilah ‘, yaitu, pengetahuan, dalam konteks Islam. Diharapkan upaya singkat ini akan berfungsi sebagai langkah untuk dasar masa depan untuk pembangunan kerangka kerja untuk teori Islam pengetahuan.
Dalam teori Islam pengetahuan, istilah yang digunakan untuk pengetahuan dalam bahasa Arab adalah ‘ilm, yang, seperti Rosenthal telah dibenarkan menunjukkan, memiliki konotasi yang lebih luas daripada sinonim dalam bahasa Inggris dan bahasa Barat lainnya. Pengetahuan di dunia Barat berarti informasi tentang sesuatu, ilahi atau ragawi, sedangkan ‘ilm adalah istilah yang mencakup semua meliputi teori, aksi dan pendidikan. Rosenthal, menyoroti pentingnya istilah ini dalam peradaban Islam dan Islam, mengatakan bahwa hal itu memberi mereka bentuk yang khas.
Dapat dikatakan bahwa Islam adalah jalan “pengetahuan.” Tidak ada agama atau ideologi lain telah begitu banyak menekankan pentingnya ‘ilm. Dalam Al Qur’an kata ‘alim telah terjadi di 140 tempat, sementara al-‘ilm di 27. Dalam semua, jumlah total ayat di mana’ ilm atau turunannya dan kata-kata terkait yang digunakan adalah 704. Hal ini penting untuk dicatat bahwa pena dan buku sangat penting untuk akuisisi pengetahuan. Wahyu Islam dimulai dengan kata iqra ‘(‘ baca! ‘Atau’ membaca! ‘).
Menurut Al-Qur’an, kelas pengajaran pertama untuk Adam dimulai segera setelah penciptaan dan Adam diajarkan ‘semua Nama’.
Allah adalah guru pertama dan panduan mutlak kemanusiaan. Pengetahuan ini tidak disampaikan untuk bahkan para malaikat. Dalam Ushul al-Kafi ada tradisi yang diriwayatkan oleh Imam Musa al-Kazim (‘a) bahwa’ ilm adalah tiga jenis: ayatun muhkamah (tanda-tanda yang tak terbantahkan dari Allah), faridatun ‘Adilah (hanya kewajiban) dan sunnah al-qa’ imah (didirikan tradisi Nabi [s]). Ini berarti bahwa ‘ilm, pencapaian yang wajib bagi semua umat Islam meliputi ilmu-ilmu teologi, filsafat, hukum, etika, politik dan kebijaksanaan disampaikan kepada umat oleh Nabi
‘Ilm adalah tiga jenis: informasi (sebagai lawan ketidaktahuan), hukum alam, dan pengetahuan dengan dugaan. Jenis pertama dan kedua pengetahuan dianggap berguna dan akuisisi mereka dibuat wajib. Adapun jenis ketiga, yang mengacu pada apa yang dikenal melalui dugaan dan dugaan, atau disertai dengan keraguan, kami akan mengambil yang menjadi pertimbangan nanti, karena dugaan atau keraguan kadang-kadang penting untuk pengetahuan sebagai sarana, tetapi bukan sebagai tujuan.
Dalam dunia Islam, gnosis (ma’rifah) dibedakan dari pengetahuan dalam arti perolehan informasi melalui proses logis. Dalam dunia non-Islam yang didominasi oleh tradisi Yunani, hikmah (kebijaksanaan) dianggap lebih tinggi dari pengetahuan. Tapi ilm dalam Islam ‘bukanlah pengetahuan belaka. Hal ini identik dengan gnosis (ma’rifah). Pengetahuan dianggap berasal dari dua sumber: ‘aql dan’ ilm huduri (dalam arti pengetahuan tanpa perantara dan langsung diperoleh melalui pengalaman mistik).
Hal ini penting untuk dicatat bahwa ada banyak penekanan pada pelaksanaan intelek dalam Al-Qur’an dan tradisi, terutama dalam hal ijtihad.
Latihan intelek (‘aql) adalah sangat penting dalam literatur Islam seluruh, yang memainkan peran penting dalam pengembangan semua jenis pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sebaliknya, di dunia Muslim. Pada abad kedua puluh, pemikir Muslim India, Iqbal di Rekonstruksi nya Agama Pemikiran dalam Islam, menunjukkan bahwa ijtihad adalah prinsip dinamis dalam tubuh Islam. Dia menyatakan bahwa banyak sebelum Francis Bacon prinsip induksi ilmiah ditekankan oleh Al-Qur’an, yang menyoroti pentingnya observasi dan eksperimen di tiba pada kesimpulan tertentu. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa fuqaha dan mufassirun Muslim memanfaatkan metode analisis linguistik dalam menafsirkan perintah Alquran dan sunnah Nabi (S). Al-Ghazalis Tahatut al-Falasifah mungkin risalah filosofis pertama yang memanfaatkan metode analisis linguistik untuk mengklarifikasi isu-isu filosofis tertentu.
Ada dibuat perbedaan antara hikmat (hikmah) dan pengetahuan dalam filsafat pra-Islam yang dikembangkan di bawah pengaruh pemikiran Yunani. Dalam Islam tidak ada perbedaan seperti itu. Mereka yang membuat perbedaan itu dipimpin Muslim berpikir ke arah Islami berpikir. Para filsuf seperti al-Kindi, al-Farabi dan Ibnu Sina dianggap hakims (filsuf) dan dalam kapasitas ini unggul ‘ulama’, dan fuqaha kesalahpahaman ini mengakibatkan serangan al-Ghazali pada filsuf. Islam adalah agama yang mengajak pengikutnya untuk latihan kecerdasan mereka dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mencapai kebenaran hakiki (haqq). Pemikir Muslim mengadopsi jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Mereka yang disebut filsuf mengabdikan diri untuk logika dan metode ilmiah dan sufi derogated mereka, meskipun beberapa dari mereka, seperti Ibnu Sina, al-Farabi dan al-Ghazali mengambil jalan ke jalan mistik dalam pencarian mereka dari kebenaran pada tahap tertentu . ‘Ilm mungkin tidak diterjemahkan sebagai pengetahuan belaka; harus ditekankan bahwa itu adalah juga gnosis atau ma’rifah. Satu mungkin menemukan unsur-unsur pengalaman mistik dalam tulisan-tulisan filsuf Muslim. Dalam tradisi filsafat Barat ada perbedaan antara pengetahuan tentang Ilahi dan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia fisik. Tapi dalam Islam tidak ada perbedaan seperti itu. Ma’rifah adalah pengetahuan utama dan muncul dari pengetahuan tentang diri (Man ‘arafa nafsahu fa qad’ arafa Rabbbahu, ‘Satu yang menyadari diri seseorang sendiri menyadari Tuhannya’). Proses ini juga mencakup pengetahuan tentang dunia fenomenal. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan pengetahuan, yang dianggap sebagai dua hal yang berbeda di dunia non-Muslim, adalah satu dan sama dalam perspektif Islam.
Dalam diskusi pengetahuan, pertanyaan penting muncul adalah bagaimana seseorang dapat mengatasi keraguannya mengenai doktrin tertentu tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Hal ini umumnya percaya bahwa dalam Islam, sejauh keyakinan yang bersangkutan, tidak ada tempat untuk meragukan dan mempertanyakan keberadaan Tuhan, kenabian Muhammad dan perintah Ilahi, bahwa Islam mengharuskan pengajuan tegas untuk perintah nya. Kepercayaan umum ini adalah kesalahpahaman dalam terang penekanan Islam pada ‘aql.
‘Ilm disebut dalam banyak ayat-ayat Alquran sebagai’ cahaya ‘(nur), dan Allah juga digambarkan sebagai nur utama. Ini berarti bahwa ‘ilm dalam pengertian umum adalah identik dengan’ cahaya ‘dari Allah. Lampu ini tidak bersinar selamanya untuk semua orang percaya. Jika kadang-kadang tersembunyi oleh awan keraguan yang timbul dari pikiran manusia. Keraguan kadang-kadang ditafsirkan dalam Quran sebagai kegelapan, dan kebodohan juga digambarkan sebagai kegelapan di sejumlah ayat nya. Allah digambarkan sebagai nur, dan pengetahuan juga dilambangkan sebagai nur. Ketidaktahuan adalah kegelapan dan ma’rifah ringan. Dalam ayat al-kursi Allah berfirman: (Allah adalah Terang langit dan bumi …
Allah adalah Master orang percaya dan Dia menuntun mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya). Biasanya kegelapan ditafsirkan sebagai ketidakpercayaan dan ringan seperti iman kepada Allah. Ada begitu banyak orang-orang yang berjuang melawan kegelapan bisa mencapai ayat dalam Al-Quran serta tradisi para nabi yang menekankan cahaya itu.
Dalam ilm Islam ‘tidak terbatas pada perolehan pengetahuan saja, tetapi juga mencakup aspek sosial-politik dan moral. Pengetahuan tidak sekedar informasi; membutuhkan orang-orang percaya untuk bertindak atas keyakinan mereka dan berkomitmen untuk tujuan, yang bertujuan Islam di Mencapai.
Islam tidak pernah menyatakan bahwa hanya teologi berguna dan ilmu-ilmu empiris tidak berguna atau berbahaya. Konsep ini dibuat bersama oleh ulama semi-melek huruf, atau oleh timeservers di antara mereka yang ingin menjaga Muslim umum di kegelapan kebodohan dan iman buta sehingga mereka tidak akan mampu menentang penguasa yang tidak adil dan menolak ulama melekat pada pengadilan tiran . Sikap ini mengakibatkan kecaman tidak hanya ilmu pengetahuan empiris tetapi juga ‘ilm al-kalam dan metafisika, yang mengakibatkan penurunan Muslim dalam politik dan ekonomi. Bahkan saat ini segmen besar masyarakat Muslim, baik orang biasa dan banyak ulama menderita penyakit ini. Sikap yang tidak sehat dan anti-pengetahuan ini melahirkan beberapa gerakan, yang dianggap buku SD teologi sebagai cukup untuk seorang Muslim, dan berkecil asimilasi atau penyebaran pengetahuan empiris sebagai mengarah ke melemahnya iman.
Setelah penurunan penyelidikan filosofis dan ilmiah di timur Muslim, filsafat dan ilmu berkembang di Muslim barat karena usaha dari para pemikir asal Arab seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajja, dan Ibn Khaldun, bapak sosiologi dan filsafat sejarah. Filsafat Ibn Khaldun dari sejarah dan masyarakat adalah berbunga karya awal oleh para pemikir Muslim di bidang etika dan ilmu politik seperti yang dari Miskawaih, al-Dawwani, dan Nasir al-Din al-Tusi. Kredit untuk memberikan perhatian serius untuk filsafat sosial-politik pergi ke al-Farabi, yang menulis buku tentang masalah ini di bawah judul Madinat al-Fadilah, Ara ‘ahl al-Madinat al-Fadilah, al-Millah al-Fadilah, Fusul al-Madang, Sirah Fadilah, K. al-Siyasah al-Madaniyyah, dll
Muslim tidak pernah mengabaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial-politik lainnya yang berkaitan dengan fisik serta realitas sosial. Mereka memberikan kontribusi kaya untuk peradaban manusia dan dianggap oleh penyelidikan berani dan bebas mereka di berbagai bidang pengetahuan bahkan dengan risiko yang dikutuk sebagai bidat atau lebih tepatnya orang-orang kafir. Percaya sejati dan teguh dalam keyakinan Islam, seperti al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibnu Bajja, al-Haytham, Ibn ‘Arabi dan Mulla Sadra, dan dalam beberapa kali Sayyid Ahmad Khan, Iqbal dan al-Maududi pun tak luput fatwa kufur oleh partisan imitasi buta yang memusuhi prinsip ijtihad, penelitian dan pemikiran kritis.
Seiring dengan astronom, matematikawan, ilmuwan alam Muslim dan dokter seperti Ibnu Sina, Zakariyya al-Razi, dan lain-lain yang berperan dalam pengembangan pengetahuan dan peradaban manusia, itu akan menjadi tidak adil untuk tidak menyebutkan kontribusi yang signifikan dari Ikhwan al-Safa (Majelis Purity) sekelompok ulama Syi’ah Ismailiyah-dan pemikir yang menulis risalah asli pada berbagai mata pelajaran filosofis dan ilmiah, upaya yang menandakan upaya pertama untuk mengkompilasi sebuah ensiklopedi dalam
Singkatnya, mungkin dibenarkan mengklaim bahwa teori Islam pengetahuan bertanggung jawab untuk mekar dari budaya penyelidikan bebas dan berpikir ilmiah rasional yang juga mencakup lingkup teori dan praktek.
G. Epistemologi di Pikiran Islam
Meskipun ada anggapan bahwa filsafat Islam adalah perluasan dari filsafat Yunani, [18] sejarah menunjukkan bahwa hanya karena rantai yang menghubungkan dunia Islam dengan Yunani melalui asimilasi antara budaya. Karya filsuf Muslim seperti al-Kindi (d 260 H / 873), al-Farabi (d 339 H / 950), Ibnu Sina (d 428 H / 1037), al-Ghazali (d 505 H / 1111), dan Ibn Rusyd (d 595 H / 1198).
Filsafat kenabian, adalah merek dagang dari filsafat Islam yang tidak dapat ditemukan dalam karya-karya Yunani itu. Salah satu buku Ibnu Bajja (d 533 H / 1138 M) dan Ibnu Tufail (d 581 H / 1185 M) “Hayy bin Yaqzhan” asli. Pada sudut pandang ini, al-Qur’an membawa doktrin benar-benar baru untuk mengamati Tuhan dan alam semesta, juga hukum yang belum diperkenalkan oleh filsafat Yunani.
Dalam Al-Qur’an dan hadits, ada banyak ayat yang berkaitan dengan pengetahuan, baik pentingnya atau keterbatasan pengetahuan serta. [19] Pertanyaan apakah filsafat dan wahyu bisa dihubungkan bersama adalah karya besar dari filsuf Muslim seperti al Kindi . Filsuf lain Ibn Rusyd dalam bukunya “Fashl al-Maqal” (Treatise Tegas) menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat (hikmah) dan agama. [20]
Setelah berabad-abad dari menurunnya minat dalam pengetahuan rasional dan ilmiah, filsuf Gramedia Ibn Rusyd dan filsuf Islam lainnya dari bergerak membantu untuk mengembalikan kepercayaan di akal dan pengalaman, pencampuran metode rasional dengan iman ke dalam sistem terpadu keyakinan. Ibn Rusyd diikuti Aristoteles dalam mengenai persepsi sebagai titik awal dan logika sebagai prosedur intelektual untuk sampai pada pengetahuan yang dapat diandalkan alam, tapi ia menganggap iman dalam otoritas kitab suci sebagai sumber utama keyakinan agama.
IV. Ilmu dalam filsafat Islam [21]
Islam mencoba untuk mensintesis akal dan wahyu, pengetahuan dan nilai-nilai, dalam pendekatan untuk mempelajari alam. Pengetahuan yang diperoleh melalui upaya manusia yang rasional dan melalui Al-Qur’an dipandang sebagai pelengkap: keduanya ‘tanda-tanda Allah’ yang memungkinkan manusia untuk mempelajari dan memahami alam. Antara abad kedua dan kedelapan AH (abad kedelapan dan kelima belas AD), ketika peradaban Islam berada di puncaknya, metafisika, epistemologi dan studi empiris alam menyatu untuk menghasilkan ledakan of’scientific semangat ‘. Para ilmuwan dan ulama seperti Ibn al-Haytham, al-Razi, Ibnu Tufail, Ibnu Sina dan al-Biruni ditumpangkan ide Plato dan Aristoteles akal dan objektivitas iman Islam mereka sendiri, sehingga menghasilkan sebuah sintesis yang unik dari agama dan filsafat. Mereka juga menempatkan penekanan besar pada metodologi ilmiah, memberikan pentingnya pengamatan sistematis, eksperimen dan membangun teori.
Awalnya, penyelidikan ilmiah ini disutradarai oleh praktek sehari-hari Islam. Misalnya, perkembangan astronomi dipengaruhi oleh fakta bahwa waktu salat Muslim didefinisikan astronomis dan arahnya didefinisikan secara geografis. Pada tahap selanjutnya, pencarian kebenaran untuk kepentingan diri sendiri menjadi norma, yang menyebabkan banyak penemuan-penemuan baru dan inovasi. Ilmuwan Muslim tidak mengakui batas-batas disiplin antara ‘dua budaya’ ilmu pengetahuan dan humaniora, dan sarjana individu cenderung sebagai aturan umum menjadi polymaths. Baru-baru ini, para sarjana Muslim telah mulai mengembangkan filsafat Islam kontemporer ilmu dengan menggabungkan konsep-konsep dasar Islam seperti ‘ilm (pengetahuan), khilafah (perwalian alam) dan istisla (kepentingan umum) dalam kerangka kebijakan ilmu pengetahuan yang terintegrasi.
A. Ilmu dan metafisika
Inspirasi Muslim untuk studi alam datang langsung dari Al-Qur’an. Al-Qur’an secara khusus dan berulang kali meminta umat Islam untuk menyelidiki fenomena alam secara sistematis, tidak hanya sebagai kendaraan untuk uunderstanding alam tetapi juga sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Dalam Surah 10, misalnya, kita membaca:
“Dia itu yang telah membuat matahari cahaya bersinar dan bulan cahaya [tercermin], dan telah ditentukan untuk itu fase sehingga Anda mungkin tahu bagaimana menghitung tahun dan untuk mengukur [waktu] … di alternatif malam dan siang , dan dalam semua bahwa Allah telah menciptakan di langit dan di bumi, ada pesan memang untuk orang-orang yang bertakwa “(QS 10: 5-6).
Al-Qur’an juga mencurahkan sekitar sepertiga dari ayat-ayat untuk menggambarkan kebajikan alasan. Penyelidikan ilmiah, berdasarkan alasan, dengan demikian terlihat dalam Islam sebagai bentuk ibadah. Akal dan wahyu adalah metode komplementer dan terintegrasi untuk mengejar kebenaran.
Filsafat ilmu dalam Islam klasik adalah produk dari fusi metafisika ini dengan filsafat Yunani. Tempat ini lebih jelas daripada dalam teori Ibnu Sina pengetahuan manusia (lihat Ibnu Sina) yang, berikut al-Farabi, transfer skema Qur’an wahyu untuk filsafat Yunani. Dalam Al Qur’an, Sang Pencipta alamat satu orang – Nabi – melalui agen malaikat Gabriel; di Ibnu Sina skema Neo-Platonisme, kata ilahi ditularkan melalui akal dan pemahaman untuk apapun, dan setiap, orang yang peduli untuk mendengarkan. Hasilnya adalah campuran dari rasionalisme dan etika. Untuk sarjana dan ilmuwan Muslim, nilai-nilai yang obyektif dan baik dan jahat adalah karakteristik deskriptif dari realitas yang tidak kalah ‘ada’ dalam hal-hal daripada kualitas mereka yang lain, seperti bentuk dan ukuran. Dalam kerangka ini, semua pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang Allah, dapat diperoleh dengan alasan saja. Kemanusiaan memiliki kekuatan untuk mengetahui serta bertindak dan dengan demikian bertanggung jawab untuk hanya dan tidak adil tindakan. Apa filosofi ini mensyaratkan baik dari segi studi alam dan membentuk perilaku manusia digambarkan oleh Ibnu Tufail dalam novel intelektualnya, Hayy ibn Yaqzan. Hayy adalah manusia yang terjadi secara spontan yang terisolasi di sebuah pulau. Melalui kekuasaannya dari pengamatan dan penggunaan kecerdasan, Hayy menemukan fakta umum dan khusus tentang struktur material dan spiritual alam semesta, menyimpulkan keberadaan Tuhan dan tiba di sistem teologis dan politik (lihat Epistemologi dalam filsafat Islam; Etika dalam filsafat Islam).
Sementara Mu’tazilah ulama memiliki perbedaan filosofis serius dengan lawan utama mereka, para teolog Asy’ariyah, kedua sekolah menyetujui studi rasional alam. Dalam bukunya al-Tamhid, Abu Bakr al-Baqillani mendefinisikan ilmu sebagai ‘pengetahuan dari objek, karena benar-benar’. Sementara bereaksi terhadap pelanggaran Mu’tazilah pada domain iman, kaum Asy’ariyah mengakui perlunya studi obyektif dan sistematis alam. Memang, beberapa ilmuwan terbesar dalam Islam, seperti Ibn al-Haytham (d. 1039), yang menemukan hukum dasar optik, dan al-Biruni (d. 1048), yang diukur lingkar bumi dan membahas rotasi bumi pada porosnya, adalah pendukung teologi Asy’ariyah (lihat Ash’ariyya dan Mu’tazilah).
Perhatian keseluruhan ilmuwan Muslim adalah penggambaran kebenaran. Ibn al-Haytham menyatakan, ‘kebenaran dicari untuk kepentingan diri sendiri’, dan al-Biruni dikonfirmasi dalam pengantar nya al-Qanun al-Mas’udi: ‘. Saya tidak menghindari kebenaran dari sumber apa pun datang’ Namun, ada perselisihan tentang cara terbaik untuk kebenaran rasional. Untuk Ibnu Sina, pertanyaan umum dan universal datang pertama dan menyebabkan pekerjaan eksperimental. Dia mulai nya al-Qanun fi’l-tibb (Kanon Kedokteran), yang merupakan teks standar di Barat sampai abad kedelapan belas, dengan diskusi umum tentang teori obat. Untuk al-Biruni, bagaimanapun, universal keluar dari praktis, karya eksperimental; teori yang dirumuskan setelah penemuan. Namun demikian baik, kritik adalah kunci untuk kemajuan menuju kebenaran. Ibn al-Haytham menulis, ‘adalah wajar untuk semua orang menganggap ilmuwan menguntungkan …. Namun, Allah tidak diawetkan ilmuwan dari kesalahan dan tidak dijaga ilmu dari kekurangan dan kesalahan ‘(lihat Sabra 1972). Inilah sebabnya mengapa para ilmuwan begitu sering tidak setuju di antara mereka sendiri. Mereka yang peduli dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran, Ibn al-Haytham melanjutkan, ‘harus mengubah diri menjadi kritikus bermusuhan’ dan harus mengkritik ‘dari setiap sudut pandang dan dalam semua aspek’. Secara khusus, kekurangan dalam karya pendahulu seseorang harus kejam terkena akan. Ide-ide Ibn al-Haytham, al-Biruni dan Ibnu Sina, bersama dengan banyak ilmuwan Muslim lainnya, meletakkan dasar-dasar dari ‘semangat ilmiah’ seperti yang kita telah datang untuk tahu itu.
B. Metodologi
‘Metode ilmiah’ (lihat metode ilmiah), seperti yang dipahami saat ini, pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Pendukung kedua Mu’tazilism dan Ash’arism menempatkan banyak penekanan pada pengamatan sistematis dan eksperimen. Desakan pada pengamatan akurat berlimpah ditunjukkan dalam zij, literatur buku pegangan astronomi dan meja. Tersebut terus diperbarui, dengan para ilmuwan memeriksa dan mengoreksi karya ulama sebelumnya. Dalam pengobatan, pengamatan klinis rinci dan sangat akurat Abu Bakar Muhammad al-Razi pada awal abad ketiga AH (abad kesembilan AD) memberikan kami dengan model universal. Al-Razi adalah orang pertama yang mengamati secara akurat gejala cacar dan dijelaskan banyak sindrom ‘baru’. Namun, itu tidak hanya pengamatan akurat yang penting; sama-sama signifikan adalah kejelasan dan presisi dimana pengamatan dijelaskan, seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Sina dalam tulisan-tulisannya.
Penekanan pada konstruksi model dan bangunan teori dapat dilihat dalam kategori sastra astronomi Islam dikenal sebagai ‘ilm al-haya, atau’ ilmu struktur (alam semesta) ‘, yang terdiri dari eksposisi umum prinsip-prinsip yang mendasari teori astronomi. Itu pada kekuatan dari kedua akurat observasi dan model pembangunan yang astronomi Islam melancarkan serangan ketat pada apa yang dianggap satu set ketidaksempurnaan di Ptolemaic astronomi (lihat Ptolemy). Ibn al-Haytham adalah orang pertama yang menyatakan dengan tegas bahwa pengaturan yang diusulkan untuk gerakan planet di Almagest yang ‘palsu’. Ibnu Shatir (d. 1375) dan astronom di observatorium terkenal di Maragha, Adharbayjan, dibangun pada abad ketiga belas oleh Nasir al-Din al-Tusi, mengembangkan beberapa Tusi dan teorema untuk transformasi model eksentrik menjadi yang epicyclic. Itu model matematis ini bahwa Copernicus digunakan untuk mengembangkan gagasan tentang heliosentris, yang memainkan peran penting dalam Eropa ‘revolusi ilmiah’.
Terlepas dari ilmu-ilmu eksakta, daerah yang paling tepat dan menarik di mana pekerjaan teoritis memainkan peran penting adalah obat. Dokter Muslim berusaha untuk meningkatkan kualitas materia medica dan penggunaan terapi mereka melalui pengembangan teori terus. Penekanan juga ditempatkan pada pengembangan terminologi yang tepat dan memastikan kemurnian obat, perhatian yang menyebabkan sejumlah bahan kimia awal dan prosedur fisik. Sejak penulis Muslim penyelenggara baik pengetahuan, teks murni farmakologi mereka sendiri sumber untuk pengembangan teori. Evolusi teori dan penemuan obat baru terkait pertumbuhan kedokteran Islam untuk kimia, botani, zoologi, geologi dan hukum, dan menyebabkan elaborasi luas klasifikasi Yunani. Pengetahuan farmakologi sehingga menjadi lebih beragam, dan menghasilkan jenis baru sastra farmakologis. Sebagai sastra ini dianggap subjek dari sejumlah perspektif disiplin ilmu yang berbeda dan berbagai macam arah baru, ada mengembangkan cara baru dalam memandang farmakologi; daerah baru dibuka untuk eksplorasi lebih lanjut dan penyelidikan lebih rinci. Pembuatan kertas membuat publikasi yang lebih luas dan lebih murah daripada menggunakan perkamen dan papirus, dan ini pada gilirannya membuat pengetahuan ilmiah jauh lebih mudah diakses oleh siswa.
Sementara para ilmuwan Muslim ditempatkan iman yang cukup besar dalam metode ilmiah, mereka juga menyadari keterbatasan. Bahkan sangat percaya pada realisme matematika seperti al-Biruni berpendapat bahwa metode penyelidikan adalah fungsi dari sifat investigasi: metode yang berbeda, semua sama-sama valid, diminta untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan. Al-Biruni sendiri memiliki jalan lain untuk sejumlah metode. Dalam risalahnya tentang mineralogi, Kitab al-Jamahir (Kitab Batu Mulia), dia adalah yang paling tepat dari ilmuwan eksperimental. Namun, dalam pengantar studi tanah-melanggar nya India ia menyatakan bahwa ‘untuk melaksanakan proyek kami, belum memungkinkan untuk mengikuti metode geometrik’; Oleh karena itu ia resort untuk sosiologi komparatif.
Karya seorang sarjana dari kaliber dan perkembang-biakan al-Biruni pasti menentang klasifikasi sederhana. Menurut dia, pada mineralogi, geografi, kedokteran, astrologi dan berbagai macam topik yang berurusan dengan kencan festival Islam. Al-Biruni adalah produk tertentu dari filsafat ilmu yang mengintegrasikan metafisika dengan fisika, tidak atribut baik posisi superior atau inferior, dan menegaskan bahwa keduanya layak studi dan sama-sama valid. Selain itu, metode belajar penciptaan besar Allah – dari pergerakan bintang-bintang dan planet-planet dengan sifat penyakit, sengatan semut, karakter kegilaan, keindahan keadilan, kerinduan spiritual manusia, ekstasi dari mistik – semua sama-sama valid dan bentuk pemahaman di daerah masing-masing penyelidikan. Dalam kedua filosofi dan metodologi, Islam telah berupaya sintesis lengkap ilmu pengetahuan dan agama.
Polymaths seperti al-Biruni, al-Jahiz, al-Kindi, Abu Bakar Muhammad al-Razi, Ibnu Sina, al-Idrisi, Ibnu Bajja, Omar Khayyam, Ibnu Zuhr, Ibn Tufayl, Ibn Rusyd, al-Suyuti dan ribuan ulama lainnya tidak terkecuali tetapi aturan umum dalam peradaban Muslim. Peradaban Islam dari periode klasik adalah luar biasa untuk jumlah polymaths itu diproduksi. I
- Islamic Concept of Knowledge[17]
Various epistemological issues have been discussed in Muslim philosophy with an orientation different from that of Western epistemology. Today attempts are being made to understand the basic epistemological issues in terms of that orientation.
With this view, an attempt is made in this paper to delineate the different shades and connotations of the term ‘ilm, i.e., knowledge, in the Islamic context. It is hoped that this brief attempt will serve as a step for future groundwork for the construction of a framework for an Islamic theory of knowledge.
In the Islamic theory of knowledge, the term used for knowledge in Arabic is ‘ilm, which, as Rosenthal has justifiably pointed out, has a much wider connotation than its synonyms in English and other Western languages. Knowledge in the Western world means information about something, divine or corporeal, while ‘ilm is an all-embracing term covering theory, action and education. Rosenthal, highlighting the importance of this term in Muslim civilization and Islam, says that it gives them a distinctive shape.
It may be said that Islam is the path of “knowledge.” No other religion or ideology has so much emphasized the importance of ‘ilm. In the Qur’an the word ‘alim has occurred in 140 places, while al-‘ilm in 27. In all, the total number of verses in which ‘ilm or its derivatives and associated words are used is 704. It is important to note that pen and book are essential to the acquisition of knowledge. The Islamic revelation started with the word iqra’ (‘read!’ or ‘recite!’).
According to the Qur’an, the first teaching class for Adam started soon after his creation and Adam was taught ‘all the Names’.
Allah is the first teacher and the absolute guide of humanity. This knowledge was not imparted to even the Angels. In Usul al-Kafi there is a tradition narrated by Imam Musa al-Kazim (‘a) that ‘ilm is of three types: ayatun muhkamah (irrefutable signs of God), faridatun ‘adilah (just obligations) and sunnat al-qa’imah (established traditions of the Prophet [s]). This implies that ‘ilm, attainment of which is obligatory upon all Muslims covers the sciences of theology, philosophy, law, ethics, politics and the wisdom imparted to the Ummah by the Prophets
‘Ilm is of three types: information (as opposed to ignorance), natural laws, and knowledge by conjecture. The first and second types of knowledge are considered useful and their acquisition is made obligatory. As for the third type, which refers to what is known through guesswork and conjecture, or is accompanied with doubt, we shall take that into consideration later, since conjecture or doubt are sometimes essential for knowledge as a means, but not as an end.
In the Islamic world, gnosis (ma’rifah) is differentiated from knowledge in the sense of acquisition of information through logical processes. In the non-Islamic world dominated by the Greek tradition, hikmah (wisdom) is considered higher than knowledge. But in Islam ‘ilm is not mere knowledge. It is synonymous with gnosis (ma’rifah). Knowledge is considered to be derived from two sources: ‘aql and ‘ilm huduri (in the sense of unmediated and direct knowledge acquired through mystic experience).
It is important to note that there is much emphasis on the exercise of the intellect in the Qur’an and the traditions, particularly in the matter of ijtihad.
Exercise of the intellect (‘aql) is of significance in the entire Islamic literature, which played an important role in the development of all kinds of knowledge, scientific or otherwise, in the Muslim world. In the twentieth century, the Indian Muslim thinker, Iqbal in his Reconstruction of Religious Thought in Islam, pointed out that ijtihad was a dynamic principle in the body of Islam. He claims that much before Francis Bacon the principles of scientific induction were emphasized by the Qur’an, which highlights the importance of observation and experimentation in arriving at certain conclusions. It may also be pointed out that Muslim fuqaha and mufassirun made use of the method of linguistic analysis in interpreting the Quranic injunctions and the sunnah of the Prophet (S). Al-Ghazalis Tahatut al-Falasifah is probably the first philosophical treatise that made use of the linguistic analytical method to clarify certain philosophical issues.
There was made a distinction between wisdom (hikmah) and knowledge in the pre-Islamic philosophy developed under the influence of Greek thought. In Islam there is no such distinction. Those who made such a distinction led Muslim thought towards un-Islamic thinking. The philosophers such as al-Kindi, al–Farabi and Ibn Sina are considered to be hakims (philosophers) and in this capacity superior to ‘ulama‘, and fuqaha this misconception resulted in al-Ghazali’s attack on the philosophers. Islam is a religion that invites its followers to exercise their intellect and make use of their knowledge to attain the ultimate truth (haqq). Muslim thinkers adopted different paths to attain this goal. Those who are called philosophers devoted themselves to logic and scientific method and the Sufis derogated them, though some of them, such as Ibn Sina, al–Farabi and al-Ghazali took recourse to the mystic path in their quest of the truth at some stage. ‘Ilm may not be translated as mere knowledge; it should be emphasized that it is also gnosis or ma’rifah. One may find elements of mystic experience in the writings of Muslim philosophers. In the Western philosophical tradition there is a distinction between the knowledge of the Divine Being and knowledge pertaining to the physical world. But in Islam there is no such distinction. Ma’rifah is ultimate knowledge and it springs from the knowledge of the self (Man ‘arafa nafsahu fa qad ‘arafa Rabbbahu, ‘One who realizes one’s own self realizes his Lord’). This process also includes the knowledge of the phenomenal world. Therefore, wisdom and knowledge, which are regarded as two different things in the non-Muslim world, are one and the same in the Islamic perspective.
In the discussion of knowledge, an important question arises as to how one can overcome his doubts regarding certain doctrines about God, the universe, and man. It is generally believed that in Islam, as far as belief is concerned, there is no place for doubting and questioning the existence of God, the prophethood Muhammad and the Divine injunctions, that Islam requires unequivocal submission to its dictates. This general belief is a misconception in the light of Islam’s emphasis on ‘aql.
‘Ilm is referred to in many Quranic verses as ‘light’ (nur), and Allah is also described as the ultimate nur. It means that ‘ilm in the general sense is synonymous with the ‘light’ of Allah. This light does not shine forever for all the believers. If is hidden sometimes by the clouds of doubt arising from the human mind. Doubt is sometimes interpreted in the Quran as darkness, and ignorance also is depicted as darkness in a number of its verses. Allah is depicted as nur, and knowledge is also symbolized as nur. Ignorance is darkness and ma’rifah is light. In the ayat al-kursi Allah says: (Allah is the Light of the heavens and the earth … Allah is the Master of the believers and He guides them out of the darkness into light). Usually darkness is interpreted as unbelief and light as faith in God. There are so many those who struggle against darkness may attain verses in the Quran as well as the traditions of the Prophets that emphasize that light.
In Islam ‘ilm is not confined to the acquisition of knowledge only, but also embraces socio-political and moral aspects. Knowledge is not mere information; it requires the believers to act upon their beliefs and commit themselves to the goals, which Islam aims at attaining.
Islam never maintained that only theology was useful and the empirical sciences useless or harmful. This concept was made common by semi-literate clerics or by the timeservers among them who wanted to keep common Muslims in the darkness of ignorance and blind faith so that they would not be able to oppose unjust rulers and resist clerics attached to the courts of tyrants. This attitude resulted in the condemnation of not only empirical science but also ‘ilm al-kalam and metaphysics, which resulted in the decline of Muslims in politics and economy. Even today large segments of Muslim society, both the common man and many clerics suffer from this malady. This unhealthy and anti-knowledge attitude gave birth to some movements, which considered elementary books of theology as sufficient for a Muslim, and discouraged the assimilation or dissemination of empirical knowledge as leading to the weakening of faith.
After the decline of philosophical and scientific inquiry in the Muslim east, philosophy and sciences flourished in the Muslim west due to endeavours of the thinkers of Arab origin like Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Ibn Bajja, and Ibn Khaldun, the father of sociology and philosophy of history. Ibn Khaldun’s philosophy of history and society is the flowering of early work by Muslim thinkers in the spheres of ethics and political science such as those of Miskawayh, al-Dawwani, and Nasir al-Din al-Tusi. The credit for giving serious attention to socio–political philosophy goes to al-Farabi, who wrote books on these issues under the titles of Madinat al-Fadilah, Ara’ ahl al-Madinat al-Fadilah, al-Millah al-Fadilah, Fusul al-Madang, Sirah Fadilah, K. al-Siyasah al-Madaniyyah, etc.
Muslims never ignored socio-political economic and other problems pertaining to the physical as well as social reality. They contributed richly to human civilization and thought by their bold and free inquiry in various areas of knowledge even at the risk of being condemned as heretics or rather unbelievers. True and firm believers in Islamic creed, like al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Bajja, al-Haytham, Ibn ‘Arabi and Mulla Sadra, and in recent times Sayyid Ahmad Khan, Iqbal and al-Mawdudi were not spared fatwas of kufr by the partisans of blind imitation who were hostile to the principle of ijtihad, research and critical thought.
Along with the Muslim astronomers, mathematicians, natural scientists and physicians like Ibn Sina, Zakariyya al–Razi, and others who were instrumental in the development of human knowledge and civilization, it would be unjust not to mention the significant contribution of Ikhwan al–Safa (The Brethren Purity) a group of Shi’i-Ismaili scholars and thinkers who wrote original treatises on various philosophical and scientific subjects, an effort which signifies the first attempt to compile an encyclopaedia in the
In brief, it may be justifiably claimed that the Islamic theory of knowledge was responsible for blossoming of a culture of free inquiry and rational scientific thinking that also encompassed the spheres of both theory and practice.
- Epistemology in Islamic Thoughts
Although there is an assumption that Islamic philosophy is an extension of Greek philosophy,[18] history shows that it only because of the chains that link the Islamic world with the Greek through the assimilation between cultures. The masterpieces of Muslim philosophers such as al-Kindi (d 260 H/873), al-Farabi (d 339 H/950), Ibn Sina (d 428 H/1037), al-Ghazali (d 505 H/1111), and Ibn Rushd (d 595 H/1198).
Prophetic philosophy, is a trademark of Islamic philosophy that could not be found in the Greek’s works. One of the books of Ibn Bajja (d 533 H/1138 M) and Ibn Tufayl (d 581 H/1185 M) “Hayy bin Yaqzhan” is original. At this point of view, al-Qur’an brings absolutely new doctrines to observe God and the universe, also laws that had not been introduced by the Greek philosophy.
In Qur’an and hadith, there are many verses that related to knowledge, either the importance or the limitations of knowledge as well.[19] Questions whether philosophy and revelation could be linked together were the major works of Muslim philosophers such as al Kindi. The other philosopher Ibn Rushd in his book “Fashl al-Maqal” (Decisive Treatise) explained that there is no contradiction between philosophy (hikmah) and religion.[20]
After many centuries of declining interest in rational and scientific knowledge, the Scholastic philosopher Ibn Rushd and other Islamic philosophers of peripatetic helped to restore confidence in reason and experience, blending rational methods with faith into a unified system of beliefs. Ibn Rushd followed Aristotle in regarding perception as the starting point and logic as the intellectual procedure for arriving at reliable knowledge of nature, but he considered faith in scriptural authority as the main source of religious belief.
- Science in Islamic philosophy[21]
Islam attempts to synthesize reason and revelation, knowledge and values, in its approach to the study of nature. Knowledge acquired through rational human efforts and through the Qur’an are seen as complementary: both are ‘signs of God’ that enable humanity to study and understand nature. Between the second and eighth centuries AH (eighth and fifteenth centuries AD), when Muslim civilization was at its zenith, metaphysics, epistemology and empirical studies of nature fused to produce an explosion of‘scientific spirit’. Scientists and scholars such as Ibn al-Haytham, al-Razi, Ibn Tufayl, Ibn Sina and al-Biruni superimposed Plato’s and Aristotle’s ideas of reason and objectivity on their own Muslim faith, thus producing a unique synthesis of religion and philosophy. They also placed great emphasis on scientific methodology, giving importance to systematic observation, experimentation and theory building.
Initially, scientific inquiry was directed by everyday practices of Islam. For example, developments in astronomy were influenced by the fact that the times of Muslim prayer were defined astronomically and its direction was defined geographically. In the later stage, the quest for truth for its own sake became the norm, leading to numerous new discoveries and innovations. Muslim scientists did not recognize disciplinary boundaries between the ‘two cultures’ of science and humanities, and individual scholars tended as a general rule to be polymaths. Recently, Muslim scholars have started to develop a contemporary Islamic philosophy of science by combining such basic Islamic concepts as ‘ilm (knowledge), khilafa (trusteeship of nature) and istisla (public interest) in an integrated science policy framework.
- Science and metaphysics
The Muslim inspiration for the study of nature comes straight from the Qur’an. The Qur’an specifically and repeatedly asks Muslims to investigate systematically natural phenomena, not simply as a vehicle for uunderstanding nature but also as a means for getting close to God. In Surah 10, for example, we read:
“He it is who has made the sun a radiant light and the moon a light [reflected], and has determined for it phases so that you might know how to compute years and to measure [time]…in the alternative of night and day, and in all that God has created in the heavens and on earth, there are messages indeed for people who are conscious of Him.” (Surah 10: 5-6)
The Qur’an also devotes about one-third of its verses to describing the virtues of reason. Scientific inquiry, based on reason, is thus seen in Islam as a form of worship. Reason and revelation are complementary and integrated methods for the pursuit of truth.
The philosophy of science in classical Islam is a product of the fusion of this metaphysics with Greek philosophy. Nowhere is this more apparent than in Ibn Sina’s theory of human knowledge (see Ibn Sina) which, following al-Farabi, transfers the Qur’an scheme of revelation to Greek philosophy. In the Qur’an, the Creator addresses one man – the Prophet – through the agency of the archangel Gabriel; in Ibn Sina’s Neo-Platonist scheme, the divine word is transmitted through reason and understanding to any, and every, person who cares to listen. The result is an amalgam of rationalism and ethics. For Muslim scholars and scientists, values are objective and good and evil are descriptive characteristics of reality which are no less ‘there’ in things than are their other qualities, such as shape and size. In this framework, all knowledge, including the knowledge of God, can be acquired by reason alone. Humanity has power to know as well as to act and is thus responsible for its just and unjust actions. What this philosophy entailed both in terms of the study of nature and shaping human behaviour was illustrated by Ibn Tufayl in his intellectual novel, Hayy ibn Yaqzan. Hayy is a spontaneously generated human who is isolated on an island. Through his power of observations and the use of his intellect, Hayy discovers general and particular facts about the structure of the material and spiritual universe, deduces the existence of God and arrives at a theological and political system (see Epistemology in Islamic philosophy; Ethics in Islamic philosophy).
While Mu‘tazilite scholars had serious philosophic differences with their main opponents, the Ash‘arite theologians, both schools agreed on the rational study of nature. In his al-Tamhid, Abu Bakr al-Baqillani defines science as ‘the knowledge of the object, as it really is’. While reacting to the Mu‘tazilite infringement on the domains of faith, the Ash‘arites conceded the need for objective and systematic study of nature. Indeed, some of the greatest scientists in Islam, such as Ibn al-Haytham (d. 1039), who discovered the basic laws of optics, and al-Biruni (d. 1048), who measured the circumference of the earth and discussed the rotation of the earth on its axis, were supporters of Ash‘arite theology (see Ash‘ariyya and Mu‘tazila).
The overall concern of Muslim scientists was the delineation of truth. As Ibn al-Haytham declared, ‘truth is sought for its own sake’, and al-Biruni confirmed in the introduction to his al-Qanun al-mas‘udi: ‘I do not shun the truth from whatever source it comes.’ However, there were disputes about the best way to rational truth. For Ibn Sina, general and universal questions came first and led to experimental work. He begins his al-Qanun fi’l-tibb (Canons of Medicine), which was a standard text in the West up to the eighteenth century, with a general discussion on the theory of drugs. For al-Biruni, however, universals came out of practical, experimental work; theories are formulated after discoveries. But either way, criticism was the key to progress towards truth. As Ibn al-Haytham wrote,‘it is natural to everyone to regard scientists favourably…. God, however, has not preserved the scientist from error and has not safeguarded science from shortcomings and faults’ (see Sabra 1972). This is why scientists so often disagree amongst themselves. Those concerned with science and truth, Ibn al-Haytham continued, ‘should turn themselves into hostile critics’ and should criticize ‘from every point of view and in all aspects’. In particular, the flaws in the work of one’s predecessors should be ruthlessly exposed. The ideas of Ibn al-Haytham, al-Biruni and Ibn Sina, along with numerous other Muslim scientists, laid the foundations of the ‘scientific spirit’ as we have come to know it.
- Methodology
The ‘scientific method’ (see Scientific method), as it is understood today, was first developed by the Muslim scientists. Supporters of both Mu‘tazilism and Ash‘arism placed a great deal of emphasis on systematic observation and experimentation. The insistence on accurate observation is amply demonstrated in the zij, the literature of astronomical handbooks and tables. These were constantly updated, with scientists checking and correcting the work of previous scholars. In medicine, Abu Bakr Muhammad al-Razi’s detailed and highly accurate clinical observations in the early third century AH (ninth century AD) provide us with a universal model. Al-Razi was the first to observe accurately the symptoms of smallpox and described many ‘new’ syndromes. However, it was not just accurate observation that was important; equally significant was the clarity and precision by which the observations are described, as was demonstrated by Ibn Sina in his writings.
The emphasis on model construction and theory building can be seen in the category of Islamic astronomical literature known as ‘ilm al-haya, or ‘science of the structure(of the universe)’, which consists of general exposition of principles underlying astronomical theory. It was on the strength of both accurate observation and model construction that Islamic astronomy launched a rigorous attack on what was perceived to be a set of imperfections in Ptolemaic astronomy (see Ptolemy). Ibn al-Haytham was the first to declare categorically that the arrangements proposed for planetary motions in the Almagest were ‘false’. Ibn Shatir (d. 1375) and the astronomers at the famous observatory in Maragha, Adharbayjan, built in the thirteenth century by Nasir al-Din al-Tusi, developed the Tusi couple and a theorem for the transformation of eccentric models into epicyclic ones. It was this mathematical model that Copernicus used to develop his notion of heliocentricity, which played an important part in the European ‘scientific revolution’.
Apart from the exact sciences, the most appropriate and interesting area in which theoretical work played an essential role was medicine. Muslim physicians attempted to improve the quality of materia medica and their therapeutic uses through continued theoretical development. Emphasis was also placed on developing a precise terminology and ensuring the purity of drugs, a concern that led to a number of early chemical and physical procedures. Since Muslim writers were excellent organizers of knowledge, their purely pharmacological texts were themselves a source for the development of theories. Evolution of theories and discovery of new drugs linked the growth of Islamic medicine to chemistry, botany, zoology, geology and law, and led to extensive elaborations of Greek classifications. Pharmacological knowledge thus became more diversified, and produced new types of pharmacological literature. As this literature considered its subject from a number of different disciplinary perspectives and a great variety of new directions, there developed new ways of looking at pharmacology; new areas were opened up for further exploration and more detailed investigation. Paper-making made publication more extensive and cheaper than use of parchment and papyrus, and this in turn made scientific knowledge much more accessible to students.
While Muslim scientists placed considerable faith in scientific method, they were also aware of its limitations. Even a strong believer in mathematical realism such as al-Biruni argued that the method of inquiry was a function of the nature of investigation: different methods, all equally valid, were required to answer different types of questions. Al-Biruni himself had recourse to a number of methods. In his treatise on mineralogy, Kitab al-jamahir (Book of Precious Stones), he is the most exact of experimental scientists. However, in the introduction to his ground-breaking study India he declares that ‘to execute our project, it has not been possible to follow the geometric method’; he therefore resorts to comparative sociology.
The work of a scholar of the caliber and prolificacy of al-Biruni inevitably defies simple classification. He wrote on mineralogy, geography, medicine, astrology and a whole range of topics which dealt with the dating of Islamic festivals. Al-Biruni is a specific product of a philosophy of science that integrates metaphysics with physics, does not attribute to either a superior or inferior position, and insists that both are worthy of study and equally valid. Moreover, the methods of studying the vast creation of God – from the movement of the stars and planets to the nature of diseases, the sting of an ant, the character of madness, the beauty of justice, the spiritual yearning of humanity, the ecstasy of a mystic – are all equally valid and shape understanding in their respective areas of inquiry. In both its philosophy and methodology, Islam has sought a complete synthesis of science and religion.
Polymaths such as al-Biruni, al-Jahiz, al-Kindi, Abu Bakr Muhammad al-Razi, Ibn Sina, al-Idrisi, Ibn Bajja, Omar Khayyam, Ibn Zuhr, Ibn Tufayl, Ibn Rushd, al-Suyuti and thousands of other scholars are not an exception but the general rule in Muslim civilization. The Islamic civilization of the classical period was remarkable for the number of polymaths it produced. This is seen as a testimony to the homogeneity of Islamic philosophy of science and its emphasis on synthesis, interdisciplinary investigations and multiplicity of methods.
- Revival attempts
At the end of the twentieth century, scholars, scientists and philosophers throughout the Muslim world are trying to formulate a contemporary version of the Islamic philosophy of science. Two dominant movements have emerged. The first draws its inspiration from Sufi mysticism (see Mystical philosophy in Islam) and argues that the notions of ‘tradition’ and the ‘sacred’ should constitute the core of Islamic approach to science. The second argues that issues of science and values in Islam must be treated within a framework of concepts that shape the goals of a Muslim society. Ten fundamental Islamic concepts are identified as constituting the framework within which scientific inquiry should be carried out, four standing alone and three opposing pairs: tawhid(unity), khilafa (trusteeship), ‘ibada (worship), ‘ilm (knowledge), halal (praiseworthy) and haram (blameworthy), ‘adl (justice) and zulm (tyranny), and istisla(public interest) and dhiya (waste). It is argued that, when translated into values, this system of Islamic concepts embraces the nature of scientific inquiry in its totality; it integrates facts and values and institutionalizes a system of knowing that is based on accountability and social responsibility. It is too early to say whether either of these movements will bear any real fruit.
- Holistics-Integralistics Paradigm & Methodology in Mulla Sadras’ Thought.
The very advanced attempt to searching andexploring the truth and reality was made by Mulla Sadra (1236-1311 AD ).He is the prominent Islamic scholar who sintetized and combine several approach and methodology had ever build in Islamic History andhuman civilizations in the harmonious & proportional way, such as peripateticism (rationalty & empiricism / masyaiyah from Palto & Aristolesfrom Greek era, Al Kindi [801-873 AD],Al Farabi [ 865-925 AD], Ibnu Sina [980-1037 AD], and Ibn Rusyd [1126-1198 AD] ), al-Razy [1149-1209] and iluminationism (isyraqiyah, by Sukhrawardi [1153-1191]and Theosophy and Mysticism(Gnostics / Irfan) from Ibn Arabi [1165-1240 AD], Nasirudin Al Thusi [1201-1274] and Al Qunawi [12090-1240 AD] and Trancendent Theosophy of Mulla Sadra (al Hikmah al Muta’aliyah).
Mulla Sadras principle theory and ontological paradigm are: The Four Jouorney (al asfar al Arba’ah), Transubtantial Movement (al Harakat al Jauhariyah),as-Shalat al-Wujud , Tasykik al-Wujud. In Epistemolgy, Mulla Sadra, and of course another several Islamic Scholars, had been following the Islamic Epistemology on Philosophy and ‘Islamicate‘ Science (vis a vis modern western-secular science) as we mention before.
Mulla Sadra (Sadr al-Din Muhammad al-Shirazi) (1571/2-1640)[22]
Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra) is perhaps the single most important and influential philosopher in the Muslim world in the last four hundred years. The author of over forty works, he was the culminating figure of the major revival of philosophy in Iran in the sixteenth and seventeenth centuries. Devoting himself almost exclusively to metaphysics, he constructed a critical philosophy which brought together Peripatetic, Illuminationist and gnostic philosophy along with Shi‘ite theology within the compass of what he termed a ‘metaphilosophy’, the source of which lay in the Islamic revelation and the mystical experience of reality as existence.
Mulla Sadra’s meta philosophy was based on existence as the sole constituent of reality, and rejected any role for quiddities or essences in the external world. Existence was for him at once a single unity and an internally articulated dynamic process, the unique source of both unity and diversity. From this fundamental starting point, Mulla Sadra was able to find original solutions to many of the logical, metaphysical and theological difficulties which he had inherited from his predecessors. His major philosophical work is the Asfar (The Four Journeys), which runs to nine volumes in the present printed edition and is a complete presentation of his philosophical ideas.
1 The primacy of existence
Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim ibn Yahya al-Qawami al-Shirazi, known variously as Mulla Sadra, Sadr al-Muta’allihin, or simply Akhund, was born in Shiraz in central Iran in AH 979-80/AD 1571-2. He studied in Isfahan with, among others, Mir Damad and Shaykh Baha’ al-Din al-‘Amili, Shaykh-e Baha’i, before retiring for a number of years of spiritual solitude and discipline in the village of Kahak, near Qum. Here he completed the first part of his major work, the Asfar (The Four Journeys). He was then invited by Allah-wirdi Khan, the governor of Fars province, to return to Shiraz, where he taught for the remainder of his life. He died in Basra in AH 1050/AD 1640 while on his seventh pilgrimage on foot to Mecca.
Safavid Iran witnessed a noteworthy revival of philosophical learning, and Mulla Sadrawas this revival’s most important figure. The Peripatetic (mashsha’i) philosophy of Ibn Sina had been elaborated and invigorated at the beginning of the Mongol period by Nasir al-Din al-Tusi, and there existed a number of important contributors to this school in the century before Mulla Sadra. Illuminationist (ishraqi) philosophy, originated by Shihab al-Din al-Suhrawardi, had also been a major current (see Illuminationist philosophy). The speculative mysticism of the Sufism of Ibn al-‘Arabi had also taken firm root in the period leading up to the tenth centuryAH (sixteenth century AD), while theology (kalam), particularly Shi‘ite theology, had increasingly come to be expressed in philosophical terminology, a process which was initiated in large part by al-Tusi (see Mystical philosophy in Islam; Islamic theology). Several philosophers had combined various strands from this philosophical heritage in their writings, but it was Mulla Sadra who achieved a true fusion of all four, forming what he called ‘metaphilosophy’ (al-hikma al-muta‘aliya), a term he incorporated into the title of his magnum opus, al-Hikma al-muta‘aliya fi’l-asfar al-‘aqliyya al-arba‘a (The Transcendent Wisdom Concerning the Four Intellectual Journeys), known simply as the Asfar.
Mulla Sadra made the primacy of existence (asalat al-wujud) the cornerstone of his philosophy. Aristotle (§§11-12) had pointed out that existence was the most universal of predicates and therefore could not be included as one of the categories, and al-Farabi added to this that it was possible to know an essence without first knowing whether it existed or not, existence thus being neither a constitutive element of an essence nor a necessary attribute, and that therefore it must be an accident. But it was Ibn Sina who later became the source for the controversy as to how the accidentality of existence was to be conceived. He had held that in the existence-quiddity (wujud-mahiyya) or existence-essence relationship, existence was an accident of quiddity. Ibn Rushd had criticized this view as entailing a regress, for if theexistence of a thing depended on the addition of an accident to it, then the same principle would have to apply to existence itself. This was merely an argument against the existence-quiddity dichotomy, but al-Suhrawardi had added to this another argument, asserting that if existence were an attribute of quiddity, quiddity itself would have to exist before attracting this attribute in order to be thus qualified. From this, al-Suhrawardi deduced the more radical conclusion that existence is merely a mental concept with no corresponding reality, and that it is quiddity which Constitutesreality.
It was this view, that of the primacy of quiddity (asalat al-mahiyya), which held sway in philosophical writing in Iran up to Mulla Sadra’s time. Indeed, Mir Damad, Mulla Sadra’s teacher, held this view. However, Mulla Sadra himself took the opposite view, that it is existence that constitutes reality and that it is quiddities which are the mental constructs. By taking the position of the primacy of existence, Mulla Sadra was able to answer the objections of Ibn Rushd and the Illuminationists by pointing out that existence is accidental to quiddity in the mind in so far as it is not a part of its essence. When it is a case of attributing existentiality to existence, however, what is being discussed is an essential attribute; and so at this point the regress stopped, for the source of an essential attribute is the essence itself.
2 The systematic ambiguity of existence
A concomitant of Mulla Sadra’s theory that reality and existence are identical is that existence is one but graded in intensity; to this he gave the name tashkik al-wujud, which has been usefully translated as the ‘systematic ambiguity’ of existence. Al-Suhrawardi, in contrast to the peripatetics, had asserted that quiddities were capable of a range of intensities; for example, when a colour, such as blue, intensifies it is not a new species of ‘blueness’ which replaces the old one, but is rather the same ‘blue’ intensified. Mulla Sadra adopted this theory but replaced quiddity with existence, which was for him the only reality. This enabled him to say that it is the same existence which occurs in all things, but that existential instances differ in terms of‘priority and posteriority, perfection and imperfection, strength and weakness’ (making reality similar to al-Suhrawardi’s Light). He was thus able to explain that it was existence and existence alone which had the property of combining ‘unity in multiplicity, and multiplicity in unity’.
Reality is therefore pure existence, but an existence which manifests itself in different modes, and it is these modes which present themselves in the mind as quiddities. Even the term ‘in the mind’, however, is merely an expression denoting a particular mode of being, that of mental existence (al-wujud al-dhihni), albeit an extremely attenuated mode. Everything is thus comprehended by existence, even ‘nothingness’, which must on being conceived assume the most meagre portion of existence in order to become a mental existent. When reality (or rather a mode of existence) presents itself to the mind, the mind abstracts a quiddity from it – being unable, except in exceptional circumstances, to grasp existence intuitively – and in the mind the quiddity becomes, as it were, the reality and existence the accident. However, this ‘existence’ which the mind predicates of the quiddity is itself merely a notion or concept, one of the secondary intelligibles. It is this which is the most universal and most self-evident concept to which the Aristotelians referred, and which al-Suhrawardi regarded as univocal. But in reality there are not two ‘things’, existence and quiddity, only existence – not the concept, but the reality – and so ‘existence’ cannot be regarded as a real attribute of quiddity; for if this were possible quiddity would have to be regarded as already existent, as al-Suhrawardi had objected.
3 Substantial Motions
Another of the key properties of existence for Mulla Sadra is its transubstantiality, effected through what he termed motion in substance (al-haraka fi’l-jawhar) or substantial motion (al-haraka al-jawhariyya). The peripatetics had held that substance only changes suddenly, from one substance to another or from one instant to another, in generation and corruption (and therefore only in the sublunar world), and that gradual motion is confined to the accidents (quantity, quality, place). They also held that the continuity of movement is something only in the mind, which strings together a potentially infinite series of infinitesimal changes – rather in the fashion of a film – to produce the illusion of movement, although time as an extension is a true part of our experience. What gives rise to movement is an unchanging substrate, part of the essence of which is that it is at an indefinite point in space at some instant in time; in other words, movement is potential in it and is that through which it becomes actual. Mulla Sadra completely rejected this, on the grounds that the reality of this substance, its being, must itself be in motion, for the net result of the peripatetic view is merely a static conglomeration of spatio-temporal events. The movement from potentiality to actuality of a thing is in fact the abstract notion in the mind, while material being itself is in a constant state of flux perpetually undergoing substantial change. Moreover, this substantial change is a property not only of sublunary elemental beings (those composed of earth, water, air and fire) but of celestial beings as well. Mulla Sadra likened the difference between these two understandings of movement to the difference between the abstracted, derivative notion of existence and the existence which is reality itself.
Existence in Mulla Sadra’s philosophical system, as has been seen, is characterized by systematic ambiguity (tashkik), being given its systematic character by substantial motion, which is always in one direction towards perfection. In other words, existence can be conceived of as a continual unfolding of existence, which is thus a single whole with a constantly evolving internal dynamic. What gives things their identities are the imagined essences which we abstract from the modes of existence, while the reality is ever-changing; it is only when crucial points are reached that we perceive this change and new essences are formed in our minds, although change has been continually going on. Time is the measure of this process of renewal, and is not an independent entity such that events take place within it, but rather is a dimension exactly like the three spatial dimensions: the physical world is a spatio-temporal continuum.
All of this permits Mulla Sadra to give an original solution to the problem which has continually pitted philosophers against theologians in Islam, that of the eternity of the world. In his system, the world is eternal as a continual process of the unfolding of existence, but since existence is in a constant state of flux due to its continuous substantial change, every new manifestation of existence in the world emerges in time. The world – that is, every spatio-temporal event from the highest heaven downwards – is thus temporally originated, although as a whole the world is also eternal in the sense that it has no beginning or end, since time is not something existing independently within which the world in turn exists (see Eternity).
4 Epistemology
Mulla Sadra’s radical ontology also enabled him to offer original contributions to epistemology, combining aspects of Ibn Sina’s theory of knowledge (in which the Active Intellect, while remaining utterly transcendent, actualizes the human mind by instilling it with intellectual forms in accordance with its state of preparation to receive these forms) with the theory of self-knowledge through knowledge by presence developed by al-Suhrawardi. Mulla Sadra’s epistemology is based on the identity of the intellect and the intelligible, and on the identity of knowledge and existence. His theory of substantial motion, in which existence is a dynamic process constantly moving towards greater intensity and perfection, had allowed him to explain that new forms, or modes, of existence do not replace prior forms but on the contrary subsume them. Knowledge, being identical with existence, replicates this process, and by acquiring successive intelligible forms – which are in reality modes of being and not essential forms, and are thus successive intensifications of existence – gradually moves the human intellect towards identity with the Active Intellect. The intellect thus becomes identified with the intelligibles which inform it.
Furthermore, for Mulla Sadra actual intelligible are self-intelligent and self-intellected, since an actual intelligible cannot be deemed to have ceased to be intelligible once it is considered outside its relation to intellect. As the human intellect acquires more intelligible, it gradually moves upwards in terms of the intensification and perfection of existence, losing its dependence on quiddities, until it becomes one with the Active Intellect and enters the realm of pure existence. Humans can, of course, normally only attain at best a partial identification with the Active Intellect as long as they remain with their physical bodies; only in the case of prophets can there be complete identification, allowing them to have direct access to knowledge for themselves without the need for instruction. Indeed, only very few human minds attain identification with the Active Intellect even after death.
5 Methodology
Even this brief account of Mulla Sadra’s main doctrines will have given some idea of the role that is played in his philosophy by the experience of the reality which it describes. Indeed he conceived of hikma (wisdom) as ‘coming to know the essence of beings as they really are’ or as ‘a man’s becoming an intellectual world corresponding to the objective world’. Philosophy and mysticism, hikma and Sufism, are for him two aspects of the same thing. To engage in philosophy without experiencing the truth of its content confines the philosopher to a world of essences and concepts, while mystical experience without the intellectual discipline of philosophy can lead only to an ineffable state of ecstasy. When the two go hand in hand, the mystical experience of reality becomes the intellectual content of philosophy.
The four journeys, the major sections into which the Asfar is divided, parallel a fourfold division of the Sufi journey. The first, the journey of creation or the creature (khalq) to the Truth (al-haqq), is the most philosophical; here Mulla Sadra lays out the basis of his ontology, and mirrors the stage in the Sufi’s path where he seeks to control his lower nafs under the supervision of his shaykh. In the second journey, in the Truth with the Truth, the stage at which the Sufi begins to attract the divine manifestations, Mulla Sadra deals with the simple substances, the intelligences, the souls and their bodies, including therefore his discussion of the natural sciences. In the third journey, from the Truth to creation with the Truth, the Sufi experiences annihilation in the Godhead, and Mulla Sadra deals with theodicy; the fourth stage, the journey with the Truth in creation, where he gives a full and systematic account of the development of the human soul, its origin, becoming and end, is where the Sufi experiences persistence in annihilation, absorbed in the beauty of oneness and the manifestations of multiplicity.
Mulla Sadra had described his blinding spiritual realization of the primacy of existence as a kind of ‘conversion’:
In the earlier days I used to be a passionate defender of the thesis that the quiddities are the primary constituents of reality and existence is conceptual, until my Lord gave me spiritual guidance and let me see His demonstration. All of a sudden my spiritual eyes were opened and I saw with utmost clarity that the truth was just the contrary of what the philosophers in general had held…. As a result [I now hold that] the existences (wujudat) are primary realities, while the quiddities are the ‘permanent archetypes’ (a‘yan thabita) that have never smelt the fragrance of existence. (Asfar, vol. 1, introduction).
Therefore it is not surprising that Mulla Sadra is greatly indebted to Ibn al-‘Arabi in many aspects of his philosophy. Ibn Sina provides the ground on which his metaphilosophy is constructed and is, as it were, the lens through which he views Peripatetic philosophy. However, his work is also full of citations from the Presocratics (particularly Pythagoras), Plato, Aristotle, the Neoplatonists (see Neoplatonism in Islamic philosophy) and the Stoics (taken naturally from Arabic sources), and he also refers to the works of al-Farabi, and Abu’l Hasan al-‘Amiri, who had prefigured Mulla Sadra’s theory of the unity of intellect and intelligible. This philosophical heritage is then given shape through the illuminationism of al-Suhrawardi, whose universe of static grades of light he transformed into a dynamic unity by substituting the primacy of existence for the latter’s primacy of quiddity. It is in this shaping that the influence of Ibn al-‘Arabi, whom Mulla Sadra quotes and comments on in hundreds of instances, can be most keenly felt. Not only is that apparent in Mulla Sadra’s total dismissal of any role for quiddity in the nature of reality, but in the importance which both he and Ibn al-‘Arabi gave to the imaginal world (‘alam al-mithal, ‘alam al-khayal).
In Ibn Sina’s psychology, the imaginal faculty (al-quwwa al-khayaliyya) is the site for the manipulation of images abstracted from material objects and retained in the sensus communis. The imaginal world had first been formally proposed by al-Suhrawardi as an intermediate realm between that of material bodies and that of intellectual entities, which is independent of matter and thus survives the body after death. Ibn al-‘Arabi had emphasized the creative aspects of this power to originate by mere volition imaginal forms which are every bit as real as, if not more real than, perceptibles but which subsist in no place. For Mulla Sadra, this world is a level of immaterial existence with which it is possible for the human soul (and indeed certain higher forms of the animal soul) to be in contact, although not all the images formed by the human soul are necessarily veridical and therefore part of the imaginal world. For Mulla Sadra, as also for Ibn al-‘Arabi, the imaginal world is the key to understanding the nature of bodily resurrection and the afterlife, which exists as an immaterial world which is nevertheless real (perhaps one might say more real than the physical world), in which the body survives as an imaginal form after death.
Philosophy has always had a tense relationship with theology in Islam, especially with the latter’s discourse of faith (iman) and orthodoxy. In consequence, philosophy has often been seen, usually by non-philosophers, as a school with its own doctrines. This is despite the assertions of philosophers themselves that what they were engaged in was a practice without end (for, as Ibn Sina had declared that what is known to humankind is limited and could only possibly be fulfilled when the association of the soul with the body is severed through death), part of the discipline of which consisted in avoiding taqlid, an uncritical adherence to sects (see Islam, concept of philosophy in). It is the notable feature of Mulla Sadra’s methodology that he constantly sought to transcend the particularities of any system – Platonic, Aristotelian, Neoplatonic, mystical or theological – by striving to create through his metaphilosophy an instrument with which the soundness of all philosophical arguments might be tested. It is a measure of his success that he has remained to the present day the most influential of the ‘modern’ philosophers in the Islamic world.
- Conclusion
To summarize this epistemological discussion, let us quote the comparation schema from Dr. Haidar Bagir lectures & his paper: Contemporary Criticism of Methodology in Epistemology in Islamic Philosophy, 7 p, as follow:
| ASPECT OF EPISTEMOLOGY |
WESTERN EPISTEMOLOGY |
EPISTEMOLOGY IN ISLAMIC KNOWLEDGE |
| 1. Sources of Knowledge : |
- Empirical-observable
- Rational
|
1. Empirical-observable world
2. Rational (Analitical; Reason)
3. Imaginal Realm (khayal/barzakh)
4. Intuition (hight Intelect, Qalb, Fuad)
5. Historical fact
6. Sacred Text (revelation/wahyu) |
| 2. Limit of Knowledge |
Rational science (ratiocination) |
No limit expect to know Dzat al Wujud (God) |
| 3.Structure of Knowledge |
In the modern era there is separable view between Subject & Object (Objectivity) |
1. Ilm al Husuli (Aquired Knowledge)
2. ilm al Hudhuri(Presential knowledge) &Ilmu Laduni
3. Subject & Object are unity |
| 4. Validity of Knowledge |
- Logical Coherence
- Correspondence
- Pragmatic Funtion
|
1. Logical Coherence (Rational-Bayani)
2. Correspondence with Fact & History (Demonstartive/Burhani)
3. Pragmatic Function
4. Harmoni with Divine Guidelines
5. Irfani (iluminationist)
6. ect. |
| 5. Main Division & Relation |
- Theoritical Philosophy
- Practical Philosophy
- Theoritical Philosophy (al Hikmah Nazhariyah)
- Practical Philosophy (al hikmah Amaliyah)
|
Principle:
Practical Phylosophy (Science-technology) must relies on, or based on Theoritical Phylosophy. |
Hence, Islamic Holistic and Integralistic Paradigm on epistemology, on ontology and on axiology are the prime principles that we are need to reviewing and reconstructing our philosophy, our sciences, our ideology and our civilization.
According to Mr. Armahedi Mahzar in Integralist Reflection there are Evolutionary Cycle of existential stages and Dynamic Integrality between Ultimate Reality (God, Allah SWT) and Human Actuality with evolution and devolution. This is the principle of : Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.Wallahu ‘alam.
List of works of Mulla Sadra [Sadr al-Din al-Shirazi]
(c.1628) al-Hikma al-muta‘aliya fi-’l-asfar al-‘aqliyya al-arba‘a (The Transcendent Wisdom Concerning the Four Intellectual Journeys), ed. R. Lutfi et al., Tehran and Qum: Shirkat Dar al-Ma‘arif al-Islamiyyah, 1958-69?, 9 vols; vol. 1, 2nd printing, with introduction by M.R. al-Muzaffar, Qum: Shirkat Dar al-Ma‘arif al-Islamiyyah, 1967.(This is Mulla Sadra’s major work, often known simply as Asfar (The Four Journeys). The full edition includes partial glosses by ‘Ali al-Nuri, Hadi al-Sabzawari, ‘Ali al-Mudarras al-Zanuzi, Isma‘il al-Khwaju’Ial-Isfahani, Muhammad al-Zanjani and Muhammad Husaynal-Tabataba’i.)
Mulla Sadra [Sadr al-Din al-Shirazi] (c.1628) Kitab al-masha‘ir (The Book of Metaphysical Penetrations), ed., trans. and intro. by H. Corbin,Le livre des pénétrations métaphysiques, Paris: Départment d’Iranologie de l’Institut Franco-Iranien de Recherche, and Tehran: Librairie d’Amerique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, Bibliothèque Iranienne vol. 10, 1964; French portion re-edited Lagrasse: Verdier, 1988; ed. and trans. P. Morewedge, The Metaphysics of Mulla Sadra, New York: Society for the Study of Islamic Philosophy and Science, 1992. (Corbin is a synopsis of Mulla Sadra’s ontology, with a useful bibliography of Mulla Sadra’s writings and introduction by Corbin. Morewedge provides a parallel Arabic-English edition; the translation is based on Corbin’s edition of the text.) Mulla Sadra [Sadr al-Din al-Shirazi] (c.1628) al-Hikma al-‘arshiyya (The Wisdom of the Throne), ed. with Persian paraphrase by G.R. Ahani, Isfahan, 1962; trans. and intro. J.W. Morris, The Wisdom of the Throne: An Introduction to the Philosophy of Mulla Sadra, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.(A useful summary of Mulla Sadra’s views on theology and eschatology; the introduction to the English translation provides an informative general introduction to Mulla Sadra work.)
References and further reading
Barbour, I. (1966) Issues in Science and Religion, New York: Harper & Row.(Very accessible survey of relationsbetween science and Christianity, beginning in the modern period.)
Barbour, I. (1974) Myths, Models and Paradigms, New York: Harper & Row. (Methodological comparison ofscience and religion, making use especially of Thomas Kuhn’s philosophy of science. Very accessible.)
Barbour, I. (1990) Religion in an Age of Science: The Gifford Lectures, 1989-1991, San Francisco, CA:
HarperCollins, vol. 1.(Combines and updates material from previous books. A particularly good introduction.)
Bakar, O. (1996) ‘Science’, in S.H. Nasr and O. Leaman, History of Islamic Philosophy, London: Routledge, ch. 53, 926-46.(Discussion of some of the main thinkers and principles of science in Islam.)
Dani, A.H. (1973) Al-Biruni’s India, Islamabad: University of Islamabad Press.(Al-Biruni’s research on the people and country of India.)
Darwin, C. (1859) The Origin of Species, London: John Murray.(Classic statement of Darwin’s thesis.)
Draper, J.W. (1874) History of the Conflict between Religion and Science, New York: D. Appleton.(A once-popular denunciation of Catholicism for its interference with scientific development.)
Eaves, L.J., Martin, N.G. and Heath, A.C. (1990) ‘Religious Affiliation in Twins and Their Parents: Testing a Model of Cultural Inheritance’, Behaviour Genetics 20 (1): 1-21.(Provides some evidence for a genetic component in religious behaviour.)
Fakhry, M. (1983) A History of Islamic Philosophy, London: Longman, 2nd edn.(A general introduction to the role of reason in Islamic thought.)
Hill, D. (1993) Islamic Science and Engineering, Edinburgh: Edinburgh University Press.(The classic work on the practical aspects of Islamic science.)
Hefner, P. (1993) The Human Factor: Evolution, Culture, and Religion, Minneapolis, MN: Fortress Press.(Example of theological use of the theory of evolution.)
Hourani, G. (1975) Essays on Islamic Philosophy and Science, Albany, NY: State University of New York
Press.(An important collection of articles on particular theoretical issues in the philosophy of science.)
Hourani, G. (1985) Reason and Tradition in Islamic Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.(A discussion of the clash between reason and tradition in Islamic culture as a whole, especially in ethics.)
Ibn Tufayl (before 1185) Hayy ibn Yaqzan (The Living Son of the Vigilant), trans. S. Oakley, The Improvement of Human Reason Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokhdan, Zurich: Georg Olms Verlag, 1983.(This translation of Hayy ibn Yaqzan was first published in 1708.)
Kirmani, Z. (1992) ‘An Outline of Islamic Framework for a Contemporary Science’, Journal of Islamic Science 8 (2): 55-76.(An attempt at conceptualizing modern science from an Islamic point of view.)
Izutsu Toshihiko (1971) The Concept and Reality of Existence, Studies in the Humanities and Social Relations 13, Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies.(Although concerned primarily with the philosophical ideas of Mulla Sadra’s principal nineteenth century follower, Mulla Hadi al-Sabzawari, this work contains an extremely valuable exposition of the history of the existence-essence controversy in metaphysics, and deals with Mulla Sadra’s views in many places.) Leaman, O. (1985) An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.(A general approach to the role of philosophy in Islam.)
Leslie, J. (1989) Universes, London: Routledge.(An accessible account of the anthropic or fine-tuning issue.)
Lindberg, D.C. (1992) The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical,Religious, and Institutional Context, 600 BC to AD 1450,Chicago, IL: University of Chicago Press.(Accessible.)
Lindberg, D.C. and Numbers, R.L. (eds) (1986) God and Nature: Historical Essays on the Encounter betweenChristianity and Science, Berkeley, CA: University of California Press. (Criticizes accounts of the historyof science and religion that presuppose the warfare model.)
Merton, R. (1938) Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England,New York: Harper & Row,repr. 1970. (Presents the thesis that the development of science was encouraged by Puritanism.)
Murphy, N. (1990) Theology in the Age of Scientific Reasoning, Ithaca, NY: Cornell University Press.(On therelation between theological method and philosophy of science. Presupposes some knowledge of philosophy.)
Murphy, N. and Ellis, G.F.R. (1996) On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and Ethics, Minneapolis, MN: Fortress Press.(Comprehensive model for relating natural and social sciences to theology and ethics. Moderate technicality.)
Nasr, S.H. (1978) Sadr al-Din Shirazi and His Transcendent Theosophy: Background, Life and Works, Tehran: Imperial Academy of Philosophy.(The first part of a planned, but so far uncompleted, two-volume work, the second volume of which is intended to deal with Mulla Sadra’s philosophical ideas; contains the best bibliography of Mulla Sadra’s works.)
Nasr, S.H. (1996) ‘Mulla Sadra: His Teachings’, in S.H. Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, 643-52.(Short summary of Mulla Sadra’s thought.)
Nasr, S.H. (1993) The Need for a Sacred Science, Richmond: Curzon Press.(An argument for the significance of religion in any understanding of science.)
Pines, S. (1964) ‘Ibn al-Haytham’s Critique of Ptolemy’, in Actes du Xe Congrès internationale d’histoire des sciences, Paris: Ithaca.(One of the most important works in Islamic astronomy.)
Peacocke, A.R. (1979) Creation and the World of Science: The Bampton Lectures, 1978, Oxford: Clarendon Press.(Thorough survey of issues in the relation of contemporary science to Christian theology. Expands onissues of evolution and creation, and the hierarchical ordering of the sciences. Less accessible than arbour.)
Peacocke, A.R. (1990) Theology for a Scientific Age, Oxford: Blackwell; enlarged edn,Minneapolis, MN: FortressPress, 1993.(Relates top-down causation to divine action.)
Rahman, F. (1975) The Philosophy of Mulla Sadr (Sadr al-Din al-Shirazi), Albany, NY: State University of New York Press. (To date, the only full-scale study of Mulla Sadra’s philosophy in English.)
Ziai, H. (1996) ‘Mulla Sadra: His Life and Works’, in S.H. Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, 635-42.(Biographical essay discussing Mulla Sadra’s influence and works.)
Rolston, H. (1987) Science and Religion: A Critical Survey, New York: Random House.(A good introduction to the field; less readable than Barbour, but aesthetically pleasing.)
Russell, R.J., Murphy, N. and Peacocke, A. (eds) (1994) Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican City State: Vatican Observatory; distributed by University of Notre Dame Press.(A series of articles on divine action, of various levels of technicality.)Sabra, A.I. (1972) ‘Ibn al-Haytham’, in C.C.
Gillispie (ed.) Dictionary of Scientific Biography, New York: Charles Scribner’s Sons, 6th edn. (An excellent introduction to the thought and work of Ibn al-Haytham.) Pakistan, November 26-December 12, 1973, Karachi: Hamdard Academy.(Contains numerous papers discussing all the major works of al-Biruni.)
Saliba, G. (1991) ‘The Astronomical Tradition of Maragha: A Historical Survey and Prospects for Future Research’,Arabic Sciences and Philosophy 1 (1): 67-100.(A study of a particularly well-developed period of astronomical research in the Islamic world.)
Sardar, Z. (1989) Explorations in Islamic Science, London: Mansell.(Some contemporary debates on the nature ofIslamic science.)
Young, M.J.L., Latham, J.D. and Serjeant, R.B. (1990) Religion, Learning and Sciences in the Abbasid Period, Cambridge: Cambridge University Press.(The leading work on the most important period for science in the Islamic world.)
White, A.D. (1896) A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, New York: D. Appleton, 2 vols.(Referred to in introduction and §2.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge
Footnote
[1] Koento Wibisono, Dasar-Dasar Filsafat, (Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1989), p. 517.
[2] Peter D. Klein, Routledge Encyclopedia of Philosophy, (Routledge: London and New York, 1998), version 1.0.
[3] Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, (Totowa New Jersey: Adams & Co., 1971), p. 94.
[4] George Thomas White Patrick, Introduction to Philosophy, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1954), p. 325.
- Wibisono, Op.Cit., p.517.
6 Doni Gahral Adian, Menyoal Objektifisme Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Teraju, 2002), p. 17.
7 Ibid., p. 19.
8 Murthadha Muthahhari, Mengenal Epistemology, translated from Iranian book: Mas’ale Syenokh, (Teheran:Intisyaarate Shadra, 1989), p. 180.
[8]
9 Ibid.
[10] Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Philosophical Instruction, An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy, (New York: Binghamton, University Global Publications, 1999), p. 85-6.
[13] Nancey Murphy, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London.
[14] Oliver Leaman, Routledge Encyclopedia of Islamic Philosophy, Version 1.0, (London and New York:Routledge, 1998), p. 2.
[15] Shams C. Innati, Routledge Encyclopedia of Islamic Philosophy, Version 1.0, (London: Routledge, 1998), p. 43-7.
[17] Dr. Wahid Akhtar, Islamic Concept of Knowledge,http://www.muslimphilosophy.com.
[18] For further information’s according to this discourse check Musa Kazhim in “Kekhasan Filsafat Islam”, an introduction to Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis, (Bandung: Mizan, 2001). This book is transliteration from Majid Fakhry, A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, (London: Oneworld Publication, Oxford, 1977).
[19] Sari Nusaibeh, “Epistemology”, in History of Islamic Philosophy, ed. S. H. Nasr and Oliver Leaman, (London and New York: Routledge, 1996), Part II, p. 824-40.
[20] Ibn Rushd star his risalah with provokating question according to legality of philosophy. See Ibn Rushd, Fashl Al-Maqal fima baina Al-Hikmah wa Al-Syari`ah min Al-Ittishal, (Kairo: tt.), p. 2.
[21] ZiauddinSardar,Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge
[22] JOHN COOPERRoutledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge
[1] Ini adalah hipotesis dari Seyyed Hossein Nasr dalam bukunya; Islam and The Plight of Modern Man... (Revised and Enlarged Edition), ABC International Group, Inc, Chicago, 2001, p.4-5
[2] Seyyed Hossein Nasr, Islam and The Plight of Modern Man, (Revised and Enlarged Edition), ABC International Group, Inc, Chicago, 2001, p.4-5
[3] Mengenai kesalahan bertahap gambaran citra manusia moden di Barat,, lihatlah G. Durrand, Defiguration Philosophique et figure traditionelle de I’homme en Occident,” Eranos-Jahrbuch, XXXVIII, 1971, pp.45-93; Sherrard, The Rape of Man and Nature, Ipswich (UK), Golgooonoza Press, 1987. Chap. 2 and 3, pp 42-89; and S.H. Nasr, Knowledge and the Sacred, Albany (NY), the State University of New York Press, 1999. Chap. 5, pp. 160-188. For a treatment of this subject from the perspective of a Western Seeker who has turned to traditional Islam see J. Herlihy, The Search of The Trurth—contemporary Raflection of Traditional Islamic Themes, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Islam, 1990.
[4] Seyyed Hossein Nasr, Islam and The Plight of Modern Man, , (Revised and Enlarged Edition), ABC International Group, Inc, Chicago, 2001, p.6
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism#cite_note-1
[6] Pericles Lewis, Modernism, Nationalism, and the Novel (Cambridge University Press, 2000). pp 38-39. [James] Joyce‘s Ulysses is a comedy not divine, ending, like Dante’s, in the vision of a God whose will is our peace, but human all-too-human…” Peter Faulkner, Modernism (Taylor & Francis, 1990). p 60., quoted from http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism#cite_note-1, acsessed at August, 2010
[7] Gardner, Helen, Horst De la Croix, Richard G. Tansey, and Diane Kirkpatrick. Gardner’s Art Through the Ages (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1991). ISBN 0155037706. p. 953. quoted from http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism#cite_note-1, acsessed at August , 2010
[8] Adorno, Theodor. Minima Moralia. Verso 2005, p. 218. quoted from http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism#cite_note-1, acsessed at August , 2010
[9] Tradition and the individual talent” (1919), in Selected Essays. Paperback Edition. (Faber & Faber, 1999). quoted from http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism#cite_note-1, acsesed in August 2010
[10] Childs, Peter. Modernism (Routledge, 2000). ISBN 0415196477. p. 17. , quoted from http://en.wikipedia.org/wiki/ Modernism#cite_note-1, Accessed on 2009-02-08
[11] F. Budi Hardiman, Sejarah Filsafat Barat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, Gramedia, Jakarta, 2004. For next quotients it will mention by F. Budi Hardiman, Sejarah Filsafat Barat Modern…..
[12] F. Budi Hardiman, Sejarah Filsafat Barat Modern
[13] F. Budi Hardiman, Sejarah Filsafat Barat Modern…..
[14] F. Budi Hardiman, Sejarah Filsafat Barat Modern…..
[15] Adopted from Nancey Murphy, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London.
[16] lihat Origen; Augustine, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London [16]
[17] liha Tertullian, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London
[18] Lihat “ interpretation of Quantum mechanics”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London
[19] Lihat “Chaos theory”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1, London
[20] Seyyed Hossein Nasr, The Plight of Modern Man, (Revised and Enlarged Edition), page 4, ABC International Group, Inc. Chicago, 2001. For next Quotations it will mention by Seyyed Hossein Nasr, The Plight of Modern Man
[21] Seyyed Hossein Nasr, The Plight of Modern Man, p. 4
[22] Seyyed Hossein Nasr, The Plight of Modern Man, p.5
[23] Armahedi Mazhar, “Kata Pengantar” (Introduction) in Hussein Heriyanto, Paradigma Holistik, p.xiii, Penerbit Teraju, Jakarta, 2003. p.xiii
[24] Descartes, R. Discourse and Methods (Translated by Jhon Veitch), J.M. Dent & Sons Ltd, London, 1960.
[25] Armahedi Mahzar, Lecture Presentation of master program of Islamic Philosophy at Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, June 18, 2005. For the next quotation it will mention by Armahedi Mahzar, Lecture Presentation…..
[26] Armahedi Mahzar, Lecture Presentation of master program of Islamic Philosophy at Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, June 18, 2005. For the next quotation it will mention by Armahedi Mahzar, Lecture Presentation…..
[27] Mulyadhi Kartanegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf (PUSKAFIT) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005. For next quotation it will mention by Mulyadhi Kartenegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf,
[28] Mulyadhi Kartanegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf (PUSKAFIT) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005. For next quotation it will mention by Mulyadhi Kartenegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf,
[29]. Mulyadhi Kartenegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf, (PUSKAFIT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005.
[30] Mulyadhi Kartanegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf (PUSKAFIT) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005. For next quotation it will mention by Mulyadhi Kartenegara, Proposal Pusat Kajian Filsafat dan Tasawuf,
[31] Hussein Heriyanto, Paradigma Holistik, Teraju-Mizan Jakarta, 2003
[32] One of radical variant of Cartesian-Newtonian Paradigm is Positivism. Positivism paradigm placed language and the method of physical sciences as the only methods for scientific activity, including for social sciences and cultures. The concepts in psychology, sociology, politics and anthropology were said scientific if refer to basic principles of Newtonian physics. Even for Egon G. Guba,, Cartesian-Newtonian paradigm is identical with positivism, since assumed with dualistic epistemology (determination between subject and object), Please read The Paradigm Dialog (edited by Egon G. Guba), Sage Publication, California, 1990.
[33] Dikutip dari harian KOMPAS news paper, October 25, 199..
[34] Giddens, A. Beyond left and Right, Polity Press, Cambridge, 1984, p.4
[35] Hussein Heriyanto, Paradigma Holistik, Teraju-Mizan Jakarta, 2003
[36] Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual, Mizan Bandung, 1997
[37] Koento Wibisono, Dasar-Dasar Filsafat, (Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1989), p. 517
[38] Peter D. Klein, Routledge Encyclopedia of Philosophy, (Routledge): London and New York, 1998, version 1.0.
[39] Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, (Totowa New Jersey: Adams & Co., 1971), p. 94.
[40] George Thomas White Patrick, Introduction to Philosophy, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1954), p. 325
[41] Koento Wibisono, Dasar-Dasar Filsafat, (Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1989), p. 517
[42] Doni Gahral Adian, Menyoal Objektifisme Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Teraju, 2002), p. 17
[43] Doni Gahral Adian, Menyoal Objektifisme Ilmu Pengetahuan, p.17
[44] Murthada Mutahhari, Mengenal Epistemology, Translated from Iranian Book: Mas’ale Syenokh (Teheran, Intisyaarate Shadra, 1989), p.180
[45] Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Philosophical Instruction, An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy, (New York: Binghamton, University Global Publications, 1999), p. 85-6. For the next quotation it will mention by Taqi Misbah Yazdi, Philosophical Instruction, An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy.
[46] Taqi Misbah Yazdi, Philosophical Instruction, An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy, p. ..
[47] Seyyed Hossein Nasr, Islamic Philosophy from its Origin to the Present, State University of New York Press, 2006
[48] Kita harus ingat bahwa Pythagoras mendirikan sebuah masyarakat religious di Croton yang berpusat di sekitar Apollo, dam dia menyediakan peraturan kehidupan seperti para Nabi lain para pendiri agama-agama. Lihatlah Kenneth S. Guthrie, kompilasi dan terjemahan., The Pythagorean Sourcebook and Library, (Grand Rapids, MI: Phanes, 1987); khususnya lihatlah “The Life of Pythagoras” oleh lamblichus.pp.57ff. di mana di sana bahkan ada perbandingan bahwa Pythagoras sebagai makhluk ilahiyah dan diidentifikasikan sebagai Dewa Apollo itu sendiri (p.80). Lihat juga misalnya karya agunhg Peter Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery and Magic (Oxford: Clarendon, 1995), yang terkait dengan baiuk Pythagoras maupun Empedocles
[49] Lihat Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom (Inverness, CA: The Golden Sufi Center, 1999); and Reality, (Inverness, CA: The Golden Sufi Center, 2004). Untuk kutipan berikutnya yang akan diambil dari Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom, and Peter Kingsley, Reality
[50] Dalam apa yang diikuti tentang Parmenides, Seyyed Hossein Nasr telah menunjukkan dalam karya Kingsley, Reality. Pp. 31ff
[51] Lihat Seyyed Hossein “Spiritual Chivalry”, in ed. S.H. Nasr, Islamic Spirituality, Vol. 2 (New York: Crossroad, 1991), pp.304-15
[52] Lihat juga: ‘Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’I, Ali wa al-Hikmat al-ilahiyyah, in his Majmu a-yi rasa’il, Syayyid Hadi Khusrawshahi (ed). (Tehran: Daftar-i- Nashr-I farhang-I Islami, 1370, A.H. [solar], pp. 191ff
[53] Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom, p.33
[54] Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom p.40
[55] Martin Lings, The Secret of Shakespeare (New York: Inner Traditions International, 1984), p. 18
[56] Di dalam teks Islami, Nabi Idris atau Ukhnukh (Enoch), yang diidentikkan dengan Hermes, telah diberi gelar Abu al-Hukama,atau Bapak Para Filosof,. Lihat “Hermes and Hermetic Writing in the Islamic World” in Nasr, Islamic Life anf Thought , (Chicago: ABC International Group, 2001), pp.102-19
[57] Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom.,p.46
[58] Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom.p.87
[59] Peter Kingsley, In the Dark Places of Wisdom p.62
[60] Ibid., p.320. See also Kingsley, Ancient Philosophy, Mysticism, and Magic, in Passim.
[61] Kingsley, Reality, P.323
[62] See, S.H. Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (Albany: State University of New York Press, 1993), Chapter 15, “Nature and The Visionary Recitals,” pp.263-74
[63] Lihat Huston Smith, Forgotten Truth (San Fransico: Harper, 1992), especially chapter 3, “Levels of Selfhood,” pp.60-95; also Rene Guenon, The Multiple States of being, Trans. Joscelyn Godwin (Burdett, NY: Larson, 1984).
[64] Lihat Huston Smith, Forgotten Truth (San Francisco: Harper, 1992), especially chapter 3, “Levels of Reality,” pp. 34-59; and Chapter 4, “Levels of Selfhood,” pp.60-95; also Rene Guenon, The Multiple Stages of Being, Trans. Joscelyn Godwin (Burdett, NY: Larson, 1986).
[65] Kita hanya perlu membaca tentang ajaran besar tokoh bijaksana Sioux Elk Hitam untuk menyadari filosofi yang mendalam apa yang ada meskipun secara lisan antara orang-orang untuk siapa kenabian adalah realitas pusat kehidupan spiritual mereka. Lihat Joseph E. Browrn, The Pipe Suci (New York: Pengguin Metaphysical Library, 1986).
[66] Henry Corbin telah sangat peduli dengan issue ini dalam banyak karyanya yang kita akan beralih kemudian setelah volume ini.
[67] An New Worldview, http://www.centerfor sacredsciences.org, accessed at October 2010
[68] Dalam Pandangan dunia Islami kita percaya bahwa alam semesta, manusia dan Tuhan adalah dalam SATU REALITAS (In Islamic worldview we believe that universe, man and God are in One Reality). Inilah konsep “Wahdat al-Wujud” dalam konsep ‘Arabi, or konsep “Al-Shalat al-Wujud” dalam istilah Mulla Sadra
[69] Dalam ajaran Mulla Sadra, ini diterangkan dengan konsep “Itihad baina Aqil wa Ma’qul”
[70] Resources and Link’s: As a starting point for further research on mysticism, science, and worldviews, we recommend the following resource: CSS Resources: Holos: Forum for a New Worldview: Holos Journal published by the Center for Sacred Sciences; Articles : Science and Mysticism in the 20th Century by Joel, Questioning the Scientific Worldview by Tom McFarlane, The Illusion of Materialism by Tom McFarlane Other Resources Books: The Need for a Sacred Science by Seyyed Hossein Nasr, The Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn, A Study of History by Arnold Toynbee, The Passion of the Western Mind by Richard Tarnas, The Social Construction of Reality by Peter Berger, Laws of Form by G. Spencer-Brown Audio: Religious Diversity in America by Huston Smith and Diana Eck. A thirty-minute ReadAudio stream of a presentation sponsored by the Cambridge Forum a few weeks after 9/11/01. In the first half, Prof. Smith contrasts the traditional religious worldview with the modern materialistic worldview. In the second half, Prof. Eck discusses the present state of religious diversity in America and the different ways of dealing with these differences among us; Websites: The Center for Integral Science: (http://www.intergralscience.org), Laws of Form (http://www.lawsofform.org),
[71] Sub Judul ini adalah Article dari Carl W. Ernst, University of North Carolina at Chapel Hill Middle East Studies Association Bulletin vol. 28, no. 2 (December 1994), pp. 176-81. Based on references bellows; Gai Eaton. King of the Castle: Choice and Responsibility in the Modern World. 216 pages. 2nd ed., Cambridge: The Islamic Texts Society, 1990 [1977]; Martin Lings. Symbol & Archetype: A Study of the Meaning of Existence. viii + 141 pages. Index. Cambridge: Quinta Essentia, 1991. ISBN 1-870196-04-X, 1-870196-05-8 paperback; Seyyed Hossein Nasr. Traditional Islam and the Modern World. London: Kegan Paul International, 1990; Seyyed Hossein Nasr, ed. Islamic Spirituality: Manifestations. World Spirituality, An Encyclopedic History of the Religious Quest, vol. 20. xxviii + 548 pages. Preface to the Series by Ewert Cousins, Introduction, Bibliography, Contributors, Photographic Credits, Index of Names. New York: The Crossroad Publishing Company, 1991. ISBN 0-8245-0768-1.
[72] Huston Smith, “Is there a Perennial Philosophy?”, JAAR LV (1987):553-66; James S. Cutsinger, “The Knowledge that Wounds Our Nature: The Message of Frithjof Schuon,” JAAR LX (1992):465-92.
[73] http://www.centerforsacredsciences.org/traditions.html
![]()
![]()


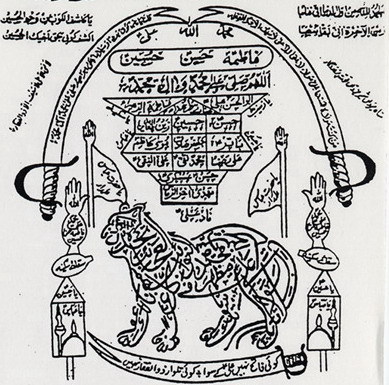
 Pada akhir Januari lalu, hanya beberapa saat setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang moderat terkait ekspor mineral mentah, bos PT. Freeport langsung terbang dari New York ke Jakarta.
Pada akhir Januari lalu, hanya beberapa saat setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang moderat terkait ekspor mineral mentah, bos PT. Freeport langsung terbang dari New York ke Jakarta.

 Taprobana (Yunani Kuno: Ταπροβανα) atau Taprobane (Ταπροβανη) adalah sebuah nama bersejarah untuk sebuah pulau di Samudera Hindia. Onesicritus (ca 360 SM – ca 290 SM) adalah penulis pertama yang menyebutkan pulau Taprobana. Nama itu juga dilaporkan di Eropa oleh Megasthenes, seorang geografer Yunani, sekitar tahun 290 SM, dan kemudian digunakan oleh Ptolemy dalam risalah geografisnya untuk mengidentifikasi sebuah pulau yang relatif besar di sebelah selatan benua Asia. Meskipun lokasi yang tepat untuk nama tersebut masih belum jelas, beberapa ilmuwan menganggapnya sebagai penafsiran yang kurang jelas tentang beberapa pulau, termasuk Sumatera dan Sri Lanka.
Taprobana (Yunani Kuno: Ταπροβανα) atau Taprobane (Ταπροβανη) adalah sebuah nama bersejarah untuk sebuah pulau di Samudera Hindia. Onesicritus (ca 360 SM – ca 290 SM) adalah penulis pertama yang menyebutkan pulau Taprobana. Nama itu juga dilaporkan di Eropa oleh Megasthenes, seorang geografer Yunani, sekitar tahun 290 SM, dan kemudian digunakan oleh Ptolemy dalam risalah geografisnya untuk mengidentifikasi sebuah pulau yang relatif besar di sebelah selatan benua Asia. Meskipun lokasi yang tepat untuk nama tersebut masih belum jelas, beberapa ilmuwan menganggapnya sebagai penafsiran yang kurang jelas tentang beberapa pulau, termasuk Sumatera dan Sri Lanka.


































































 Sebetulnya, tema Al-Asma Wa As-Sifat bisa kita lihat dari dua disiplin ilmu. Bisa dibahas dan didiskusikan dari sisi Filsafat dan juga bisa dibahas dari sisi ilmu Irfan (Tasawuf). Walaupun menurut Mulla Sadrapembahasan ini termasuk dari tema yang sangat rumit dan bahkan beliau mensyarahkan tentang sifat-sifat Allah dalam kitab Syarah Ushul Al-Kafi yang berisikan syarah yang rinci mengenai sifat-sifat Allah. Tema ini menjadi sangat manis (mudah) jika dibahas dari sisi irfan, namun menjadi sangat rumit jika dibahas dari sisi filsafat.
Sebetulnya, tema Al-Asma Wa As-Sifat bisa kita lihat dari dua disiplin ilmu. Bisa dibahas dan didiskusikan dari sisi Filsafat dan juga bisa dibahas dari sisi ilmu Irfan (Tasawuf). Walaupun menurut Mulla Sadrapembahasan ini termasuk dari tema yang sangat rumit dan bahkan beliau mensyarahkan tentang sifat-sifat Allah dalam kitab Syarah Ushul Al-Kafi yang berisikan syarah yang rinci mengenai sifat-sifat Allah. Tema ini menjadi sangat manis (mudah) jika dibahas dari sisi irfan, namun menjadi sangat rumit jika dibahas dari sisi filsafat. Filsafat Hikmah Muta’aliyah adalah tampilan yang paling utuh dari semua filsafat. Matangnya Hikmah Muta’aliyah adalah karena kontribusi dari Filsafat-filsafat sebelumnya, bahkan dari filsafat yang paling awal, dari Thales hingga Suhrawardi. Kebesaran Hikmah Muta’aliyah adalah berasal dari sebuah bangunan filsafat yang megah dari berbagai zaman dan peradaban.
Filsafat Hikmah Muta’aliyah adalah tampilan yang paling utuh dari semua filsafat. Matangnya Hikmah Muta’aliyah adalah karena kontribusi dari Filsafat-filsafat sebelumnya, bahkan dari filsafat yang paling awal, dari Thales hingga Suhrawardi. Kebesaran Hikmah Muta’aliyah adalah berasal dari sebuah bangunan filsafat yang megah dari berbagai zaman dan peradaban.




 Sedikit kotradiksi dari Pleyte adalah pertama ia menunjuk kampung Batutulis sebagai lokasi keraton, akan tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah Kelurahan Batutulis yang sekarang.
Sedikit kotradiksi dari Pleyte adalah pertama ia menunjuk kampung Batutulis sebagai lokasi keraton, akan tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah Kelurahan Batutulis yang sekarang.
 Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu:
Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu:













 Selama ini, buku-buku sejarah mengungkap bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia khususnya di Jawa sejak kerajaan Demak. Namun dari berbagai data seperti Babad Majapahit, cerita para sesepuh serta berbagai artefak di situs, candi, makam, dan masjid yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY ternyata menunjukkan bahwa Islam masuk di Jawa jauh sebelum itu dan sejak zaman Majapahit kerajaan ini sudah Islam. Dari data itulah, Herman Sinung Janutama menulis buku yang berjudul “Kesultanan Majapahit: Fakta Sejarah yang Tersembunyi”. Buku tersebut sengaja diluncurkan dalam rangka menyambut Muktamar I Abad Muhammadiyah atas permintaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui latar belakang dan fakta-fata sejarah serta target dari diterbitkan buku tersebut, wartawan Republika, Neni Ridarineni mewawancarai penulis buku tersebut.
Selama ini, buku-buku sejarah mengungkap bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia khususnya di Jawa sejak kerajaan Demak. Namun dari berbagai data seperti Babad Majapahit, cerita para sesepuh serta berbagai artefak di situs, candi, makam, dan masjid yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY ternyata menunjukkan bahwa Islam masuk di Jawa jauh sebelum itu dan sejak zaman Majapahit kerajaan ini sudah Islam. Dari data itulah, Herman Sinung Janutama menulis buku yang berjudul “Kesultanan Majapahit: Fakta Sejarah yang Tersembunyi”. Buku tersebut sengaja diluncurkan dalam rangka menyambut Muktamar I Abad Muhammadiyah atas permintaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui latar belakang dan fakta-fata sejarah serta target dari diterbitkan buku tersebut, wartawan Republika, Neni Ridarineni mewawancarai penulis buku tersebut. Semuanya serba kebetulan saja. Saya orangnya senang berziarah ke situs-situs. Dan ternyata banyak artefak dan bahan-bahan lain yang saya temukan, dari sinilah kemudian saya tulis dalam buku dan tidak menyangka bisa menjadi buku seperti ini. Memang untuk menggali informasi, saya dapatkan dari pernyataan pinisepuh pada tahun 2008. Dia berkata, “siapa bilang Majapahit itu Hindu?”
Semuanya serba kebetulan saja. Saya orangnya senang berziarah ke situs-situs. Dan ternyata banyak artefak dan bahan-bahan lain yang saya temukan, dari sinilah kemudian saya tulis dalam buku dan tidak menyangka bisa menjadi buku seperti ini. Memang untuk menggali informasi, saya dapatkan dari pernyataan pinisepuh pada tahun 2008. Dia berkata, “siapa bilang Majapahit itu Hindu?”









![Kitab Negarakertagama [image source]](http://i1.wp.com/boombastis.com/wp-content/uploads/2015/10/Kitab-Negarakertagama.jpg?resize=700%2C400)
![Kitab Sutasoma [image source]](http://i1.wp.com/boombastis.com/wp-content/uploads/2015/10/Kitab-Sutasoma.jpg?resize=700%2C400)
![Kitab Arjuna Wiwaha [image source]](http://i1.wp.com/boombastis.com/wp-content/uploads/2015/10/Kitab-Arjuna-Wiwaha.jpg?resize=700%2C400)
![Serat Centhini [image source]](http://i1.wp.com/boombastis.com/wp-content/uploads/2015/10/Serat-Centhini.jpg?resize=700%2C400)
![La Galigo [image source]](http://i1.wp.com/boombastis.com/wp-content/uploads/2015/10/Galigo.jpg?resize=700%2C400)

 Salah satu watak dari penyebaran Islam di Nusantara adalah menguatnya keberadaan figur-figur tokoh yang mengarah pada terbentuknya komunitas-komunitas, yang kemudian disempurnakan dengan berdirinya lembaga kesultanan. Menurut penelitian Prof. Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, para penyebar agama Islam di Nusantara telah berhasil membangun kekuasaan Islam dengan mendirikan sekitar 40 kesultanan Islam yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Cirebon (Irianto, 2012:2-3).
Salah satu watak dari penyebaran Islam di Nusantara adalah menguatnya keberadaan figur-figur tokoh yang mengarah pada terbentuknya komunitas-komunitas, yang kemudian disempurnakan dengan berdirinya lembaga kesultanan. Menurut penelitian Prof. Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, para penyebar agama Islam di Nusantara telah berhasil membangun kekuasaan Islam dengan mendirikan sekitar 40 kesultanan Islam yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Cirebon (Irianto, 2012:2-3).






